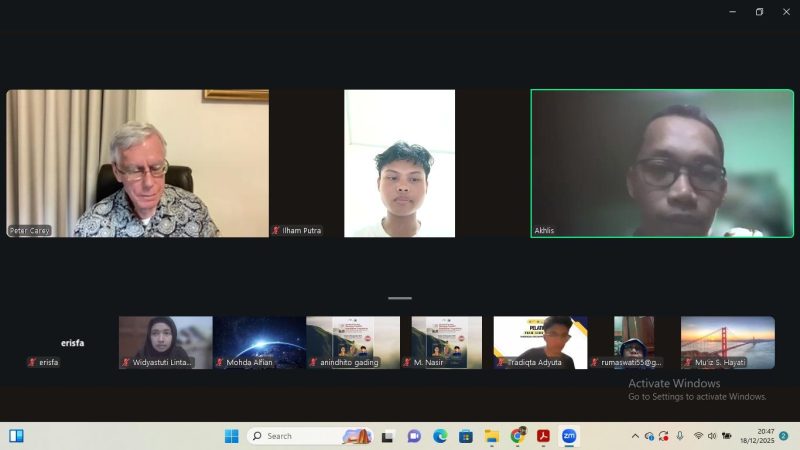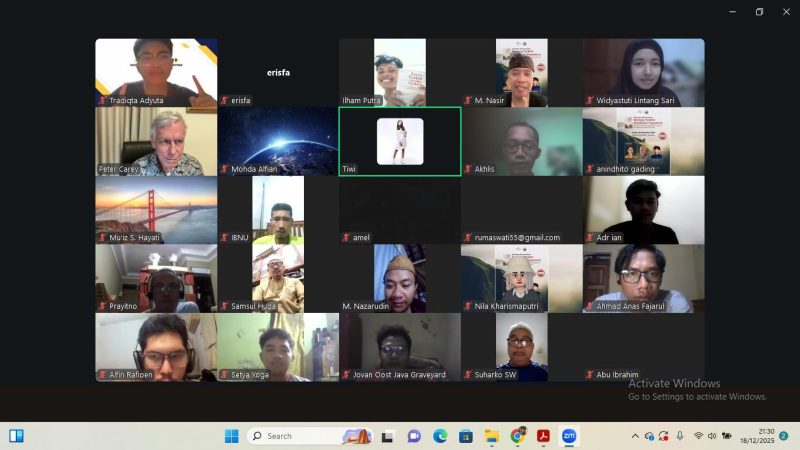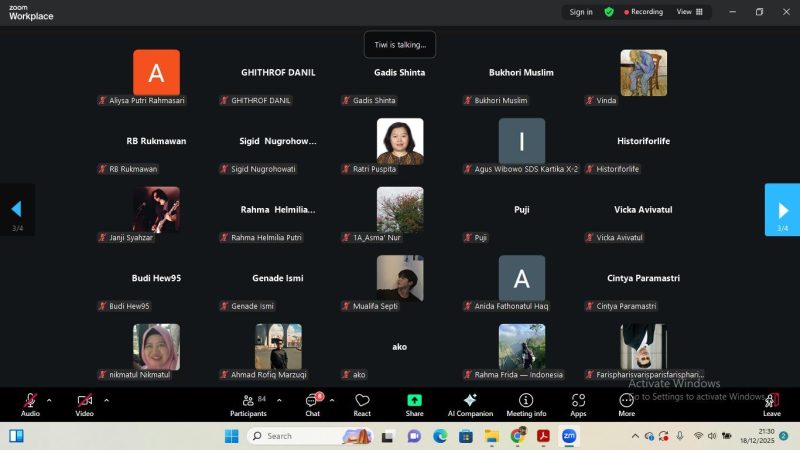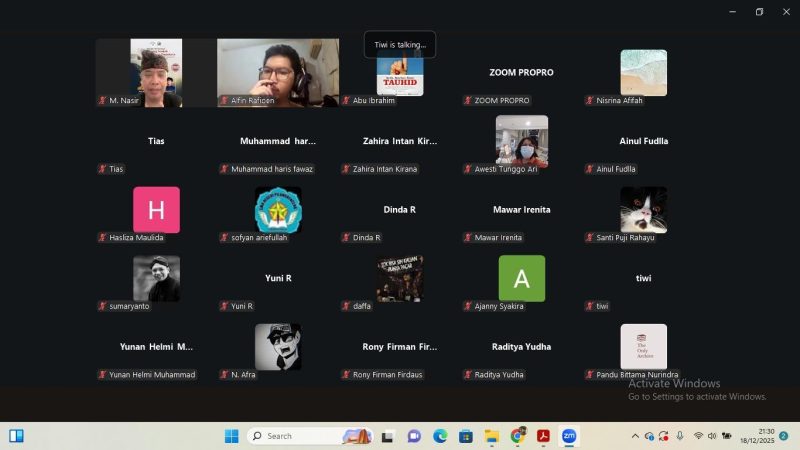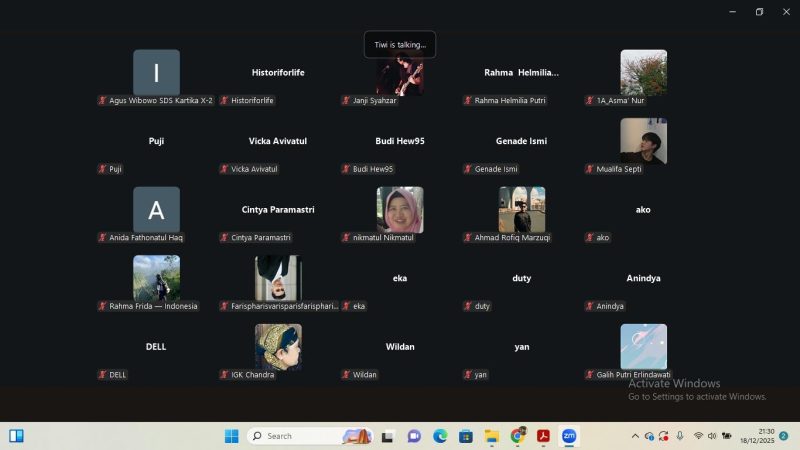Komunitas Temu Sejarah berkolaborasi dengan Laboratorium Pembelajaran Sosial dan Humaniora Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret telah menyelenggarakan kegiatan Diskusi/Bedah Buku Temu Sejarah edisi ke-96 pada Kamis, 18 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara online melalui platform Zoom Meeting pada pukul 20.00-21.30 WIB dan diikuti oleh hampir seratus peserta dari berbagai kalangan kalangan, mulai dari mahasiswa, pegiat sejarah, serta masyarakat umum.
Diskusi buku ini membahas karya berjudul Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta: Riwayat Raden Ronggo Prawirodirjo III dari Madiun, sekitar 1779–1810, karya Akhlis Syamsal Qomar bersama Prof. Peter Carey yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia pada tahun 2022. Kegiatan ini sekaligus diselenggarakan untuk memperingati haul ke-115 Raden Ronggo Prawirodirjo III, salah satu tokoh penting dalam sejarah perlawanan bangsawan Jawa terhadap kolonialisme Belanda.
Kegiatan diskusi dipandu oleh saudara Ilham Putra Pratama selaku Ketua Laboratorium Pembelajaran Sosial dan Humaniora. Adapun narasumber utama dalam diskusi ini adalah Prof. Peter Carey, sejarawan dan Emeritus Fellow Trinity College, Oxford, serta Akhlis Syamsal Qomar selaku penulis buku. Diskusi ini menjadi ruang dialog yang mempertemukan kajian ilmiah, penulisan sejarah lokal, serta minat publik terhadap sejarah kritis.
Dalam pengantar diskusi, moderator menjelaskan bahwa sejarah Madiun kerap dilekatkan dengan narasi perlawanan yang sempit dan identik dengan stigma tertentu. Padahal, dinamika sejarah wilayah tersebut jauh lebih kompleks. Perlawanan Raden Ronggo Prawirodirjo III merupakan salah satu contoh penting perlawanan bangsawan Jawa terhadap kebijakan kolonial, khususnya pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Perlawanan ini berlangsung dalam rentang waktu 20 November hingga 17 Desember 1810 dan berakar pada penolakan terhadap eksploitasi sumber daya hutan jati di wilayah Brang Wetan.
Dalam pemaparannya, Prof. Peter Carey menjelaskan latar belakang genealogis dan posisi Raden Ronggo Prawirodirjo III dalam struktur Kesultanan Yogyakarta. Ia merupakan cucu Sultan Hamengkubuwono I dan berasal dari trah Sukowati yang sejak awal berperan sebagai penopang kekuasaan keraton di wilayah Mancanegara Wetan dengan pusat pemerintahan di Madiun. Diangkat sebagai Bupati Madiun pada usia yang sangat muda, Raden Ronggo pada awalnya dipandang oleh pihak kolonial sebagai bangsawan yang keras kepala. Namun, dalam praktik pemerintahannya, ia justru dikenal dekat dengan rakyat dan berhasil membangun Madiun sebagai wilayah yang makmur dan relatif stabil.
Prof. Carey juga menekankan bahwa perlawanan Raden Ronggo tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan global pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Revolusi Prancis dan Revolusi Industri membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan kolonial, yang kemudian diimplementasikan oleh Daendels di Jawa melalui militerisasi birokrasi, penghapusan simbol status bangsawan tradisional, serta eksploitasi sumber daya alam secara masif. Kebijakan-kebijakan inilah yang memicu ketegangan serius antara elit lokal Jawa dan pemerintah kolonial.
Ketegangan tersebut mencapai puncaknya ketika Raden Ronggo diperintahkan menghadap ke Batavia. Perintah ini dipandang sebagai ancaman langsung terhadap martabatnya sebagai bangsawan Jawa. Raden Ronggo memilih menolak dan mengambil jalan perlawanan terbuka. Perlawanan ini berakhir dengan gugurnya Raden Ronggo di tepi Sungai Bengawan Solo pada 17 Desember 1810. Meskipun secara militer perlawanan tersebut dapat dipadamkan, Prof. Carey menegaskan bahwa kematian Raden Ronggo justru menjadi simbol awal perlawanan bangsawan Jawa terhadap kolonialisme pada abad ke-19 dan memberi inspirasi bagi tokoh-tokoh perlawanan berikutnya, termasuk Pangeran Diponegoro.
Akhlis Syamsal Qomar selaku penulis buku menjelaskan bahwa penulisan Banteng Terakhir Kesultanan Yogyakarta berangkat dari penelitian skripsinya yang kemudian dikembangkan melalui diskusi dan kerja sama dengan Prof. Peter Carey. Sebagai putra daerah Madiun, penulis merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengangkat kembali sosok Raden Ronggo Prawirodirjo III yang selama ini kurang mendapat tempat dalam narasi sejarah arus utama. Dalam proses penulisannya, buku ini menggunakan berbagai sumber, mulai dari arsip kolonial di Arsip Nasional Republik Indonesia hingga sumber tradisional seperti babad, silsilah keluarga, dan naskah keraton.
Dalam diskusi juga dibahas makna julukan “banteng terakhir” yang berasal dari Babad Diponegoro. Dalam simbolisme Jawa, banteng melambangkan kekuatan dan keberanian sebagai pelindung negara. Julukan tersebut menempatkan Raden Ronggo sebagai figur pelindung terakhir Kesultanan Yogyakarta sebelum kekuatan politik keraton semakin dilemahkan oleh intervensi kolonial. Selain itu, disoroti pula karakter perlawanan Raden Ronggo yang inklusif, karena melibatkan masyarakat lintas etnis dan tidak berlandaskan sentimen agama maupun golongan tertentu.
Salah satu bagian menarik dalam diskusi adalah pembahasan tulisan Prof. Peter Carey mengenai peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam memulihkan martabat sejarah Raden Ronggo Prawirodirjo III. Pada tahun 1957, Sultan HB IX secara resmi menyatakan Raden Ronggo sebagai pejuang perintis melawan Belanda dan memindahkan makamnya dari Banyusumurup ke Giripurno, Magetan, bersebelahan dengan makam permaisurinya. Tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk rekonsiliasi sejarah dan kepedulian seorang raja terhadap leluhur serta memori kolektif bangsanya.
Sesi diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta, di antaranya mengenai hubungan perlawanan Raden Ronggo dengan Perang Jawa serta posisi politik Sultan Hamengkubuwono II yang tidak mendukung perlawanan tersebut. Narasumber menjelaskan bahwa Sultan berada dalam posisi dilematis antara menjaga keberlangsungan keraton dan menghadapi tekanan kolonial, sehingga memilih langkah yang dianggap paling aman meskipun berakibat tragis bagi Raden Ronggo.
Melalui kegiatan bedah buku ini, Laboratorium Pembelajaran Sosial dan Humaniora bersama Komunitas Temu Sejarah berharap dapat memperluas wawasan mahasiswa dan masyarakat tentang sejarah lokal secara kritis dan kontekstual. Kegiatan ini sekaligus menegaskan pentingnya membaca sejarah tidak hanya sebagai kisah masa lalu, tetapi sebagai refleksi atas relasi kekuasaan, identitas, dan keberanian moral yang relevan hingga masa kini.