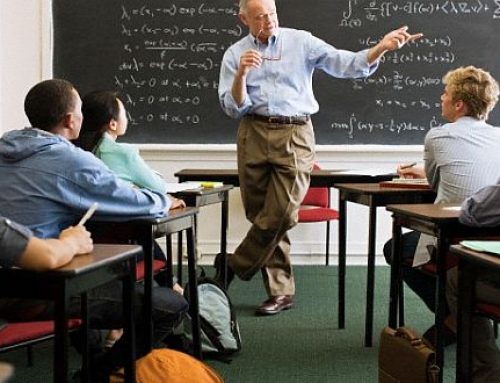Oleh: Dadan Adi Kurniawan
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id
Pendahuluan
Ada banyak indikator suatu masyarakat-bangsa bisa dikatakan “sudah dewasa” atau “belum dewasa”. Dewasa dalam konteks ini bukanlah dewasa dalam arti umur-biologis melainkan cara berfikir, bersikap dan bertindak. Kedewasaan bisa ditunjukkan dari adanya rasa peduli, tanggung jawab, adil, bijaksana, memiliki prinsip, tidak labil, bisa mengelola emosi, tidak egois, hati-hati (tidak grusa-grusu), tidak mudah menyalahkan, berani mengakui kesalahan, berani mengakui kekurangan, berusaha mencari solusi, dan terbuka terhadap kritik maupun saran.
Pertanyaannya, mengapa suatu bangsa tidak kunjung dewasa? Penyebabnya tidaklah tunggal. Dalam tulisan ini, penulis melihat bahwa salah satu penyebabnya dikarenakan oleh dampak sistemik [jangka panjang] dari adanya “penulisan sejarah yang tidak manusiawi”. Disebut jangka panjang karena mentalitas masyarakat-bangsa yang terbangun saat ini merupakan manifestasi tabungan yang telah dibangun sejak lama dengan cara yang kurang tepat. Penulisan sejarah yang tidak manusiawi punya andil dalam membentuk mentalitas itu.
Bangsa yang Tak Kunjung Dewasa
Meskipun belum tua-tua amat, 10 windu lebih merupakan usia yang terbilang tidak singkat. Dengan usia demikian, “mestinya” Indonesia sudah mampu menjadi negara yang beranjak dewasa (bijak). Namun itu hanyalah angan-angan, hanyalah “mestinya”. Das sollen sering bertolak belakang dengan das sein. Apa yang diidealkan seringkali berkebalikan dengan kenyataan. Dalam banyak kasus, masyarakat-bangsa kita belum cukup dewasa. Justru yang lebih menonjol ialah mentalitas pecundang, mentalitas pincang, mentalitas parsial. Apa buktinya? Berikut penulis paparkan beberapa contoh dari sekian banyak fakta di masyarakat.
1. Mentalitas Tak Siap Kalah dan Mengakui Kekalahan
Contoh pertama adalah warga sepak bola yang pendendam. Tentu tidak berlaku untuk semua, tetapi bukan berarti hanya segelintir. Karena posisinya kalah, yang diutamakan bukanlah sportivitas melainkan permainan kasar dan hasrat ingin menciderai lawan. Tak hanya pemainnya, sering dijumpai suporter sepak bola yang belum siap menerima tim kesayangannya kalah. Karena belum siap menerima kekalahan, para suporter meluapkan amarah dengan cara anarkis, tawuran, bentrok, pembulian, dan sejenisnya. Perseteruan dan rivalitas ekstrem antarsuporter juga kerap kali merembet ke luar lapangan, di mana antar suporter tidak bisa bebas memakai kaos sepak bola di wilayah-wilayah tertentu.
Sepak bola yang mestinya menjadi ajang mempersatukan dan menjunjung nilai-nilai sportivitas justru sering menjadi ajang mempertontonkan politik identitas dan keterceraiberaian. Memperlihatkan mentalitas pecundang, mentalitas egois yang tidak siap kalah dan mengakui kekalahan. Layaknya anak kecil yang merengek lalu menangis ketika keinginannya tidak dikabulkan. Tidak ada yang salah dengan sepakbola sebagai salah satu jenis olahraga, tetapi kesalahan terdapat pada cara berfikir dan mentalitas oknum-oknum yang belum kunjung dewasa tersebut. Dari mana datangnya mentalitas yang demikian? Sejarah punya andil dalam membentuk mentalitas mayarakat-bangsa.
2. Tidak Sesakti dan Sesuci yang Dibayangkan
Narasi tentang tokoh-tokoh seringkali digambarkan terlampau sakti layaknya bukan manusia, padahal fakta kerasnya jelas-jelas menyanggah penggambaran itu. Sebagai contoh, raja sering dikisahkan sebagai manusia suci dan wakil (tangan kanan) Tuhan. Setiap sabdanya adalah keadilan, keluhuran dan kebijaksanaan. Dalam kenyataannya setiap manusia sesakti apapun tetap ada batas hidupnya, pun setiap raja yang sakti mandraguna juga akhirnya meninggal. Legitimasi “wakil Tuhan” ini pun sebenarnya bisa dipertanyakan mengingat semua manusia di bumi sebenarnya merupakan wakil Tuhan yang ditugaskan untuk menjaga bumi agar tetap lestari.
Di sisi lain, raja yang katanya suci dan bijaksana nyatanya juga ada yang bengis, keji, dan ambisius serta menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Yang katanya sakti nyatanya juga meminta bantuan pada kubu lain termasuk ada yang meminta bantuan pada kubu VOC maupun kolonial Belanda. Gemerlapnya rebutan kekuasaan dunia juga dibuktikan dengan banyaknya perang saudara. Kakak adik (anak raja) saling membunuh, pangeran berseteru dengan pangeran, paman bertikai dengan keponakan, trah berkonflik dengan trah, dan sejenisnya. Entah ada berapa puluh kisah tentang perebutan kekuasaan di lingkungan kerajaan-kerajaan di Indonesia, mulai dari era kuno hingga baru, mulai kerajaan-kerajaan di Jawa maupun di luar Jawa. Buku-buku sejarah mencatat berbagai konflik hebat bahkan berdarah di keluarga raja pernah terjadi seperti pada era Kerajaan Mataram Kuno, Medang, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak, Banten, Cirebon, Pajang, dan Mataram Islam (terutama sejak era Amangkurat I). Bahkan di era modern dewasa ini, konflik suksesi yang pelik masih diperlihatkan secara gamblang di internal Keraton Kasunanan Surakarta.
Jika dicermati, sesuci dan sesakti-saktinya manusia tetaplah manusia yang memiliki “sisi-sisi manusiawi” pada umumnya. Tetap dijumpai manusia-manusia gila hormat, manusia gila gelar dan jabatan, manusia gila harta, manusia yang tidak suka jika lainnya sukses, rasa tidak suka jika merasa disingkirkan, rasa tidak terima dan ingin balas dendam, rasa tidak puas atau kurang sehingga ingin menambah, rasa tidak rela jika kekuasaan jatuh pada keturunan trah yang lainnya, rasa kawatir jika besuk terbunuh, rasa cemburu jika perempuan yang diincar juga disukai orang lain, dan kelaziman-kelaziman lainnya. Potret-potret inilah yang jarang ditekankan kepada publik pembaca terutama peserta didik di sekolah. Yang dipelajari sering kali lebih ke perang-perang, kepahlawanan, kemasyuran-kemasyuran, kejayaan, dan pencapaian-pencapaian besar lainnya.
3. Mengutamakan Citra – Mengingkari Jati Diri
Proyek-proyek penulisan sejarah organisasi, lembaga atau institusi acapkali enggan menuliskan berbagai kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Mereka “sengaja menutupi” berbagai kekurangan dan kelemahan demi terjaganya citra positif lembaga. Ada bagian-bagian dari perjalanan sejarah yang sengaja tidak ditampilkan karena takut menjadi aib yang sewaktu-waktu bisa dijadikan bahan olok-olokan masyarakat. Perjalanan suatu lembaga, instansi dan organisasi terkadang tidak lepas dari adanya konflik internal yang disebabkan karena perbedaan paham, pandangan, ideologi, atau prinsip antaranggota atau para penggedenya. Konflik internal itu ada yang dalam tingkat kecil, sedang dan besar (meruncing). Ada fase-fase di mana lembaga, instansi atau organisasi mengalami ketidakkompakan, perpecahan dan kemunduran. Ada fase-fase di mana suatu lembaga, instansi atau organisasi terkadang mengambil kebijakan yang keliru. Juga anggota lembaga atau organisasi yang pernah terlibat kasus.
Sayangnya tidak semua lembaga, instansi dan organisasi “berani menampilkan secara jujur” berbagai kekurangan dan kesalahan tersebut sebagai sebuah satu kesatuan perjalanan hidup yang sebenarnya sangat manusiawi. Padahal keberanian mengakui masa lalu adalah bentuk kejujuran agar siap melangkah ke depan. Berani mengakui masa lalu adalah bentuk kemenangan di masa kini dan yang akan datang. Sayangnya masih sangat sedikit lembaga, instansi atau organisasi yang berani dan jujur akan jati dirinya. Mentalitasnya mesih termakan oleh “bayang-bayang citra yang semu”. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masih banyak lembaga atau institusi “bermental pecundang” karena tidak berani mengakui kekurangan diri, hanya siap menerima fakta dan citra yang baik-baik saja. Sejatinya yang demikian merupakan wujud “pengingkaran keutuhan jati diri”.
4. Mudah Sensitif dan Berlebihan Terhadap Isu Kekirian
Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pembredelan buku-buku yang bertema kiri serta penghentian sepihak acara-acara diskusi atau seminar yang bertema “kekirian” (komunisme, sosialisme, marxisme, dan sejenisnya). Apakah begini caranya pemerintah mengajarkan masyarakatnya menjadi dewasa? Apakah tindakan pembredelan dan penghentian sepihak ini menununjukkan sikap dewasa pemerintah? Harusnya pemerintah mampu membedakan secara jernih apa bedanya “belajar” dan apa bedanya “menggerakkan”. Belajar kekirian tidaklah sama dengan menggerakkan kekirian. Kekirian itu perlu dipelajari supaya masyarakat-bangsa ini bisa paham riwayatnya, bisa paham kekurangan dan kelebihannya, bisa paham bahayanya, dan bisa paham cara menangkalnya. Masyarakat juga berhak tahu alasan mengapa sesuatu bisa dianggap kiri dan mengapa kiri dicap membahayakan. Masyarakat harus melek literasi, bukan tunduk mentah-mentah pada indoktrinasi.
Untuk mencapai kedewasaan (kesadaran tinggi), masyarakat tidak boleh hanya sampai pada level doktrin dan langsung menerimanya mentah-mentah. Mempelajari kekirian tidak berarti ingin menghidupkan dan menggerakkan kekirian itu sendiri. Belajar tentang PKI bukan berarti ingin membentuk dan menghidupkan PKI kembali. Belajar fasisme bukan berarti ingin mendirikan negara fasis. Sama halnya ketika seseorang ingin belajar tentang setan, bukan berarti orang tersebut ingin menjadi setan dan meneladani sifat-sifatnya, melainkan supaya bisa mengetahui dan menanggulangi tipu daya setan. Belajar tentang sejarah korupsi bukan berarti ingin korupsi, melainkan supaya tahu pintu-pintu masuk bisa terjadi korupsi itu dari mana saja, cara menangkalnya seperti apa. Sekali lagi harus bisa dibedakan antara belajar (sebagai sebuah kajian akademis – ranah kognitif) dan gerakan. Pemerintah (lewat aparat yang ditugaskan) mestinya tidak perlu baperan, dikit-dikit bawaannya ingin membredel dan menghentikan sepihak.
5. Nasionalisme Kebablasan
Pada dekade-dekade awal setelah kemerdekaan, Soekarno menilai bahwa bangsa Indonesia masih banyak yang “bermental tempe” (lembek) sebagai akibat kuku kolonialisme yang menancap berkepanjangan. Oleh karenanya diperlukan penguatan nasionalisme agar tumbuh rasa percaya diri dan tidak minder di hadapan bangsa-bangsa lain. Salah satu alat strategisnya melalui narasi sejarah. Anak-anak kecil, remaja hingga dewasa disuguhi narasi sejarah yang heroik, patriotik dan nasionalistik dalam kerangka membangun “nasionalisme” (rasa cinta dan bangga pada tanah air). Nasionalisme merupakan salah satu “semen” yang sangat diperlukan dalam membangun, merekatkan, dan memperkokoh negara.
Sayangnya narasi sejarah dalam rangka pemupukan nasionalisme sering kali bersifat tidak manusiawi alias dilebih-lebihkan (meskipun tujuannya baik). Kisah-kisah sejarah dibuat begitu ultraheroik, ultrapatriotik, dan ultranasionalistik. Tokoh-tokoh digambarkan sebagai sosok sempurna, sakti, selalu berhasil, dan tanpa celah sedikitpun. Para pahlawan diceritakan sebagai manusia yang selalu berjuang siang dan malam, selalu kompak, tanpa lelah, tanpa pamrih, dan tanpa rasa takut sedikit pun. Sekilas memang sangat luar biasa dan pastinya menggugah jiwa nasionalisme pembacanya, tetapi narasi sejarah yang demikian tidaklah manusiawi dan cenderung mengabaikan realitas-realitas aslinya. Narasi sejarah terkadang kebablasan karena terjebak pada kepentingan politik-iedologis sehingga mengaburkan fakta-fakta manusiawi.
Penulisan Sejarah yang Manusiawi
Sejarah manusiawi sebagai sebuah pendekatan menekankan pada upaya rekonstruksi kisah kehidupan masa lalu yang “sewajarnya”. Makna sewajarnya adalah tidak dilebih-lebihkan, tidak direkayasa agar terlihat sempurna, menyajikan kisah apa adanya tanpa dibuat-buat, tanpa ditutup-tutupi sebagiannya. Menerima baik buruk dan hitam putih sebagai “kodrat kehidupan” dari Yang Maha Kuasa. Ada pencapaian, ada kegagalan, ada kelebihan, ada kekurangan, ada kebaikan, ada keburukan, ada kebenaran, ada kesalahan. Memiliki putih bukan berarti tidak memiliki hitam. Sering sukses bukan berarti tidak pernah gagal dan tidak pernah berbuat kesalahan. Memiliki banyak kelebihan bukan berarti tidak punya kekurangan.
Penulisan sejarah yang manusiawi mengajarkan akan arti “ketidaksempurnaan”. Peserta didik yang sejak kecil diajarkan tentang “ketidaksempurnaan” akan menjadi pribadi atau kelompok yang lebih mudah menerima dan tidak mudah kecewa pada kenyataan. Banyak hal di dunia ini tidak bisa dipaksakan sempurna dan selalu berhasil sekalipun manusia telah berusaha sekuat tenaga. Bahwa di balik kejayaan juga ditemui kisah-kisah miris. Di balik nama-nama besar yang katanya otoriter juga terselip sisi-sisi humanis. Di balik ketokohannya yang besar dan kondang, mereka tetaplah manusia biasa meski ia memiliki keunggulan di atas rata-rata. Penulisan sejarah yang manusiawi mengajarkan agar kita tidak mudah “mengkultuskan” atau “mendewakan” sesuatu (utamanya tokoh) secara membabi buta. Tidak pula mudah mengutuk dan menyumpah serapah semaunya.
Dengan menekankan pendekatan sejarah manusiawi, secara perlahan akan terbentuk pola pikir yang kritis, rasional, dan proporsional (adil, sesuai porsi) dalam melihat setiap hal atau subyek yang dipelajarinya. Pemikiran kritis, rasional, dan proporsional sangat dibutuhkan untuk melahirkan “potret berfikir yang jernih”. Lagi pula cara mencintai suatu bangsa tidak harus dengan suguhan kisah-kisah yang serba menampilkan kecemerlangan, pengorbanan, kemenangan, dan kejayaan. Cara terbaik mencintai bangsa ini adalah menerima segala kelebihan dan segala kekurangan serta kesalahan yang pernah diperbuatnya. Tak perlu disembunyi-sembunyikan, tak perlu diingkari. Tidak perlu dilebih-lebihkan, tidak perlu dikurangi. Salah dibilang salah, benar dibilang benar. Siap menerima kemenangan, juga kekalahan. Tidak hanya berani mengkritik ke luar, tetapi juga berani mengkritik ke dalam.
Sejarah tidak harus menampilkan kisah-kisah secara ultraheroik, ultrapatriotik, dan ultranasionalistik yang serba sempurna dan menggebu-gebu, karena itu akan menjadi “watak” dan “bom waktu”. Biarlah masyarakat dan anak bangsa belajar kepahlawanan lengkap beserta sisi-sisi kemanusiawiannya. Biarlah masyarakat dan anak bangsa belajar berbagai kecemerlangan bangsa ini lengkap dengan kegagalannya. Nasionalisme tidak harus selalu dimaknai anti asing, memaknai negara asing itu pasti penjajah kejam, bahwa Barat itu selalu buruk dan Timur itu pasti semuanya luhur. Sadar tidak sadar, penulisan sejarah yang sarat akan kepentingan ideologis-praktis dan akhirnya mengesampingkan sisi-sisi kemanusiawian, akan melahirkan mentalitas yang parsial (tidak utuh). Mentalitas masyarakat-bangsa yang mudah menghakimi, bersumbu pendek, dan memukul rata berbagai hal.
Sesuai namanya, sejarah manusiawi menempatkan segala sesuatunya secara “manusiawi” (koridor kewajaran) sesuai realitas di lapangan. Tak dilebih-lebihkan, tak dikurangi. Belajar menerima berbagai kesalahan dan kekurangan di masa lalu. Sama sekali bukan mengajarkan pesimis, melainkan menempatkan kisah secara manusiawi. Justru di situlah letak sejarah sebagai “guru kehidupan”. Sejarah adalah guru terbaik yang telah membuktikan dan menegaskan bahwa di dunia ini “tidak ada yang sempurna”. Paradigma ini akan mengantarkan manusia pada tingkat kedewasaan yang lebih matang.



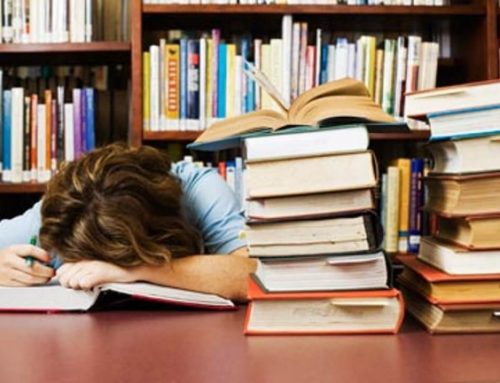

![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)









![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)