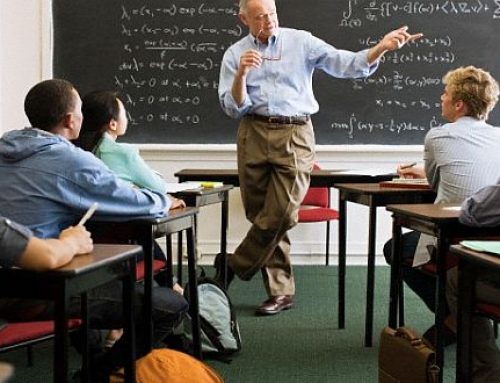Oleh: Dadan Adi Kurniawan
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id
Rasa Benci Menguras Energi
Sesuai kodratnya, setiap manusia ditakdirkan memiliki rasa suka dan rasa tidak suka. Kedua rasa ini bisa memunculkan kebahagiaan tetapi juga bisa melahirkan kekecewaan dan kesengsaraan. Mengapa bisa demikian? Semua berawal dari “rasa yang berlebihan” (berlebihan dalam menyukai atau berlebihan dalam membenci). Rasa suka dan rasa tidak suka yang berlebihan dan membabi buta bisa melahirkan sikap “fanatisme” (fanatisme menyukai dan fanatisme membenci). Fanatisme muncul karena “pintu rasionalitas” telah tertutup sebagai akibat sumber informasi dan pengetahuan yang masuk “sangat terbatas dan sepihak” (hanya dilihat dari satu perspektif, satu pandangan, satu paham, satu kelompok, satu aliran, atau satu mahdzab saja). Karena fanatisme buta (berawal dari rasa suka atau rasa benci tidak terkontrol), seseorang sering kali “tidak tahu atau tidak mau tahu” terhadap pendapat, pandangan atau perspektif dari kacamata lain yang berbeda.
Dalam prosesnya, rasa suka dan rasa tidak suka yang berlebihan akan banyak “menguras energi” yakni menguras segala daya, kekuatan dan kemampuan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Rasa suka dan tidak suka yang berlebihan akan mendorong seseorang melakukan “berbagai cara” untuk mencapai kepuasan batin. Sayangnya segala sesuatu terkadang tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Sebagian upaya dan pengorbanan yang telah terkuras habis hanya melahirkan kekecewaan berat, rasa sakit yang mendalam, dan rasa dendam (rasa tidak terima). Itulah mengapa ada filosofi bijak agar “memuja sepantasnya, membenci secukupnya”. Kata ‘sepantasnya’ dan ‘secukupnya’ menegaskan bahwa segala hal di dunia ini memang idealnya disikapi “sewajarnya”, tak perlu berlebihan. Yang berlebihan itu biasanya tidak baik. Oleh karenanya, kalau tidak suka pada orang atau sesuatu, ya sewajarnya saja. Pun demikian kalau suka atau kagum pada seseorang atau sesuatu, juga sewajarnya saja.
“Ilmu sewajarnya” merupakan ilmu mahal dan kelas tinggi yang bisa diterapkan dalam segala lini dan bidang kehidupan, tak terkecuali di lingkungan bekerja dan tempat kita belajar. Terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang sering bikin emosi dan menguras energi. Tiap hari beradu pikir, lisan dan perasaan yang melelahkan. Tetapi jika kita resapi, bisa jadi itu disebabkan karena penyikapan kita saja yang belum tepat. Mungkin kitanya sendiri yang sering ikut campur urusan orang lain. Kita sendiri yang sedikit-sedikit mengomentari urusan orang lain. Kita sendiri yang memang mudah memendam rasa benci pada orang lain, sedikit-sedikit tidak suka pada orang lain, sedikit-sedikit disimpan dalam hati dan pikiran. Akhirnya pikiran, hati, lisan dan tindakan kita “terforsir keras” untuk mengurusi masalah tersebut. Tanpa disadari kita telah mengeluarkan banyak energi untuk “meladeni” rasa tidak suka atau rasa benci kita pada orang lain.
Dalam filosofi Stoik ditekankan bahwa seberapa besar “pengaruh eksternal” sebenarnya “keputusan internal”-lah yang menentukan. Kendali penuh ada pada diri kita masing-masing dalam menyikapi setiap permasalahan. Mudah marah (naik pitam), biasa saja (sedengan), atau cuek sekali (tidak gubris), itu semua tergantung diri kita masing-masing, apakah pintu hati/pikiran “diizinkan” terbuka sehingga muncul perasaan tersinggung, merasa tersakiti, merasa menjadi korban, merasa tidak terima, dan sejenisnya. Tersinggung atau biasa saja, suka atau benci, cuek atau peduli, menerima atau tidak menerima, semuanya terletak pada “izin” pemiliknya. Kendali penuh “penyikapan” ada pada diri si perespon. Kendali ini harus terus dilatih. Tidak hanya setahun dua tahun, melainkan sepanjang manusia hidup. Ini terjadi karena rasa suka dan tidak suka (yang berkaitan dengan hati dan pikiran) akan selalu ada selama manusia masih bernafas.
Melatih Rasa Benci yang Proporsional
Sebagai manusia biasa, sampai kapan pun dan sesaleh apa pun, rasa tidak suka itu pasti akan tetap ada dan akan muncul sewaktu-waktu saat kita menyikapi suatu keadaan/permasalahan. Meskipun bisa muncul sewaktu-waktu bukan berarti “rasa itu” tidak bisa dikelola. Manusia bisa belajar, belajar dan terus belajar mengelola pikiran dan perasaan. Salah satu yang bisa diupayakan adalah belajar bagaimana mengelola rasa tidak suka supaya bekerja secara “proporsional” (adil, sesuai porsinya). Memang tidak gampang, tetapi bukan berarti tidak bisa diusahakan.
Sebagai contoh misalnya: kita pernah sekolah selama 3 tahun. Di sekolah itu kita punya guru. Selama sekolah kita mendapat banyak ilmu berharga dari guru tersebut, sebagai misal ilmu membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi. Ilmu itu sangat bermanfaat di kemudian hari ketika kita sekolah lanjut dan bahkan ketika sudah bekerja. Sekian puluh tahun kemudian guru tersebut terkena kasus, semisal selingkuh. Pertanyaannya adalah apakah kita kemudian harus membenci ia sepenuhnya? Tak lagi mau berteman dengannya? Tak mau lagi berbicara dengannya? Tak mau lagi mengakui sebagai guru kita? Itu tidak adil. Kita perlu dudukkan permasalahan sesuai porsinya. Kita boleh benci bahkan mengutuk keras perilaku guru tersebut karena telah melakukan tindakan hina dan tercela. Namun demikian, kita tidak boleh “mengingkari” jasa baiknya di masa lalu. Bagaimanapun ia telah banyak memberikan ilmu berharga pada kita. Tindakan selingkuh harus dipisahkan dengan sisi-sisi lain yang tak ada sangkut pautnya.
Contoh lain misalnya, kita punya teman kuliah. Selama kuliah ia sering membantu kita mengatasi tugas-tugas berat, membantu kita mencari referensi yang sulit, mengarahkan kita dengan telaten manakala kita bingung bergerak sendirian, membayari ongkos foto copy ketika kita benar-benar tidak punya uang, serta selalu ada dan memberi semangat ketika kita sedang terhantam badai. Suatu waktu, teman kita tersebut tersandung masalah yakni terbukti mencuri helm di kampus. Pertanyaannya, apakah kita kemudian benci dan tak mau lagi mengakui ia sebagai teman? Tak mau lagi ketemu dan bertegur sapa? Di sini kita harus proporsional dalam menilai dan bersikap. Satu masalah harus didudukkan secara adil pada tempatnya. Tak perlu merembet dan membawa-bawa masalah pada hal-hal lainnya. Cukup benci dan mengutuk keras tindakan mencuri helm karena itu masuk tindakan kriminal. Namun bukan berarti harus “mengingkari” dan “melupakan” jasa-jasa baiknya di masa lalu. Kriminalitas merupakan sisi lain hidupnya, tetapi kebaikan-kebaikan yang ia lakukan juga bagian dari sisi lain yang tak terpisahkan. Manusia tak ada yang sempurna.
Dalam Putih tak Semuanya Putih, dalam Hitam tak Semuanya Hitam
Memukul rata setiap masalah berarti tidak obyektif, tidak adil, mengingkari fakta (realitas). “Rasa benci” sering kali membawa seseorang gelap mata, memandang semuanya serba hitam. Melihat hamparan batu kerikil seakan tajam semua, padahal aslinya banyak juga kerikil halus. Ribuan kebaikan terlupakan oleh satu kesalahan. Semua itu disebabkan karena rasa benci membabi buta, tak menyisakan kejernihan untuk berfikir secara adil dan rasional. Tidak mendudukkan perkara pada porsinya. Mudah percaya pada informasi-informasi satu pihak yang belum tentu kebenarannya. Hasratnya mengedepankan rasa benci, rasa tidak suka, dan bahkan rasa ingin merendahkan. Pikiran, hati dan perasaan mengalami kepincangan.
Ada orang yang gayanya super sombong plus songong, tetapi harus diakui bahwa di sisi lain ia memang sangat pandai secara intelektual. Ada orang ketus dan ucapannya tajam tetapi di sisi lain apa yang disampaikannya adalah kebenaran. Ada orang suka marah-marah, tetapi di sisi lain bertipikal peduli dan suka menolong orang yang membutuhkan. Ada tipe orang cerewet tetapi sebenarnya tulus dan baik hati. Ada orang tidak disiplin tetapi sebenarnya cerdas. Ada orang keras kepala tetapi sangat bertanggung jawab. Ada orang sulit ditemui tetapi sekalinya diberi pekerjaan selalu beres. Ada orang sedikit urakan tetapi jujur dan disiplin. Ada pemuka agama yang cara ceramahnya keras dan kasar tetapi substansinya benar. Kita boleh tidak cocok dengan “caranya” ia berceramah, tetapi bukan berarti mengingkari “kebenaran isi” yang ia sampaikan.
Masih banyak contoh karakteristik lain yang kontradiktif dalam setiap diri manusia. Manusia memang makhluk unik, sulit dipahami. Setiap manusia ditakdirkan memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan harus ditangkap sebagai kekurangan tanpa meniadakan kelebihan. Pun sebaliknya, kelebihan harus ditangkap sebagai kelebihan tanpa mengingkari adanya kekurangan. Dalam putih tak semuanya putih, dalam hitam tak semuanya hitam. Dua hal itu sangat mungkin berjalan beriringan dalam satu waktu.
Iri-Dengki Sebagai Mentalitas Pecundang
Selalu ada orang-orang yang tidak suka atas pencapaian orang lain di sekitarnya. Ketidaksukaan tersebut ada yang dilakukan secara terang-terangan, ada pula secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi (di belakang). Rasa tidak suka terhadap pencapaian baik orang lain itulah yang disebut “iri” atau “sirik” (bukan syirik = menyekutukan Tuhan). Ketidaksukaan yang terus berlanjut akan naik tingkat menjadi “rasa benci”. Rasa benci yang telah menumpuk berpeluang besar membuat seseorang melakukan berbagai cara agar kesuksesan, kebahagiaan, kepemilikan, dan berbagai pencapaian baik orang lain sirna. Rasa benci yang diikuti dengan berbagai cara-upaya buruk inilah yang disebut “dengki”.
Iri dengki di tempat kerja misalnya melakukan fitnah ke sesama rekan kantor agar dipindah, dikeluarkan atau diturunkan jabatannya. Cari muka di hadapan pemimpin untuk menyingkirkan dan merendahkan teman kerja lainnya. Tidak suka teman kerja naik pangkat melebihi pangkatnya. Tidak suka jika pekerjaan teman berjalan dengan lancar dan mendapatkan bonus. Berusaha menjatuhkan nama baik teman agar usahanya bangkrut dan gulung tikar. Mempengaruhi rekan-rekan kerja lainnya supaya membenci dan menjauhi teman yang dibencinya. Tidak suka bila rekan kerja bisa beli ini beli itu yang lebih mewah daripada miliknya. Dan masih banyak lainnya.
Tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat dan tempat kerja, nyatanya sifat iri dan dengki juga sering dijumpai di lingkungan tempat belajar (termasuk kampus). Temuan di lapangan menunjukkan bahwa ada mahasiswa-mahasiswi yang memiliki “mentalitas pecundang” (loser). Mentalitas pecundang ini ditunjukkan dengan sifat iri dan dengki terhadap teman lain yang memiliki kemampuan dan pencapaian lebih dibandingkan dengannya, kelompoknya atau gengnya.
Sebagai contoh misalnya tumbuh rasa tidak suka ketika ada teman lain yang lebih aktif saat pelajaran di kelas, nilainya lebih bagus, IPK-nya lebih tinggi, sering menang lomba, punya banyak karya, banyak dikagumi teman-teman lainnya, lebih dekat dengan dosen, kendaraannya lebih bagus, dan sebagainya. Ketidaksukaan atas capaian orang lain sering kali berujung pada lahirnya sindiran, ejekan, fitnah, kerenggangan, dan konflik horizontal. Pertemanan menjadi retak dan rusak gara-gara pengelolaan “rasa tidak suka” yang berlebih (membabi buta). Yang demikian merupakan mentalitas yang payah. Mentalitas yang membuat bangsa Indonesia sulit maju. Iri dengki atas prestasi orang lain adalah wujud seorang pecundang, seseorang yang sejatinya “kalah” dalam suatu medan pertempuran. Sejatinya setiap orang memiliki rejeki dan garis sukses masing-masing.
Mentalitas yang mestinya dibangun adalah “mentalitas sehat” (sportif). Kelebihan dan capaian teman mestinya dijadikan cambuk untuk sadar dan berbenah diri bahwa dirinya masih tertinggal. Sadar bahwa dirinya terjebak pada rasa nyaman dan leha-leha. Berbagai kelebihan teman mestinya dijadikan inspirasi guna membangun jiwa kompetisi yang sehat. Berlomba-lomba untuk sama-sama maju, berkembang, dan saling mengingatkan. Yang pandai tak perlu congkak dan menjatuhan teman lainnya dan yang tertinggal pun harus lebih semangat belajar untuk mengejar kekurangan. Inilah yang dinamakan mahasiswa dengan “mentalitas pemenang” yakni manusia yang berjuang dengan cara-cara sportif, respect, positif, saling menghargai dan tidak menjatuhkan orang lain. Tidak merasa paling pintar dan ingin dilihat paling menonjol. Tidak menggurui dan meremehkan teman-teman lainnya. Mentalitas Pemenang adalah mentalitas orang-orang yang sama-sama mau belajar menjadi “manusia pembelajar”. Tidak irian dan dengkian. Keberhasilan dan prestasi teman berarti “berkah untuk lainnya” juga karena bisa menjadi sumber inspirasi bagi sesama.
Sesama teman mestinya saling belajar, saling berkolaborasi dan bersinergi. Jika ada teman yang sering mengenalkan buku baru, itu tandanya teman-teman lainnya sedang diajak untuk menaikkan level literasi. Bukan malah dirasani “sok pinter, sok yes”. Jika ada teman yang sering menginformasikan lomba-lomba, tandanya ia sedang mengajak teman-teman lain untuk menantang dan menjajal kemampuan diri. Jika ada teman yang suka ngajak baca-baca di perpustakaan, tandanya ia ingin membangun iklim dan budaya positif.
Dalam batasan tertentu perbanyaklah teman, jangan terlalu nge-geng (membentuk circle khusus yang ekslusif). Saling membentuk circle-circle (geng) dalam satu kelas merupakan budaya yang kurang elok. Lebih banyak minusnya ketimbang kebermanfaatannya. Dulu Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah Taman Siswa bercorak “nasional” dalam rangka menampung semua kelompok, kalangan, suku, ras, agama, dll. Tujuannya supaya bangsa ini bisa berbaur dengan semuanya. Beliau dan rekan-rekan seperjuangannya justru menghindari adanya circle-circle kelompok/golongan serta menghindari terbentuknya “sekolah eksklusif” (basis suku tertentu, agama tertentu, partai tertentu, golongan tertentu, dan sejenisnya).
Seorang yang “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri) adalah orang yang merdeka, orang yang bisa ke sana ke mari, diterima dan mampu beradaptasi dengan semua lapisan kalangan pertemanan. Ia sengaja tidak hanya berdiri di satu circle pertemanan saja. Terkadang ke perpustakaan dengan teman-teman A, kadang ke makan siang di kantin dengan teman-teman B, kadang nongkrong bersama dengan teman-teman C, kadang main futsal dengan teman-teman D, kadang menemui dosen dengan teman-teman E, dan sebagainya.
Manusia berdikari juga tidak pilih-pilih dalam membentuk kelompok tugas. Ia siap dipasangkan dengan siapapun, kapanpun dan dalam mata kuliah apapun. Ia sadar bahwa modal ini penting ketika nanti terjun ke masyarakat dan dunia kerja. Di lingkungan kerja, kita harus terbiasa siap bertemu dengan siapa saja (orang-orang baru dengan berbagai karakter yang berbeda). Manusia berdikari adalah manusia yang terbuka bagi semua, karena semua adalah anak bangsa. Ia menjalin pertemanan dengan semua supaya memiliki banyak relasi. Ia berteman dengan banyak teman supaya bisa belajar menghadapi banyak karakter. Dengan begitu, ketika lulus nanti, ia siap menghadapi dunia yang sesungguhnya. Memang untuk level pertemanan yang lebih intim (dalam hal positif) perlu lebih “selektif”, karena lingkungan pertemanan sangat mempengaruhi pertumbuhan karakter dan budaya hidup seseorang.
Jika ada teman yang suka mengingatkan teman lain agar jujur dan disiplin (sebagai misal masuk kelas tepat waktu dan tidak suka nitip presensi), tandanya ia peduli, menjaga budaya kelas tetap berada di “rel yang lurus”. Jika ada teman menegur teman lain yang sering berkata kotor, itu tanda jika orang tersebut masih ada rasa peduli pada hal kebaikan. Memang dewasa ini banyak sekali mahasiswa suka menyelipkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, bahasa hewan, dan berbagai bahasa gaul negatif dalam pergaulan sehari-hari (baik di kelas maupun di tongkrongan). Dikiranya terlihat gaul dan keren, padahal sebaliknya, miris dan memprihatinkan. Kalangan yang katanya berpendidikan tinggi, tetapi tidak setinggi tutur lisannya yang rusak.
Contoh lainnya lagi misalnya jika ada mahasiswa yang melaporkan pada dosen bahwa temannya berbohong (semisal izin tidak masuk karena sakit tetapi aslinya sedang jalan-jalan atau ada kepentingan lain yang tidak mendesak), itu mestinya bersyukur karena dalam satu kelas masih ada orang yang berani menegakkan budaya kejujuran. Contoh lagi, jika ada teman yang akhirnya terpaksa melaporkan ke dosen karena ada yang hanya “numpang nama” (setelah sebelumnya sudah beberapa kali diingatkan tetapi tetap ngeyel), itu memang sudah menjadi hal yang seharusnya. Ia sedang menegakkan budaya keadilan. Yang begini mestinya bukan kok malah dimusuhi, tetapi didukung. Orang-orang yang tidak menyukai temannya menegakkan budaya positif-edukatif di kelas tandanya cacat mental dan pikir. Kebenaran sejati tidak dapat dipertukarkan dengan kesalahan. Kesalahan tak pantas mendapatkan pembelaan.
Dalam satu kelas memang sudah seharusnya ada “pejuang-pejuang kebenaran”. Jika cara-cara halus (mengajak, mengingatkan, dan menasehati) sudah tak mempan lagi, tandanya memang harus ada yang merani bertindak lebih tegas demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Tegas di sini dalam artian tidak dengan cara-cara yang melanggar aturan. Sebagai contoh misalnya tegas untuk tidak mencantumkan nama teman yang hanya numpang nama dalam pengerjaan tugas. Tegas menolak teman yang ingin nitip absen padahal tidak hadir kuliah. Melaporkan kepada pihak yang berwajib (misal Kaprodi) jika menjumpai teman yang terbukti melakukan pencurian atau kekerasan. Tentu masih banyak contoh lainnya.
Jika ada teman yang suka marah ketika diingatkan dalam kebaikan, tandanya ada yang “tidak beres” (bermasalah) pada orang tersebut. Mungkin sudah teracuni oleh circle pertemanan yang tidak sehat. Circle pertemanan yang getol membela anggota temannya meski dalam jalan kesalahan dan kesesatan.



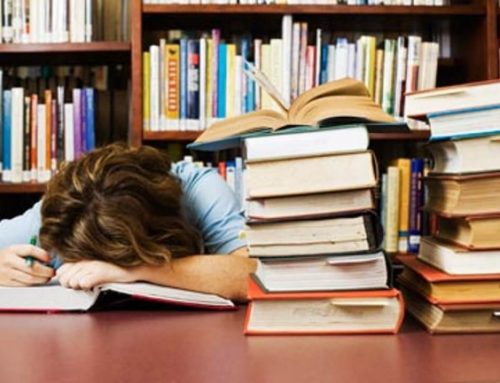


![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)








![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)