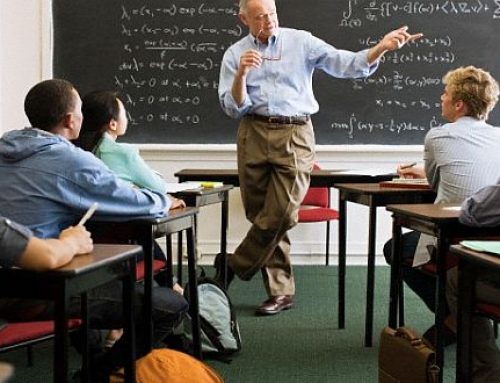Oleh: Isawati, S.Pd., M.A.
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: isawati@staff.uns.ac.id
Pendahuluan
Indonesia merupakan sebuah masyarakat majemuk. Kemajemukan diperlihatkan oleh adanya polarisasi masyarakat Indonesia ke dalam berbagai sub kesatuan di bawah negara kebangsaan (nation state), baik dalam dimensi horizontal maupun vertical. Dalam dimensi horizontal, Indonesia memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, kebiasaan, ras, agama, dan pada gilirannya budaya politik.
Hildred Geertz mengidentifikasi adanya 300 suku bangsa; Iwan Gayo mencatat secara rinci adanya tak kurang dari 362 suku bangsa; dan Skiner menyebut jumlah yang lebih kecil, yaitu 35 suku bangsa. Keragaman suku bangsa tersebut ditambah dengan adanya keragaman bahasa dan kebiasaan hidup. Dalam konteks ras, masyarakat Indonesia juga tidak homogen, terutama berkaitan dengan adanya perbedaan rasial antara masyarakat Indonesia Bagian Barat dengan masyarakat Indonesia Bagian Timur serta adanya ras Cina disamping ras pribumi (Eep Saefulloh Fatah, 2010: 1).
Tingkat keragaman yang tinggi seperti yang dimiliki Indonesia, sesungguhnya merupakan kekayaan dan khasanah kehidupan yang penuh makna, tetapi dapat berubah menjadi bencana manakala tidak ada manajemen pengelolaan yang baik. Banyaknya konflik dengan beragam latar belakang yang terjadi di Indonesia merupakan contoh nyata tentang bagaimana keragaman telah menjadi bencana yang tragis dan memilukan. Bagaimana mungkin orang bisa menghancurkan dan membunuh mereka yang berbeda karena sentiment ras, suku, agama, atau afiliasi politik. (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2011:7).
Salah satu konflik yang sering terjadi yaitu konflik etnis Jawa-Tionghoa.Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan relasi etnis Jawa-Tionghoa berjalan rumit sehingga menimbulkan konflik dan tindak kekerasan. Faktor politik menempati urutan pertama, disusul selanjutnya oleh faktor ideologi, kesenjangan ekonomi, dan segregasi sosial. Pengaruh keempat faktor tersebut menyumbat komunikasi antar kedua komunitas tersebut hingga sampai ke tingkat lapisan masyarakat yang paling bawah (Ma’arif Jamuin, 2001: 1).
Jika ditilik secara historis, citra negative terhadap etnis Tionghoa memiliki akar yang panjang. Menurut Aswi Warman Adam (peneliti sejatah LIPI), historisnya bisa dilacak pada ,masa sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama pada masa kolonial. Sejak pembantaian Tionghoa di Batavia pada tahun 1740, orang Tionghoa tidak diperbolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan wijkenstelsel menciptakan pemukiman etnis Tionghoa atau Pecinan di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.sehingga menyebabkan minimnya interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa yang selanjutnya mengarah pada citra negative terhadap etnis Tionghoa. (Choirul Mahfud, 2009:165-167).
Surakarta merupakan daerah pemukiman yang cukup tua yang manjadi salah satu lokasi tujuan migrasi orang-orang Cina di masa lalu dan sebagai tempat tinggal mereka di masa sekarang. Dalam realitas sosial orang-orang Tionghoa di Surakarta senantiasa mendapatkan stigma dan citra jelek, padahal realitas kultural orang-orang Tionghoa ikut berperan dalam pembentukan dan pengembangan budaya Jawa. Konflik bernuansa rasial merupakan suatu fenomena penting dan sangat menarik dalam perjalanan sejarah Kota Surakarta.
Masalah relasi Jawa Tionghoa hingga kini masih mengundang perdebatan sengit. Dalam serangkaian tragedi konfik rasial di Surakarta tahun 1972-1998 ini sudah banyak menelan korban jiwa, banyak gedung-gedung perkantoran, pertokoan, atau rumah-rumah yang hangus terbakar serta kendaraan-kendaraan transportasi warga juga tak luput dari amukkan massa (Yahya Aryanto Putro, 2017: 67).
Dalam konteks relasi Jawa-Tionghoa, akumulasi pengalaman buruk akibat konflik tidak terkomunikasikan secara terbuka. Masing-masing mencatat dan mereproduksi beragam cerita dengan persepsi yang berbeda. Kondisi ini diperparah dengan dominannya pendekatan politik yang digunakan pemerintah dan rendahnya pendekatan kultural dalam penyelesaian konflik etnis Jawa-Tionghoa (Ma’arif Jamuin, 2001: 3).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengkaji tentang urgensi pendekatan kultural dalam upaya penyelesaian konflik Jawa-Tionghoa di Surakarta .Penulis tertarik memilih Surakarta dengan alasan bahwa konflik rasial di Surakarta sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Pada masa Orde Baru sudah terjadi tiga kali kerusuhan berskala besar yang terjadi pada tahun 1972-1998. Peristiwa rasial anti Tionghoa di Kota Surakarta ini memiliki faktor pemicu kerusuhan berskala kecil yang menjadi karakteristik unik yang mampu menyebabkan kekacauan sangat besar dan sangat serius.
Selain itu uniknya kota Surakarta sebagai pusat konflik terkenal dengan masyarakatnya yang lemah lembut, santun, perhitungan dan mengedepankan keharmonisan. Peristiwa rasial di Surakarta yang selama ini terjadi mengandung tanda tanya besar. Sikap santun dan lemah lembut masyarakat Surakarta ternyata mengandung sikap agresif yang luar biasa.Oleh karena itu pendekatan kultural sangat urgen dalam penyelesaian konflik dengan asumsi bahwa pendekatan kultural bisa memfasilitasi proses tumbuhnya kesadaran identitas historis terhadap orang Tionghoa. Proses tersebut selanjutnya membentuk identitas budaya Tionghoa dan bermanfaat bagi terjadinya asimilasi dan integrasi secara wajar tanpa adanya pemaksaan sehingga bermuara pada terciptanya keharmonisan relasi Jawa Tionghoa.
Latar Belakang Historis Relasi Jawa-Tionghoa di Surakarta
Emigrasi orang China ke Jawa mulai terjadi secara besar-besaran pada abad ke-14. Awal terjadinya pemukiman Cina di sepanjang Pantai utara Jawa tersebut sebagai akibat dari aktivitas perdagangan antara India dan Cina lewat laut. Perkembangan pemukiman Cina di Asia Tenggara semakin bertambah dipicu adanya usaha Dinasti Ming (1368-1644) untuk memasukkan daerah Asia Tenggara sebagai daerah protektoratnya pada abad ke-14.
Admiral Zheng He (Cheng Ho dalam dialek Fujian) dari dinasti Ming dikirim untuk melakukan ekspedisi pelayaran. Antara tahun 1405-1433, Zheng He melakukan 7 kali ekspedisi pelayaran. Pada zaman ekspedisi Zheng He inilah pemukiman Cina di berbagai kota Pantai utara Jawa mengalami pemantapan. Jadi pemukiman Cina di Jawa sudah ada jauh sebelum orang-orang Belanda menguasai daerah Pantai utara Jawa pada tahun 1743 (Handinoto, 2015: 76-77).
Selanjutnya, berdasarkan bukti sejarah menunjukkan bahwa pemukiman keluarga-keluarga Tionghoa sudah ada di Solo sejak Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Solo dan Yogyakarta merupakan daerah-daerah pertanian yang sangat subur, dari akhir abad ke-16 sampai awal abad ke-19, kedua wilayah ini menjadi pusat politik utama Jawa Tengah dan Jawa Timur, negeri Etnik bangsa Jawa . Di daerah Solo sendiri, merupakan daerah yang dikuasai oleh 2 generasi kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Pajang dan Kerajaan Mataram Islam.
Ketika Solo di bawah kekuasaan Mataram Islam yang dipimpin oleh Pakubuwana II, wilayah ini merupakan sentral dari segala bidang. Bermacam-macam suku bangsa hidup di wilayah ini, salah satunya Etnik Tionghoa. Pusat pemerintahan Mataram Islam kala itu berada di Kartasura, namun oleh karena geger Pecinan akhirnya dipindahkan ke Solo. Kepindahan Keraton Mataram Islam pemerintahan Pakubuwana II ke Solo,diikuti pula dengan kepindahan Klenteng “Tien Kok Sie” ke wilayah baru tersebut, maka secara tidak langsung banyak Etnik Tionghoa yang juga menyebar ke wilayah ini. Dari tahun pembuatan Klenteng “Tien Kok Sie” (ketika itu masih di Kartasura) yang terletak di Jalan. Pasar Besar Ketandan No. 65 Solo yakni tahun 1745, diketahui bahwa Etnik Tionghoa sudah ada di Solo sekitar tahun 1740 dan membentuk koloni (Chandra Halim dan Silverio R. L. Aji Sampurno, 2013: 61).
Pada zaman Kolonial Belanda, pemukiman yang terdapat di berbagai kota di Jawa, termasuk Surakarta berada di bawah kekuasaan pemerintah Kolonial Belanda. Jumlah penduduk Cina di Jawa semakin lama semakin banyak. Pada tahun 1800-an, penduduk Cina di Jawa berjumlah 100.000 orang dan menjadi 500.000 orang menjelang akhir abad ke-19. Sedangkan jumlah penduduk Cina di Surakarta pada tahun 1815 yaitu 2.435 orang atau 0,25% .dari jumlah seluruh penduduk Surakarta (Handinoto, 2010:357).
Menurut Benda S.A.Yeoh, kota kolonial menampung masyarakat yang sangat beragam.Mereka hidup menjadi satu dalam satu kota, namun tempat dan posisi terkotak-kotak berdasarkan warna kulit atau ras. Perbedaan tempat tinggal yang didasarkan warna kulit (segregasi ras) adalah sesuatu yang didesain pemerintah colonial Belanda dengan dikeluarkannya Regerings Reglement tahun 1854. Dengan kebijakan ini, terbentuklah Kawasan khusus untuk orang Eropa, Kawasan Pecinan (Chinese Kamp) untuk orang Cina, Kawasan kampung Melayu (Malaise Kamp), dan perkampungan Arab (Arabisceh Kamp). Pemusatan pemukiman tersebut didasarkan kepentingan pemerintah colonial Belanda agar mudah melakukan control dan sekaligus menghindari konflik horisontal (Purnawan Basundoro, 2012: 94-95).
Di Surakarta, perkampungan orang Eropa terletak di luar Beteng yang disebut Loji Wetan, karena bangunannya berbentuk loji yang menggunakan bahan batu bata. Sedangkan Masyarakat Tionghoa ditempatkan dalam sebuah Pecinan di daerah Balong dan sekitar Pasar Gedhe Solo. Pemukiman masyarakat Tionghoa terletak di utara Sungai Pepe sekitar Pasar Besar ke timur di Ketandhan hingga Limalasan, ke utara sampai di Balong, ke sebelah utara menuju Warungpelem. Pemukiman masyarakat Arab terletak di Pasar Kliwon. Perkampungan penduduk bumiputera terpencar di seluruh kota. Sebagian nama perkampungan menurut nama putra putri raja seperti Jayakusuman, Adi Wijayan,Suryabratan dan Kalitan; Sebagian lain menurut kelompok abdi dalem kriya dengan pekerjaan sejenis, misalnya Sayangan, Serengan, Telukan, dan sebagainya. Ada juga yang disebut menurut profesi orang yang menempati kampung tersebut misalnya Carikan, Sraten, Kalangan, Punggawan, dan Gadhingan. Tempat yang khusus untuk abdi dalem ulama disebut kampung Kauman.(Julianto Ibrahim, 2008: 26-27)
Orang Cina merupakan kelompok sosial yang piawai dalam berbisnis, maka pemerintah Kolonial Belanda menjadikan orang Cina sebagai kekuatan ekonomi untuk mempertahankan politik penjajahannya.Orang Cina diharuskan tinggal di Pecinan dengan diawasi seorang opsir Cina yang diangkat pemerintah colonial Belanda. Menurut Skinner, system pemukiman yang diskriminatif dan eksklusif di Pecinan dan pengetatan pemberian pas jalan bagi orang Cina dalam realitanya bertujuan membatasi ruang gerak mereka untuk menjalin hubungan dagang dengan para pemimpin lokal. (Lia Yulia dan Soni Akhmad Nulhaqim, 2021: 245).
Masyarakat Tionghoa di Solo harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah colonial yang bersifat diskriminatif seperti halnya Tionghoa di daerah lain. Belanda menetapkan peraturan dalam bidang hukum yang bersifat memojokkan komunitas Tionghoa. Sistem Lapisan ras, system wilayah tempat tinggal (wijkenstelsel) dan surat jalan(Passenstelsel) , serta sistem agraria (mengacu pada UU Agraria 1870) yang melarang mereka memiliki tanah, membuat komunitas ini semakin terkekang. (Chandra Halim dan Silverio R. L. Aji Sampurno, 2013: 62).
Pada tahun 1925 Orang Cina mulai terbebas dari Passen en Wijkenstelsel yang menghambat gerak langkah dan keharusan untuk berdiam di wilayah Pecinan sesuai dengan peraturan yang telah dihapuskan pada tahun 1915 dan 1919.(Sarkawi B.Husain,dkk, 2010: 212).Sejak dihapusnya peraturan tersebut dan dengan bertambahnya jumlah emigran Tionghoa ke Indonesia, maka orang-orang Tionghoa tidak harus tinggal di Pecinan.Akan tetapi,daerah Balong tetap menjadi Pecinan. Dalam perkembangannya, hanya sedikit orang-orang Tionghoa yang tinggal di sana. Di daerah Balong terdapat orang-orangTionghoa Solo yang dapat dikatakan sebagai Tionghoa yang paling tua. Rata-rata penduduknya merupakan masyarakat Tionghoa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah. Oleh sebab itulah, terjalin suatu komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi yang berlangsung sangat akrab. Di kampung ini pula yang menghasilkan banyak Tionghoa peranakan, akibat perkawinan campur antara Tionghoa dengan Jawa.
Penyebaran orang-orang Tionghoa di Surakarta terjadi mulai abad ke-20. Tempat strategis seperti Nonongan dan Coyudan menjadi pilihan mereka. Tahun 1960-an, para pedagang Tionghoa sudah menyebar ke lokasi strategis lain seperti jalan-jalan sekitar Pasar legi, Pasar Gedhe, dan Pasar Singosaren. Masyarakat Tionghoa di Solo, lebih di dominasi oleh etnik Hokkian dibandingkan etnik yang lainnya, sehingga suku bangsa Hokkian memiliki peran penting di dalam kegiatan sehari-hari komunitas Tionghoa yang ada di Solo. Etnik Hokkian berasal dari propinsi Fukien bagian selatan.Daerah tersebut adalah daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan perdagangan orang-orang Tionghoa ke Seberang lautan. Mereka pada umumnya sangat menguasai sifat dagang yang dikenal begitu ulet, tahan uji dan rajin. Oleh sebab itu,tidaklah mengherankan apabila sebagian besar perdagangan di Surakarta dipegang oleh orang-orang Hokkian (Chandra Halim dan Silverio R. L. Aji Sampurno, 2013:63-65).
Berbagai Konflik yang Pernah Terjadi Dalam Relasi Etnis Jawa-Tionghoa di Surakarta dan Faktor Penyebabnya
1. Peristiwa Geger Pacinan
Konflik rasial di eks-Karesidenan Surakarta ini sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda. Sekitar dua setengah abad yang lalu, yang dikenal dengan “Bedah Kartasura” atau Geger Pacinan pada tahun 1742. Tragedi besar-besaran tersebut terjadi di pusat-pusat otoritas.yang saat itu Kartasura sebagai pusat Mataram (Yahya Aryanto Putro,dkk, 2017:67). Geger Pecinan merupakan peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap keraton Surakarta, karena keraton Surakarta waktu itu dianggap sebagai boneka Belanda.(Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto, 2020:42).
Geger Pacinan mempunyai hubungan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya yaitu ketika pada tahun 1740 terjadi keributan antara orang Tionghoa dengan Belanda yang menjalar dari Batavia ke Jawa Tengah. Pada tahun 1740 terjadi pembantaian massal terhadap masyarakat Cina, de Chinezenmoord.Orang Cina menyampaikan ketidakpuasan sebagai korban berbagai peraturan colonial Belanda yang membatasi ruang gerak mereka. Orang Cina kemudian dituduh merencanakan pemberontakan dan hendak mengenyahkan VOC (Denys Lombard, 2018: 74).
Di Batavia, lebih dari 10.000 orang Tionghoa mati terbunuh oleh Belanda. Selebihnya banyak yang berhasil melarikan diri ke Jawa Tengah. Akibatnya, keraton Mataram yang beribukota di Kartasura mengalami kekacauan. Paku Buwana II tidak dapat mengatasi kerusuhan yang timbul akibat adanya aliansi antara elit bangsawan oposan dengan orang Tionghoa.Sunan Paku Buwana II akhirnya terpaksa mengungsi ke Ponorogo. Ketika Paku Buwana II Kembali dari Ponorogo tahun 1742, menyaksikan kehancuran bangunan istana. Hampir seluruh bangunan istana rusak berat, bahkan banyak yang rata dengan tanah akibat ulah para pemberontak pada masa Geger Pacinan. Kondisi tersebut mendorong Sunan Paku Buwana II untuk membangun istana yang baru karena istana Kartasura tidak layak lagi sebagai tempat raja dan pusat Kerajaan.Selain itu ada semacam nilai tradisi dalam budaya Jawa bahwa tidak baik menempati kembali sebuah istana yang pernah runtuh karena diapercaya akan susah membangun Kembali kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Purwadi dan Djoko Dwiyanto, 2008: 33-34).
2. Konflik Rekso Roemekso dan Kong Sing
Pada awal abad 20 muncul konflik etnis Tionghoa dan Jawa akibat persaingan dagang yaitu antara perkumpulan Rekso Roemekso (Sarekat Islam) dan Kong Sing (perkumpulan pedagang Tionghoa).Orang-orang Cina terlibat persaingan dagang dengan para pengusaha Jawa. Hubungan orang Cina dengan masyarakat Jawa pada umumnya menjadi tegang gara-gara meningkatnya kesombongan dan kebanggaan orang Cina yang mereka perlihatkan pada saat bangkitnya revolusi Cina pada tahun 1911 (M.C.Ricklefs, 2010: 358).
Pada Bulan Oktober 1911 terjadi revolusi di Cina yang ditandai dengan runtuhnya Dinasti Ching dan diganti oleh Republik. Orang Tionghoa yang berada di Hindia melihat fenomena ini sebagai tanda adanya negara Tiongkok yang kuat dan modern. Shiraishi mengatakan pada tahun tersebut terdengar desas desus mengenai Tionghoa berani mengatakan kepada pribumi bahwa mereka akan menjadi penguasa dan tuan bagi pribumi. Perilaku Tionghoa terhadap pribumi sangat sombong. Ketika berita revolusi Tiongkok mencapai Hindia, Tionghoa mulai bersikap angkuh dan memperlakukan pribumi secara kurang layak. H. Samanhudi marah dan akhirnya mendirikan perkumpulan serupa dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam pertikaian yang bernama Rekso Roemekso. Rekso Roemekso beralih menjadi organisasi sosial yang diberi nama Serikat Dagang Islam ini terjadi disaat persaingan dagang antara pedagang pribumi muslim dengan Tionghoa (Firda Nurjanah dan Andika Saputa, 2021: 32).
Sebagai perkumpulan ronda, awalnya Rekso Rumekso bertujuan menjaga keamanan dari penjahat yang banyak melakukan pencurian di Lawean dan kota Solo, tetapi sebenarnya Rekso Rumekso dibentuk untuk menandingi perkumpulan Kong Sing. Kong Sing adalah perkumpulan yang didirikan tahun 1911 beranggotakan orang Cina maupun Jawa. Pedagang Tionghoa menguasai jaringan niaga, bahan baku impor dan pemasaran produksinya,sehingga mampu mempermainkan harga dan pemogokan pasar dan menjadikan produsen kecil pribumi bergantung dan terpojok, tanpa kemampuan mengembangkan usaha mereka. Etnis Tionghoa bersaing secara tidak sehat karena memperoleh hak istimewa dari Belanda berupa monopoli bahan batik. Pihak Belanda juga mempersulit pribumi dalam memperoleh bahan-bahan untuk membuat batik. Reaksi terhadap monopoli tersebut, maka Tirtoadisoerjo dan Martodharsono, memperkenalkan cara baru untuk menghadapi pedagang Tionghoa dengan boikot.Pertama-tama hal itu dilakukan terhadap toko “Sie Dhian Ho” dan beberapa toko Tionghoa lainnya, yang diikuti dengan perkelahian-perkelahian bahkan melibatkan 90 orang prajurit Mangkunegaran dalam penyerangan pasar Gede (Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuatie, 2015: 219-220).
Rekso Rumekso yang didirikan Haji Samanhudi pada 1911 selanjutnya berubah menjadi Sarekat Dagang Islam (SDI) cabang Surakarta karena tidak memiliki status badan hukum. SDI bertujuan agar para pedagang batik pribumi muslim dapat bersaing dengan para pedagang Tionghoa. Pada tahun 1912, SDI berubah menjadi Sarekat Islam yang diketuai Tjokroaminoto. SI didirikan untuk memajukan perdagangan, membantu sesama anggota yang kesusahan, memajukan pendidikan, dan meningkatkan pengetahuan agama (Lorient Marccelita dan M Bagus Sekar Alam,2024:4).
3. Konflik Pada Masa Pemberontakan G30S/PKI.
Saat itu masyarakat pribumi menganggap bahwa banyak warga Tionghoa yang menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang merupakan organisasi sosial politik Cina peranakan di Indonesia yang berdiri pada tahun 1954-1966. Baperki yang secara terang-terangan mendukung PKI yang berimbas pada pengrusakan toko-toko milik warga Tionghoa.
Di tengah arus 1965, warga Tionghoa di negeri ini terjepit oleh kekuasaan represif. Rezim Soeharto pada tahun 1965, meluncurkan kebijakan pemaksaan asimilasi bagi warga Tionghoa. Kebijakan itu memaksa warga Tionghoa di negeri ini melepaskan kebudayaan dan meminggirkan bahasa Mandarin dalam percakapan keseharian. Di sektor pendidikan, pemerintah menutup semua sekolah yang berbahasa Mandarin serta menggiring anak-anak Tionghoa belajar di sekolah yang berbahasa Indonesia. Instruksi Presiden (Inpres) No 14 Tahun 1967 menjadi palu godam bagi kebebasan Tionghoa untuk mengekspresikan identitas dan kulturnya.
Pasca 1965, warga Tionghoa di negeri ini mengalami tekanan dari penguasa. Rasialisme terhadap orang Tionghoa meningkat tajam karena pemerintah China (RRC) dianggap sebagai sponsor utama dari peristiwa gelap 30 September 1965. RRC dituduh mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Hingga, warga Tionghoa yang tidak terafiliasi dengan PKI juga kena getahnya. Segala sesuatu yang berbau Tiongkok disingkirkan rezim Soeharto Dari sisi gelap itu, muncul dikotomi antara pribumi dan nonpribumi sebagai politik strata demografis.(Munawir Azis, 2017).
4. Kerusuhan antar etnis Tionghoa dan Jawa Tahun 1980
Kerusuhan antar etnis Tionghoa dan Jawa pada bulan November 1980 dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina dekat Pasar Gede. Perkelahian ini menyulut kemarahan masa yang kemudian berimbas pada pembakaran dan penjarahan toko-toko milik orang Cina oleh ribuan massa. Peristiwa 19 November 1980 berjalan selama dua hari. Akar masalah konflik ini bermula oleh kejadian tabrakan lalu-lintas di jalan sekitar Warung Pelem pada 19 November 1980, antara Pipit (Jawa) pelajar Sekolah Guru Olahraga (korban) dan Kicak, seorang pemuda Tionghoa. Kemudian disusul dengan pemukulan Pipit oleh Kicak. Peristiwa ini segera berkembang cepat menjadi kerusuhan massal di Kota Surakarta terutama yang terdapat pertokoan milik orang-orang Tionghoa. Selain merusak dan membakar toko-toko, massa juga melakukan aksi penjarahan (Lydiana Salim dan Akhmad Ramdhon, 2020: 62)
5. Peristiwa kerusuhan Mei 14-15 Mei 1998
Kerusuhan ini dianggap kerusuhan paling kolosal di sepanjang sejarah Surakarta. Selama kerusuhan dua hari itu, korban tewas tercatat 29 orang, 307 buah bangunan terbakar meliputi toko, plaza, show room, bank, dan 2 swalayan Matahari.
Peristiwa 14 Mei 1998 dimulai dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang terjadi di dua tempat, yakni di kampus Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Pabelan. dan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Kentingan, Surakarta. Dari kedua aksi itu memunculkan kekerasan massa yang dimulai dari kampus UMS. Kejadian itu kemudian melebar, dan mahasiswa mulai bergerak keluar kampus. Aksi damai sekaligus aksi menuntut adanya reformasi yang digelar mahasiswa berubah seketika menjadi bentrok yang besar, di tambah lagi dengan keterlibatan masyarakat sekitar yang mudah terprovokasi menjadikan aksi ini sebagai awal terjadinya kerusuhan Mei 1998 (Yahya Aryanto Putro,dkk, 2017: 69-70).
Etnis Tionghoa yang secara etos kerja memang cenderung ulet dan pekerja keras menjadikan kehidupannya lebih mapan daripada orang-orang di sekitarnya sehingga hal tersebut menjadi ladang dari beberapa oknum untuk menanamkan sebuah doktrin kebencian dalam meraih kepentingan di berbagai bidang baik ekonomi, politik, maupun sosial (Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto,2020: 43)
Gambaran sejarah orang Cina seringkali diwarnai dengan bias stereotipe tentang mereka yang eksklusif, tertutup, mementingkan diri sendiri, egoistik dan pelit. Walaupun sekali-kali muncul juga gambaran yang kontras, seperti misalnya kedekatan mereka dengan rakyat kecil. Selain itu, orang Cina sebagai kelompok minoritas, ternyata mampu berada pada kedudukan yang sangat berarti, terutama di bidang ekonomi, jauh di atas kemampuan penduduk pribumi. Kondisi tersebut semakin memantapkan stereotip minoritas Cina (Sarkawi B.Husain,dkk. 2010: 201). Kekerasan terhadap etnis Cina di Indonesia khususnya kasus Mei 1998 tidak bisa serta-merta timbul karena sentimen etnis. Salah satu faktor yang mendorong munculnya konflik kekerasan tersebut adalah morfologi fisik pemukiman. Pola pemukiman yang berubah menjadi model sosio-ekonomis yang eksklusif telah menumbuhkan citra negatif sebuah kelompok bermodal (Cina).(Nanik Prihartanti,dkk, 2009:112).
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan (2024:53), korban dari etnis Tionghoa memiliki tekad untuk mengampuni dan menerima perlakuan masyarakat pribumi terkait kerusuhan Mei 1998 yang terjadi. Para korban juga mengaku telah memaafkan para pelaku dan tidak menyalahkan masyarakat pribumi atas kejadian tersebut. Walau begitu, peristiwa kerusuhan yang terjadi menghasilkan adanya trauma maupun perubahan perasaan dan perilaku dari para korban etnis Tionghoa terhadap etnis Pribumi, sehingga menyebabkan korban Etnis Tionghoa lebih berjaga-jaga dalam berelasi dengan masyarakat Pribumi (etnis Jawa) hingga saat ini.
Urgensi Pendekatan Kultural Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Relasi Jawa-Tionghoa di Surakarta
Sebenarnya upaya-upaya perbaikan hubungan antara kedua etnis sudah lama dilakukan, seperti dibentuknya Chuan Min Kung Hui pada tahun 1932, yang selanjutnya pada tahun 1959 menjadi Perkumpulan Masyarakat Surakarta (PMS) yang anggotanya meliputi etnis Cina dan Jawa di Surakarta. Di perkumpulan ini mereka melakukan kegiatan bersama. Selain itu, proses asimilasi secara mandiri maupun melalui peran lembaga juga sudah lama berlangsung. Bentuk asimilasi tersebut antara lain pernikahan, pemakaian nama-nama Jawa atau Nasional pada orang-orang Cina, dan berpindah menjadi penganut agama Islam (sebagian besar dianut masyarakat Jawa), atau sebaliknya orang Jawa yang menjadi penganut agama Kristen. ).(Nanik Prihartanti,dkk, 2009: 110).
Permasalahan mendasar dari penelitian ini adalah bahwa telah lamanya kedua pihak (etnis Jawa-Cina) hidup bertetangga (1740-sekarang) semestinya telah terjalin suatu pola hubungan yang eklektif dan kondusif, namun sebagaimana diketahui serangkaian konflik kekerasan kembali berulang. Berbagai upaya harmonisasi hubungan yang telah dilakukan sebelumnya seakan tidak memiliki kontribusi apa-apa. Titik-titik persamaan yang sesungguhnya bisa merajut persatuan tidak dapat menahan berulangnya konflik. Ini menunjukkan perlunya meninjau ulang berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan.
Dominasi pendekatan politik yang selama ini yang dilakukan pemerintah, terutama masa Orde dalam penyelesaian konflik Jawa-Tionghoa cenderung bersifat koersif, represif, dan instrumental sehingga berdampak pada hancurnya ikatan kultural yang tumbuh dalam relasi komunitas Jawa-Tionghoa. Pendekatan tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan prakarsa dan inisiatif untuk membangun ikatan sosial yang kokoh. Semua serba pemerintah. Alam pikir yang menonjol dalam benak masyarakat adalah” kita tidak bisa apa-apa” semuanya harus menunggu tangan pemerintah. Masyarakat dibuat tidak berdaya untuk menentukan apa yang penting bagi dirinya sendiri. (Ma’arif Jamuin, 2001: i).
Pendekatan politik yang membabi buta akhirnya memporak-porandakan bangunan identitas dan harga diri kelompok. Pendekatan politik yang kental dengan ideologi penyeragaman telah mereduksi berbagai keunikan yang melekat dalam komunitas. Akibat yang terparah ketika perbedaan direpresi, makna keanggotaan dari kebanyakan kelompok sosial dan primordial menjadi hampa. Oleh karena itu perlu merekonstruksi kualitas relasi Jawa-Tionghoa dengan mengembangkan model resolusi konflik yang berbasis pada pendekatan kultural.
Gudykunst dan Kim menyatakan bahwa terdapat dua tahap dalam proses adaptasi yaitu cultural adaptation dan cross-cultural adaptation. Pertama, cultural adaptation adalah suatu proses ketika individu atau kelompok berpindah ke lingkungan yang baru yang selanjutnya terjadi proses enculturation yaitu proses komunikasi yang dilakukan antara penduduk lokal dengan pendatang. Proses penerimaan etnis Jawa terhadap etnis Tionghoa merupakan keberhasilan cultural adaptation dalam proses enculturation, karena keduanya dapat berkomunikasi secara baik hingga dapat hidup berdampingan secara damai.
Kedua, cross-cultural adaptation. Proses cross-cultural adaptation meliputi tiga tahap yaitu akulturasi (acculturation), dekulturasi (deculturation), dan asimilasi (assimilation). Akulturasi adalah fenomena yang terjadi ketika kelompok individu yang memiliki budaya berbeda masuk ke dalam kontak langsung pertama, dengan perubahan selanjutnya dalam pola budaya asli dari kedua atau kedua kelompok yang berbeda. Strategi akulturasi yang meliputi asimilasi, pemisahan, marginalisasi, dan integrasi. Asimilasi melibatkan pelepasan warisan budaya seseorang dan mengadopsi budaya baru. Proses ini terjadi ketika individu pendatang yang telah melalui proses sosialisasi mulai berinteraksi dengan budaya yang baru dan asing baginya. Seiring dengan berjalannya waktu, pendatang tersebut mulai memahami budaya baru itu dan memilih norma dan nilai budaya lokal yang dianutnya. Walaupun demikian, pola budaya terdahulu juga mempengaruhi proses adaptasi.(Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto,2020: 45).
Dalam perspektif komunikasi, bahwa komunikasi antarbudaya yang mindful membutuhkan 4 kecakapan, yaitu kekuatan pribadi (personality strength), kecakapan komunikasi (communication skills), penyesuaian psikologis (psychological adjustment), dan kesadaran budaya (cultural awareness). Sifat kepribadian yang mempengaruhi komunikasi antarbudaya adalah konsep diri (self-concept), pengungkapan diri (self-disclosure), pemantauan diri (self-monitoring), dan relaksasi sosial (social relaxation). Konsep diri merujuk pada cara seseorang memahami dirinya sendiri.
Komunikasi antarbudaya yang mindful akan muncul ketika masing-masing pihak yang menjalin kontak atau interaksi dapat meminimalisasikan kesalahpahaman budaya, yaitu berusaha untuk mereduksi perilaku etnosentris, prasangka dan stereotip. Selain itu, komunikasi yang mindful juga akan muncul apabila kedua belah pihak dapat mengelola dengan baik kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi. Secara filosofis, usaha untuk menciptakan situasi komunikasi antarbudaya yang mindful dapat dijelaskan dari perspektif salah satu tokoh psikologi Humanistik, yaitu Martin Buber dengan konsep I-Thou dan I-it yang merupakan model relasi interaksi. Idealnya komunikasi antarbudaya yang mindful perlu dipahami dalam konteks hubungan I-Thou (Aku-Engkau). Dalam hubungan I – Thou, orang lain diterima, diakui, dan diperlakukan sebagai pribadi yang memilki ruang gerak untuk menjadi dirinya sendiri.(Nanik Prihartanti,dkk, 2009: 112).
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:
- Latar Belakang Historis Relasi Jawa-Tionghoa di Surakarta dimulai ketika terjadi emigrasi orang China ke Jawa secara besar-besaran pada abad ke-14. Pada zaman ekspedisi Zheng He, pemukiman Cina di berbagai kota Pantai utara Jawa mengalami pemantapan. Pemukiman keluarga-keluarga Tionghoa sudah ada di Solo sejak Kerajaan Pajang di bawah kekuasaan Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir. Pada masa Paku Buwana II, Etnik Tionghoa sudah ada di Solo sekitar tahun 1740 dan membentuk koloni.Pada masa colonial Belanda, terjadi segregasi ras yang menyebabkan etnis Tionghoa harus tinggal di daerah Pecinan. Masyarakat Tionghoa di Solo harus tunduk pada peraturan-peraturan pemerintah colonial yang bersifat diskriminatif seperti halnya Tionghoa di daerah lain. Di daerah Balong terdapat masyarakat Tionghoa yang berasal dari ekonomi menengah ke bawah, sehingga terjalin suatu komunikasi sosial dengan masyarakat pribumi yang berlangsung sangat akrab. Di kampung ini pula menghasilkan banyak Tionghoa peranakan, akibat perkawinan campur antara Tionghoa dengan Jawa.Penyebaran orang-orang Tionghoa di Surakarta terjadi mulai abad ke-20. Masyarakat Tionghoa di Solo, lebih di dominasi oleh etnik Hokkian sehingga suku bangsa Hokkian memiliki peran penting di dalam kegiatan sehari-hari komunitas Tionghoa yang ada di Solo. Mereka pada umumnya sangat menguasai sifat dagang yang dikenal begitu ulet, tahan uji dan rajin. Oleh sebab itu,tidaklah mengherankan apabila sebagian besar perdagangan di Surakarta dipegang oleh orang-orang Hokkian.
- Berbagai konflik yang pernah terjadi dalam relasi etnis Jawa-Tionghoa di Surakarta antara lain Geger Pecinan tahun 1742 yang merupakan peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh etnis Tionghoa terhadap keraton Surakarta, karena keraton Surakarta waktu itu dianggap sebagai boneka Belanda. Selanjutnya pada awal abad 20 muncul konflik etnis Tionghoa dan Jawa akibat persaingan dagang yaitu antara perkumpulan Rekso Roemekso (Sarekat Islam) dan Kong Sing (perkumpulan pedagang Tionghoa).Tahun 1965 masyarakat pribumi menganggap bahwa banyak warga Tionghoa yang menjadi anggota BAPERKI yang secara terang-terangan mendukung PKI yang berimbas pada pengrusakan toko-toko milik warga Tionghoa. Pada tahun 1980 kembali terjadi kerusuhan antar etnis Tionghoa dan Jawa yang dipicu oleh perkelahian antara dua pemuda Jawa dan Cina dekat Pasar Gede. Perkelahian ini menyulut kemarahan masa yang kemudian berimbas pada pembakaran dan penjarahan toko-toko milik orang Cina oleh ribuan massa. Selanjutnya terjadi kerusuhan Mei 14-15 Mei 1998 yang dianggap kerusuhan paling kolosal di sepanjang sejarah Surakarta yang disebabkan oleh akumulasi berbagai faktor penyebab,baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial.
- Urgensi Pendekatan Kultural Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Relasi Jawa-Tionghoa Di Surakarta karena dominasi pendekatan politik selama ini yang dilakukan pemerintah, terutama masa Orde Baru dalam penyelesaian konflik Jawa-Tionghoa cenderung bersifat koersif, represif, dan instrumental sehingga berdampak pada hancurnya ikatan kultural yang tumbuh dalam relasi komunitas Jawa-Tionghoa. Pendekatan tersebut mengakibatkan masyarakat kehilangan prakarsa dan inisiatif untuk membangun ikatan sosial yang kokoh. Oleh karena itu perlu merekonstruksi kualitas relasi Jawa-Tionghoa dengan mengembangkan model resolusi konflik yang berbasis pada pendekatan kultural. Pertama, cultural adaptation adalah suatu proses ketika individu atau kelompok berpindah ke lingkungan yang baru yang selanjutnya terjadi proses enculturation yaitu proses komunikasi yang dilakukan antara penduduk lokal dengan pendatang. Kedua, cross-cultural adaptation. Proses cross-cultural adaptation meliputi tiga tahap yaitu akulturasi (acculturation), dekulturasi (deculturation), dan asimilasi (assimilation). Komunikasi antarbudaya yang mindful akan muncul ketika masing-masing pihak yang menjalin kontak atau interaksi dapat meminimalisasikan kesalahpahaman budaya, yaitu berusaha untuk mereduksi perilaku etnosentris, prasangka dan stereotip. Selain itu, komunikasi yang mindful juga akan muncul apabila kedua belah pihak dapat mengelola dengan baik kecemasan dan ketidakpastian yang dihadapi.
Sumber Referensi
Annisa Istiqomah dan Delfiyan Widiyanto. 2020.”Resolusi konflik berbasis budaya Tionghoa-Jawa di Surakarta”, Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 1 Tahun 2020,hlm 40 – 49.
Chandra Halim dan Silverio R. L. Aji Sampurno.2013. “Masyarakat Tionghoa Di Solo Dan Organisasi Sosial (Dari Terbentuknya CMKH Sampai PMS)”. Jurnal Sejarah Kebudayaan Bandar Maulana, Volume 4, Nomor 1.
Choirul Mahfud. 2009.Pendidikan Multikultural.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Denys Lombard.2018.Nusa Jawa:Silang Budaya Kajian Sejarah Terpadu Bagian I : Batas-Batas Pembaratan Edisi Revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Eep Saefulloh Fatah. 2010. Konflik, Manipulasi dan Kebangkrutan Orde Baru: Manajemen Konflik Malari, Petisi 50, dan Tanjung Priok. Jakarta: Burung Merak Press.
Firda Nurjanah dan Andika Saputa. 2021. “Strategi Spasial Kalangan Tionghoa Di Kauman Surakarta”, Jurnal Arsitektur NALARs Volume 20 Nomor 1 Januari 2021 : 29-36
Handinoto. 2010. Arsitektur dan Kota-Kota di Jawa pada Masa Kolonial. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Handinoto.2015.Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII sampai Pertengahan Abad XX Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya. Yogyakarta: Ombak.
Julianto Ibrahim.2008.Keraton Surakarta dan Gerakan Anti Swapraja.Yogyakarta: Malioboro Press.
Lia Yulia dan Soni Akhmad Nulhaqim. 2021.” Jarak Sosial antara Keturunan Cina dan Pribumi dalam Proses Pembauran di Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang”, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 8 Nomor 2 Tahun 2021.
Lorient Marccelita dan M Bagus Sekar Alam. 2024.” Dinamika Ekonomi Lumbung Batik Pamong Pengusaha Batik Surakarta (PPBS) di Laweyan Surakarta Periode 2010-2021”, Jurnal of Policy, Vol. 15, No. 1, Juni 2024,hlm. 1-10
Lydiana Salim dan Akhmad Ramdhon, 2020. “Dinamika Konflik Kerusuhan Mei 1998 Di Kota Surakarta Melalui Perspektif Korban”,Journal of Development and Social Change, Vol. 3, No. 1, April 2020,hlm 58-71
Ma’arif Jamuin.2001. Memupus Silang-Sengkarut Relasi Jawa-Tionghoa: Panduan Advokasi untuk Membangun Rekonsiliasi. Surakarta: Ciscore.
MC.Ricklefs.2010.Sejarah Indonesia Modern 1200-2008.Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta
Munawir Azis.2017. “ Tionghoa dalam Sejarah Gelap 1965”.Jawa Pos com, 3 Oktober 2017, https://www.jawapos.com/sudut-pandang/01109105/tionghoa-dalam-sejarah-gelap-1965
Naomi Gomar dan Eunike Mutiara Himawan. 2024.” Peristiwa Kerusuhan Mei 1998: Sebuah Gambaran Pengampunan Para Korban”, Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Volume 13, Nomor 01,April 2024.
Nanik Prihartanti,dkk, 2009.” Mengurai Akar Kekerasan Etnis Pada Masyarakat Pluralis”. Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 10, No. 2, Agustus 2009: 107-120
Ngainun Naim dan Achmad Sauqi. 2011. Pendidikan Multikultural Konsep dan Aplikasi.Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Purnawan Basundoro. 2012. Pengantar Sejarah Kota.Yogyakarta: Ombak.
Purwadi dan Djoko Dwiyanto. 2008.Kraton Surakarta: Sejarah, Pemerintahan, Konstitusi, Kesusastraan dan Kebudayaan.Yogyakarta: Panji Pustaka.
Retno Winarni dan Mrr. Ratna Endang Widuatie. 2015. “Konflik Politik Dalam Pergerakan
Sarekat Islam 1926”, Jurnal Literasi Vol. 5, No. 2, Desember 2015, hlm 216 – 232
Sarkawi B.Husain,dkk. 2010.Indonesia Across Orders: Arus Bawah Sejarah Bangsa (1930-1960).Jakarta: LIPI Press.
Yahya Aryanto Putro,dkk. 2017.” Konflik Rasial Antara Etnis Tionghoa Dengan Pribumi Jawa di Surakarta Tahun 1972-1998”, Journal of Indonesian History 6 (1) (2017).



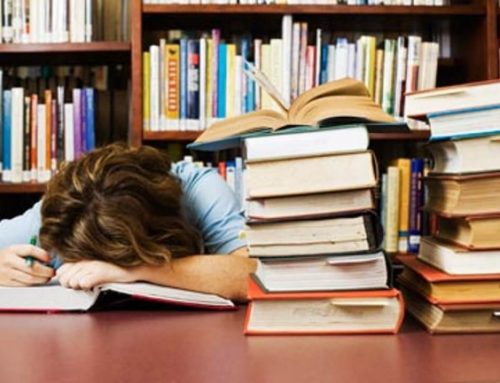


![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)









![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)