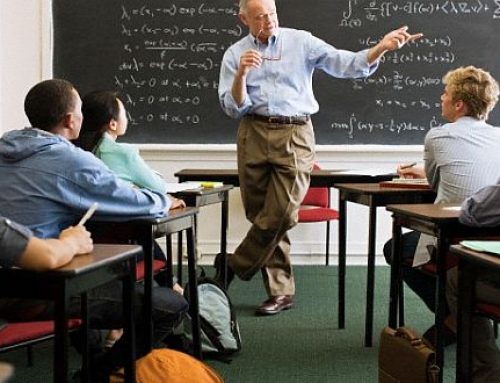Oleh: Dadan Adi Kurniawan
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id
— “Telatan (tidak disiplin waktu) tanda seseorang tidak memiliki rasa hormat dan rasa menghargai pada yang lainnya, tanda menyepelekan orang lain” —
Pendahuluan
Pernahkah menjumpai orang-orang telatan (sering telat) di sekitar kita? Ada kelas jam 07.30 tapi seringnya datang jam 07.45 bahkan lebih. Atau menjumpai teman yang tiap janjian selalu tidak on time (tidak tepat waktu)? Janjian pukul 09.00 datangnya 09.10. Janjian jam 13.00 datangnya jam 13.30. Selalu saja ada alasannya. Yang ini, yang itu. Kemarin begini, sakarang begitu, besuk begini, besuknya lagi begitu, seterusnya!
Selain telatan, pernahkah menjumpai acara-acara yang mulainya sering molor (moloran)? Acara jam 08.00 tapi mulainya jam 08.20 atau acara jam 10.00 tapi mulainya jam 10.30 bahkan lebih. Sering mengalami kasus yang demikian? Bagaimana rasanya? Biasa saja atau gregetan?
Jika merasa “biasa saja”, tandanya negeri ini memang benar-benar sedang “sakit“. Mungkin sekilas terlihat ‘waras’ (karena telat dan molor sudah dianggap hal biasa/lumrah) tetapi sejatinya bangsa yang demikian adalah bangsa yang sedang sakit, tepatnya “sakit kolektif“. Yang menganggap lumrah tidak hanya segelintir orang, melainkan sudah menjadi fenomena umum dan merata di banyak tempat serta kalangan (termasuk kaum intelektual). Bisa dikatakan sudah menjadi “mentalitas bersama” (meskipun tidak semuanya).
Telatan dan Moloran
Telatan (dari kata telat + an) artinya sering datang terlambat dari waktu yang telah ditentukan. Telatnya bisa 1 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 45 menit, 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Yang jelas telah melewati waktu yang telah ditetapkan. Tambahan an di belakang menunjukkan bahwa perilaku telat tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali melainkan “sering” bahkan “selalu”, entah di acara formal maupun nonformal. Telatan menunjukkan suatu habit atau kebiasaan yang telah membudaya pada diri seseorang. Perilaku ini cermin dari “tidak disiplin waktu” dan sikap “nggampangke“ (menyepelekan).
Telat dan telatan merupakan dua hal yang berbeda. Telat belum tentu telatan. Telat tidak selalu menunjukkan kebiasaan (habit). Kejadiannya hanya sesekali (karena suatu hal yang tidak terduga). Namanya hidup terkadang ada hal-hal di luar prediksi dan rencana yang mengakibatkan terlambat menghadiri suatu acara/kegiatan. Kejadiannya benar-benar tidak disengaja. Meski berangkatnya sudah diawalkan terkadang ada faktor X di luar kendali manusia. Kejadiannya tidak sering, melainkan hanya sesekali atau dua kali terjadi (semisal dari 10 kali acara, hanya telat 1 atau 2 kali saja, selebihnya selalu on time).
Adapun telatan bukan disebabkan karena hal-hal tak terduga melainkan sudah menjadi watak, sifat, ciri, kepribadian atau karakter seseorang. Saat longgar pun tetap akan datang telat atau lebih tepatnya “sengaja nelat” (sengaja datang terlambat). Kalau datang tepat waktu justru akan terasa ada yang mengganjal (aneh). Seorang yang berkarakter telatan akan mencari-cari berbagai “alasan fiktif” atau “alasan klasik“ sebagai basis argumentasi atas ketelatannya. Selalu ada saja alasannya. Karena saking seringnya, tak heran bila terkadang sebagian orang atau teman-teman di sekitarnya menjadi muak mendengarkan alasan basi yang sering dilontarkannya.
Telatan sebagai cermin “tidak disiplin waktu” adalah tanda seseorang tidak memiliki “rasa hormat” dan “rasa menghargai” pada yang lainnya, tanda “menyepelekan” orang lain, tanda seseorang tidak punya komitmen dan tanggung jawab. Telat juga merepresentasikan seseorang menyepelekan nilai dari acara atau kegiatan yang dihadirinya. Ia menganggap acara tersebut tidak begitu penting. Yang dipikirkan lebih ke dirinya sendiri. Ia lupa pada hukum sosial bahwa “untuk bisa dihargai maka hargai juga orang lain”.
Budaya telat secara tidak sadar menunjukkan sikap “egois“. Orang-orang telatan sejatinya tidak mampu menghargai orang lain yang telah berjuang datang sesuai waktu yang telah disepakati. Tidak mampu menghargai bagaimana orang lain telah bersusah payah berusaha mendisiplinkan diri agar bisa datang tepat waktu. Mereka yang disiplin waktu sering dirugikan karena harus menunggu kalangan orang-orang telatan. Ketika peserta sudah cukup banyak (menunggu orang-orang telatan terlebih dahulu) biasanya acara baru akan dimulai. Karena mulainya molor, selesainya pun sering kali ikut molor. Jika sudah demikian, tak jarang ada pihak-pihak yang akhirnya dirugikan karena mereka sudah memiliki agenda lain setelah acara tersebut.
Sangat mudah untuk membandingkan orang-orang yang “bermental telatan” dan orang-orang “bermental disiplin”. Dalam suatu kasus yang sama, di mana dua pihak sama-sama memiliki kesibukan dan kompleksitas yang luar biasa di rumah, tetapi akan terlihat dua penyikapan yang berbeda. Orang-orang bermental disiplin akan berusaha memikirkan seribu cara agar bisa hadir tepat waktu (tanpa mencari-cari alasan receh). Adapun orang-orang bermental telatan akan berusaha mencari seribu alasan agar bisa datang telat. Dari sini akan terlihat jelas mana pihak yang memiliki “dedikasi tinggi” (tanggung jawab) dan mana yang “berdedikasi rendah” (nggampangke/menyepelekan).
Secara logika dan etik, kalau sudah tahu acara dimulai pukul 07.00, mestinya datang sebelum jam 07.00. Kalau sudah tahu acara dimulai pukul 09.00, mestinya datang sebelum jam 09.00. Kalau sudah tahu acara dimulai pukul 13.00, mestinya datang sebelum jam 13.00. Mentalitas disiplin mengajarkan seseorang “datang lebih awal ” (semisal kurang 5 menit, 10 menit, 15 menit, atau 30 menit sebelumnya). Jika sudah tahu jalanan macet maka datangnya bisa lebih diawalkan, bukan malah “mengkambinghitamkan” jalanan yang macet tersebut. Kecuali ada hal-hal tak terduga seperti ban bocor, kena tilang, jatuh dari kendaraan, atau lainnya (yang benar-benar tidak disengaja). Membiasakan datang telat meskipun hanya 5 menit atau 10 menit dari waktu yang telah ditentukan tetaplah masuk kategori “budaya telat”. Menormalisasikan budaya telat (meskipun hanya sebentar) pertanda masih memiliki jiwa “meremehkan” orang lain. Sudah sering telat ditambah selalu memberi alasan klasik, sempurnalah sudah. Layak mendapat gelar “sang telatan tulen”.
Budaya Telatan dan Moloran (dari kata dasar molor) telah menjangkiti berbagai lini kehidupan manusia. Budaya ini telah mendarah daging di berbagai acara, kegiatan, atau janjian seperti kegiatan-kegiatan rapat (rapat prodi, rapat organisasi, rapat RT, rapat karang taruna, rapat kantor perusahaan, dll), seminar, kuliah tamu, pembelajaran di kelas sehari-hari, jam berangkat jalan-jalan, nongkrong, dan masih banyak lainnya. Budaya telatan dan moloran telah menjangkiti kegiatan-kegiatan di kantor, di sekolah, di kampus, di pasar, di mall, di kafe, di angkringan, di tempat nongkrong, acara-acara kampung, dan masih banyak lainnya. Menjangkiti urusan pekerjaan atau pun non-pekerjaan. Menjangkiti acara-acara yang sifatnya formal maupun non-formal. Menjangkiti para pejabat, para pendidik, peserta didik, anggota organisasi, para pedagang, teman bermain, dan siapapun. Janjian pukul 07.00 datangnya jam 07.10, janjian pukul 15.30 datangnya jam 16.00, janjian pukul 19.30 datangnya jam 19.50, janjian pukul 10.00 datangnya jam 11.00, dan sejenisnya. Terlihat biasa karena sudah budaya, tetapi di sinilah mirisnya. Mentalitas telatan dan moloran rasanya (seakan) sudah menjadi “mentalitas kolektif” (meskipun masih banyak juga orang-orang disiplin yang menghargai waktu dan menghargai orang lain).
Dalam dunia pendidikan, budaya telat juga menjangkiti banyak “pendidik” (guru, lebih-lebih dosen). Jenis pendidik telatan itu nyata dan banyak jumlahnya. Memang tidak semua, tetapi hampir ditemukan di mana-mana. Pendidik yang sering telat masuk kelas (tanpa keterangan yang jelas dan bersifat mendesak) berarti telah melakukan “korupsi waktu”. Kalau itu dilakukan berulang kali dalam satu semester, berarti ia telah korupsi banyak waktu.
Katakanlah setiap pertemuan seorang pendidik sengaja memulai pembelajarannya telat 15 menit, maka dalam satu semester (katakanlah total dihitung 14 pertemuan) ia telah korupsi waktu sebanyak 210 menit (3,5 jam). Belum lagi jika dihitung dari jumlah kelas dan jumlah mata kuliah yang diampu. Bayangkan jika tiap pertemuan rata-rata telatnya 20-30an menit, maka jumlah korupsi waktunya jauh lebih besar. Secara tidak sadar, sebagian gaji yang diterima ‘mestinya’ haram karena sebagiannya makan “gaji buta“ (gajinya tetap utuh).
Budaya telatan juga banyak dilakukan para mahasiswa saat masuk kelas perkuliahan maupun dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan organisasi kampus. Sebagai contoh misalnya kelas jam 07.00 datangnya jam 07.10, kelas jam 07.30 datangnya jam 07.45, kelas jam 10.00 datangnya jam 10.20, kelas jam 13.00 datangnya jam 13.30, dan sejenisnya. Alasannya beraneka macam mulai dari alasan klasik sampai alasan yang bisa diterima (masuk akal).
Dalam hal berorganisasi juga banyak didapati kasus-kasus yang menunjukkan mentalitas moloran. Sebagai contoh undangan rapat organisasi pukul 08.00 mulainya pukul 08.15, undangan rapat pukul 13.00 mulainya pukul 13.20, undangan acara seminar mahasiswa pukul 09.00 mulainya pukul 09.30, dan sejenisnya. Sepengalaman dan sepengetahuan penulis, jarang kegiatan-kegiatan mahasiswa dimulai tepat waktu. Yang ada selalu molor, entah 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit, bahkan lebih. Sering muncul ungkapan “gak apa-apa, toh cuma molor 10-15 menit. Wajar“. Mentalitas yang demikian sebenarnya mentalitas yang tidak etis. Berarti menormalisasikan budaya tidak disiplin sekalipun hanya 5-15 menit. Yang namanya molor tetaplah molor. Kalau itu diulang-ulang namanya “budaya molor“. Dalam sebuah budaya molor terkandung “mentalitas molor“. Mentalitas inilah cermin suatu organisasi belum mampu mendisiplinkan dirinya sendiri.
Berpijak dari hal tersebut, kiranya dapat diambil suatu hikmah bahwa sepintar dan secerdas apa pun seseorang hendaknya diimbangi sikap disiplin (terutama “disiplin waktu”). Lebih-lebih jika seorang pendidik (entah guru maupun dosen) sebagai teladan murid-muridnya. Disiplin waktu merupakan salah satu “cermin kepribadian” seseorang. Mencerminkan seberapa jauh seseorang tersebut mampu menundukkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Kerap menuntut orang lain untuk tidak telat tetapi diri sendiri sering telat, jelas suatu tindakan konyol dan membagongkan. Akan sangat ironis jika itu dilakukan oleh para pemimpin dan para pendidik, dua profesi yang umumnya diemban oleh kalangan yang katanya “kaum intelektual“. Mestinya bisa menjadi teladan antara omongan dan tindakan!
Ketika seseorang datang terlambat untuk pertama kalinya dan ternyata tidak ada rasa kecewa sama sekali pada diri sendirinya, pertanda ada “krisis diri” yang mesti direnungkan. Satu-dua kali telat kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menimbulkan rasa nyaman yang akhirnya mewujud menjadi “budaya telat”. Sesuatu yang sudah menjadi budaya akan sulit dihilangkan.
Akankah kita menjadi bagian dari penopang sekaligus agen-agen pelestari JAM KARET Indonesia?? Sejatinya budaya jam karet “mengajarkan” dan “mewajarkan” masyarakat Indonesia berkarakter menyepelekan, tidak menghargai orang lain, tidak menghargai waktu. Kuatnya budaya JAM KARET di Indonesia mengindikasikan bahwa keberadaan jam dinding, jam tangan, dan jam di HP hanyalah “pajangan semata“, tak terlalu berguna.
Meskipun jam-jam tersebut masih hidup, berfungsi dan dipakai ke mana-mana (sebagai penanda waktu), tetapi kesadaran para pemakainya sudah banyak yang mati. Bangsa ini mengalami krisis kesadaran akan disiplin waktu. Buktinya masih banyak yang telatan dan moloran, padahal mereka punya jam dan bisa baca jam. Masa iya telatan dan moloran karena “buta jam” (tidak bisa membaca jam)? Tampaknya bukan buta jam, tapi buta kesadaran.
Telatan dan Moloran (JAM KARET) menunjukkan suatu mentalitas pelakunya. Karena pelakunya banyak bisa disebut “mentalitas kolektif”. Mentalitas telatan dan moloran yang menjangkiti masyarakat luas inilah salah satu faktor penghambat majunya bangsa Indonesia. Bagaimana suatu bangsa akan melangkah maju sedangkan bangsa itu sendiri belum mampu mendisiplinkan dirinya sendiri!
Nesuan
Pernahkah menjumpai seseorang yang bertipikal nesuan? Apa itu nesuan? Nesuan dari kata dasar nesu yang berarti ‘marah’. Nesuan (nesu + an) merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang berarti mudah marah, sering marah, sedikit-sedikit marah. Hal-hal sederhana yang mestinya bisa dibicarakan baik-baik tetapi disikapi secara tempramen. Hal-hal kecil menjadi besar karena dibesar-besarkan. Temperamen adalah bagian dari karakter seseorang yang memengaruhi perbuatan, perasaan, dan pikiran. Nesuan kerap menimbulkan suasana menjadi kurang kondusif seperti tegang dan saling tidak enakan entah untuk sementara waktu saja atau dalam waktu yang lama.
Ekspresi nesu atau marah seseorang bisa dilakukan secara verbal yakni melalui lisan (mulut) secara terang-terangan. Contohnya seperti dengan cara memarahi, mengomeli, memaki-maki, memprotes, mengumpat, dan sejenisnya. Di sisi lain, marah juga bisa diekspresikan secara non-verbal seperti melalui sikap diam, tatapan tajam, dan gerakan badan (seperti menendang, memukul, mencoret-coret, dan lainnya). Terkadang “diam“ (mendiamkan orang lain) justru merepresentasikan tingkat kemarahan yang lebih besar. Mendiamkan seseorang dalam jangka waktu lama menunjukkan seseorang memiliki kemarahan yang luar biasa yang baginya sulit dimaafkan.
Wajarkah manusia “marah” (nesu)? Sangat wajar, sangat manusiawi. Kalau tidak pernah marah justru bukan manusia. Dalam kondisi-kondisi tertentu manusia pasti dihadapkan pada cobaan berat yang menantang sisi emosionalnya. Karena berbagai faktor yang mendasar, manusia akhirnya marah. Itu wajar sekali. Sesekali memuntahkan kemarahan juga penting untuk menjaga keseimbangan dan kewarasan hidup. Tetapi bagaimana jika sedikit-sedikit marah alias nesuan? Di sinilah menjadi “tidak wajar”. Ada sesuatu yang “tidak balance“, ada sesuatu yang “tidak beres“ dalam diri seseorang yang nesuan.
Bad Mood-an
Pernahkah di kelas menjumpai seorang pendidik yang bad mood-an (suasana hati yang buruk, cenderung labil)? Atau seorang pendidik yang sering membawa masalah di luar ke dalam kelas? Biasanya peserta didik menjadi korbannya. Tidak tahu apa-apa dan tidak melakukan apa-apa tetapi tiba-tiba kena omel, kena semprot, kena marah, atau kena cuek si pendidik. Hidup memang kadang memiliki banyak masalah seperti masalah keluarga, masalah asmara, masalah pertemanan, dan lainnya. Namun demikian, seorang pendidik seharusnya bersikap profesional, bisa melihat tempat dan kondisi. Sebisa mungkin tidak mudah badmood di kelas, tidak membawa masalah keluarga atau masalah dari luar ke dalam kelas pembelajaran.
Mutungan
Pernahkah menjumpai orang bertipikal mutungan? Apa itu mutungan? Mutungan (dari kata mutung + an) merupakan suatu istilah dalam bahasa Jawa yang berarti sikap seseorang yang mudah ngambek, jengkel, merajuk, kesal dan akhirnya pergi meninggalkan. Istilah ini biasanya identik dengan persoalan-persoalan ringan yang sebenarnya kurang begitu penting (mendasar). Namun karena sensibilitasnya tinggi, seseorang menjadi mudah tersinggung, baperan, sakit hati, dan akhirnya patah hati.
Sebagai contoh ada sekelompok orang sedang ngumpul dalam rangka persiapan touring bersama. Sebelum berangkat mereka ngobrol bersama. Dalam percakapan tersebut secara tidak sengaja muncul candaan agak aneh. Bagi sebagian besar orang di kelompok tersebut tidak ada masalah terhadap candaan tersebut, tetapi ada satu orang yang menganggap itu serius. Akhirnya satu orang tersebut patah hati dan memutuskan langsung pergi dan tidak jadi ikut touring. Tanpa dialog dahulu, ia langsung pergi meninggalkan kawan-kawannya. Ia langsung keluar group WA.
Mutung atau mutungan ini bisa dinilai negatif atau positif, tergantung sudut pandang yang digunakan. Tetapi secara umum, mutungan lebih sering ditempatkan pada konotasi negatif. Mutungan lebih dekat pada simbol “ketidakdewasaan“ (seperti anak kecil) dan simbol “keegoisan“. Sedikit-sedikit mutung, sedikit-sedikit mudah ngambek, sedikit-sedikit mudah tersinggung, sedikit-sedikit tidak jadi. Hal-hal tidak cocok yang mestinya bisa dibicarakan dulu secara baik-baik tetapi lebih memilih mutung secara sepihak.



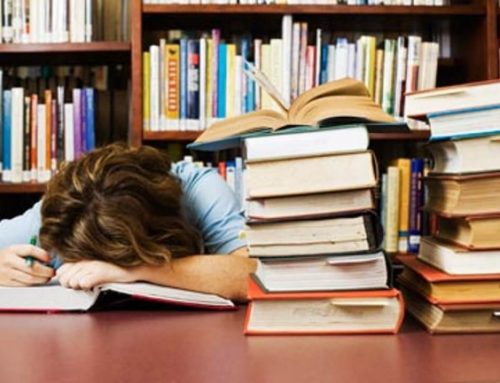


![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)








![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)