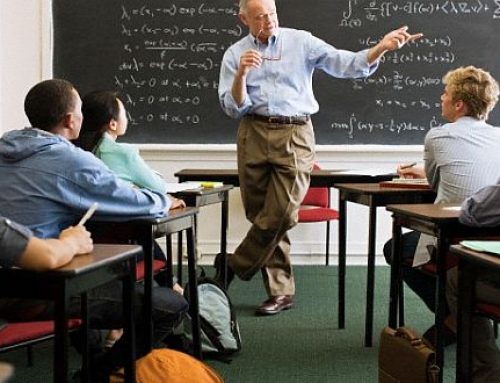Views: 58
Views: 58
Oleh: Dr. Hieronymus Purwanta, M.A.
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: hpurwanta@staff.uns.ac.id
Pendahuluan
Dalam pelajaran sejarah, “Hindu” dipahami sebagai nama agama, bahkan digunakan untuk menamai suatu periode sejarah Indonesia yang disebut masa Hindu-Buddha. Apakah penamaan itu tepat? Kalau tidak tepat, pendidikan sejarah sudah merusak pemikiran jutaan generasi muda yang pernah menerima pelajaran sejarah di sekolah, termasuk gurunya. Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri asal-usul istilah tersebut dan memahami konteks budaya historisnya.
Asal-usul Nama “Hindu”
Kata Hindu berasal dari bahasa Persia kuno. Istilah ini digunakan oleh bangsa Persia untuk menyebut penduduk di seberang timur Sungai Indus, yakni wilayah yang kini menjadi bagian dari India utara. Dalam bahasa Sanskerta, kata yang mirip adalah Sindhu (सिन्धु), yang berarti “sungai besar”, dan secara khusus merujuk pada Sungai Indus beserta daerah di sekitarnya. Pergeseran kata Sindhu dari bahasa Snaskerta menjadi Hindu dalam bahasa Persia lebih merupakan adaptasi kebahasaan dan tidak mengubah maknanya, yaitu secara geografis untuk menamakan wilayah sebelah timur Sungai Indus dan secara antropologis untuk menyebut penduduk yang tinggal di daerah tersebut (Flood, 1996).
Mengapa Hindu berubah dari nama etnis menjadi nama kepercayaan atau agama? Perubahan makna dari nama etnis menjadi nama kepercayaan baru terjadi pada masa penjajahan Inggris di India. Pada abad ke-18, para sarjana Barat (orientalis) mulai meneliti adat, hukum, dan teks kuno India. Sir William Jones, misalnya, mendirikan Asiatic Society of Bengal (1784) dan menerjemahkan Manusmṛti (Hukum Manu). Teks ini kemudian dijadikan dasar hukum yang oleh pemerintah kolonial Inggris disebut “Hindu Law” untuk mengatur perkawinan, warisan, dan moralitas masyarakat India (Doniger & Smith, 1991). Melalui proses kategorisasi kolonial inilah lahir istilah Hinduisme, suatu label yang diciptakan oleh kaum orientalis untuk menyebut penduduk India non-Muslim, non-Kristen, dan non-Buddha. Max Müller pada abad ke-19 memperkuat konstruksi ini dengan mengedit dan menerbitkan teks-teks Weda yang disebutnya sebagai “kitab suci Hindu” (Müller, 1891). Sejak itu, “Hindu” tidak lagi sekadar penanda geografis, tetapi menjadi istilah religius dalam pengertian Barat.
Masalah muncul ketika istilah tersebut digunakan untuk menamai tata nilai dan sistem kepercayaan di Asia Tenggara. George Coedès (1975) mengemukakan teori Indianisation of Southeast Asia, yakni bahwa sejak abad ke-4 M masyarakat Asia Tenggara telah menerima ekspansi peradaban India, termasuk agama Hindu dan Buddha. Pandangan ini bersifat distortif dan bahkan destruktif karena menganggap terjadi proses pasifikasi satu arah dari India ke Asia Tenggara. Sementara itu, Sanātana Dharma yang sering disepadankan dengan “agama Hindu” pada dasarnya bukanlah agama dalam arti institusional, melainkan way of life lokal masyarakat lembah Sungai Indus. Ia tidak memiliki semangat ekspansi seperti agama Kristen atau Islam. Kedua, pandangan Coedes juga bersifat spekulatif karena tidak didukung oleh bukti historis yang kuat baik dari sisi India maupun Asia Tenggara.
Hubungan antara India dan Asia Tenggara terutama adalah perdagangan. Catatan historis menunjukkan bahwa pada pertengahan abad ke-3 Kerajaan Funan di Kamboja selatan (sekarang masuk wilayah Vietnam) mengadakan ekspansi perdagangan ke India. Vickery (2003: 108) mengutip catatan Cina tentang pengiriman utusan ke India sebagai berikut:
Fan Chan mengirim seorang utusan ke India. Ia menyusuri pantai [sisi barat semenanjung], kemudian menyusuri sungai India [Gangga?], dan membutuhkan waktu lebih dari satu tahun untuk mencapai kota raja India. Raja India terkejut melihatnya karena ia tidak tahu apa-apa tentang Funan. Ia mengirim seorang utusan ke Funan dengan 4 ekor kuda; utusan India tersebut berangkat bersama utusan Funan, dan mereka mencapai Funan dari India 4 tahun setelah utusan Funan dikirim ke India.
Interaksi kultural merupakan akibat sampingan dari hubungan perdagangan yang semakin intensif. Tidak ada unsur pasifikasi atau dominasi di dalamnya, melainkan pertukaran simbol, gagasan, dan praktik budaya dalam suasana kesetaraan yang mengiringi interaksi perdagangan.
Setelah dibawa pulang oleh para pedagang, hasil kebudayaan India kemudian diolah untuk memperkuat way of life Asia Tenggara. Dalam konteks ini, proses tersebut dapat dipahami lebih sebagai bentuk traveling theory (Said, 1983), yakni ketika ide-ide dan simbol budaya berpindah lintas ruang dan mengalami reinterpretasi di tempat baru, sebagaimana teori kolonial dalam Black Skin, White Masks (Fanon, 1952) yang ditransformasi menjadi wacana perlawanan terhadap hegemoni. Oleh karena itu, sepanjang periode ini tidak pernah terjadi gerakan pemurnian seperti Kristen di Eropa (Reformasi) maupun Muhammadiyah di Yogyakarta.
Berkenalan dengan Sanātana Dharma
Sanātana Dharma secara harfiah berarti “hukum abadi” atau “tatanan yang kekal”. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai ajaran moral baik-buruk sebagaimana hukum abadi yang dipahami dalam agama-agama samawi yang bersumber pada kehendak Tuhan personal. Hukum abadi atau kekal dalam Sanātana Dharma dimaksudkan untuk menamai tata cara ritual (yajña), seperti aturan tentang urutan acara, syair (mantra) yang harus dilantunkan dan sesaji yang harus disediakan untuk persembahan agar upacara yang dilakukan dapat mengembalikan harmoni alam.
Gagasan tentang harmoni alam sebagai tujuan tertinggi bukan milik India secara ekseklusif, tetapi kebudayaan itu berkembang luas di seluruh masyarakat Asia Selatan, Tenggara, dan Timur. Hanya berbeda dalam bentuk ritus, sikap, dan tindakan yang harus dilakukan untuk menjaganya. Di masyarakat sekitar Sungai Indus, penegakan harmoni alam (ṛta) diwujudkan melalui pelaksanaan yajña: ritual di depan altar api yang disertai lantunan syair-syair dalam bahasa Sanskerta, bahasa yang dianggap suci dan digunakan untuk berkomunikasi kaum brahmana dengan dunia atas. Ketepatan tahapan, kejelasan pengucapan dan intonasi dalam melantunkan mantra, serta kesucian sikap para pelaku upacara sangat diperhatikan agar keseimbangan semesta dapat ditegakkan kembali. Syair dan mantra pun sudah ditetapkan dengan rinci: Rigveda untuk syair-syair pujian (sūkta) kepada penguasa dunia atas; Samaveda untuk syair-syair nyanyian untuk mengiringi ritual (udgātṛ); Yajurveda untuk rumusan mantra dan instruksi praktis bagi pelaksana ritual (adhvaryu); dan Atharvaveda untuk mantra-mantra magis penolak bala. Inilah yang dimaksud dengan hukum abadi atau Sanātana Dharma.
Ritual masyarakat sekitar Sungai Indus ditujukan kepada dunia atas yang diyakini sebagai penguasa dunia bawah, yaitu: Agni – penguasa api; Indra – penguasa langit; Varuṇa – penguasa laut; Sūrya – penguasa cahaya; dan Vāyu – penguasa angin. Dalam kerangka ini, yajña merupakan upacara persembahan kepada para penguasa dunia atas tersebut agar keteraturan dan harmoni kosmos dapat dipertahankan. Upacara ini tidak dimaksudkan sebagai penyembahan dalam pengertian teistik seperti pada agama samawi, melainkan sebagai tindakan menjaga keselarasan antara manusia dan dunia atas agar terdapat harmoni di dunia bawah, inti dari Sanātana Dharma.
Sampai disini sudah paham? Istilah Hindu pada awalnya bermakna geografis dan antropologis. Menjadi istilah untuk nama kelompok masyarakat India yang bukan Islam, Kristen, maupun Buddha terjadi pada masa kolonialisme Barat di India. Dari sini istilah Hindu berkembang untuk menamai local wisdom masyarakat lembah sungai Indus sebagai agama. Salah satu unsur dominan dalam Hindu adalah Sanātana Dharma, tata laksana upacara persembahan masyarakat India di sekitar Sungai Indus untuk dunia atas.
Daftar Pustaka
Coedès, G. (1975). The Indianized States of Southeast Asia (W. F. Vella, Ed.; S. B. Cowing, Trans.). Australian National University Press. https://openresearch-repository.anu.edu.au/items/bc4b4619-34db-46f1-8358-c35e97778ce3
Doniger, W., & Smith, B. K. (1991). The Laws of Manu. Penguin Classics.
Fanon, F. (1952). Black skin, white masks. Paris: Éditions du Seuil.
Flood, G. (1996). An Introduction to Hinduism. Cambridge University Press. https://archive.org/details/anintroductiontohinduismgavinfloodd.oupseeotherbooks_355_z
Gonda, J. (1975). Vedic Ritual: The Non-Solemn Rites. Brill.
Higham, C. (2014). Early Mainland Southeast Asia: From First Humans to Angkor. River Books.
Knipe, D. M. (2015). Vedic Voices: Intimate Narratives of a Living Andhra Tradition. Oxford University Press.
Manguin, P.-Y. (2011). The archaeology of early maritime polities of Southeast Asia. In J. G. Butcher & E. Tagliacozzo (Eds.), Oceanic Connections: Southeast Asia and the Wider World (pp. 67–93). Cambridge University Press.
Said, E. W. (1983). the World, the Text, and the Critic. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Vickery, Michael. 2003. Funan Reviewed : Deconstructing the Ancients. Bulletin de l’Ecole française d’Extrême-Orient. Tome 90-91, hlm. 101-143.
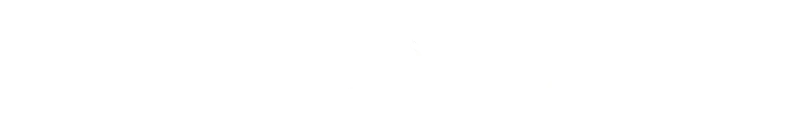

![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)






![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)