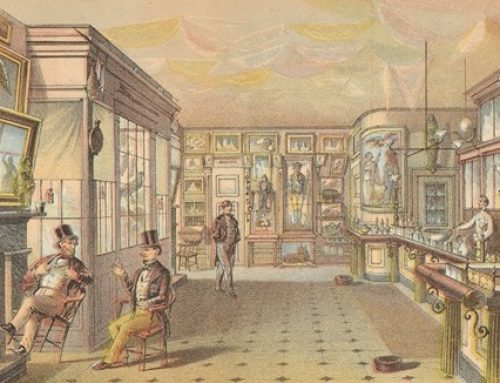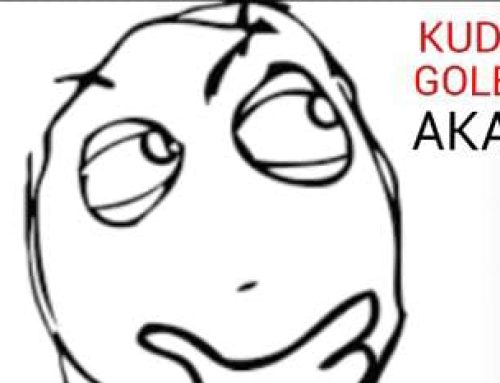Views: 68
Views: 68
Oleh: Dadan Adi Kurniawan
Staff Pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret, Surakarta
Gambar R.A. Kartini (paling kiri) bersama dua saudaranya

https://luk.staff.ugm.ac.id/itd/Kartini/01.html (Sumber asli diambil dari Collectie Tropenmuseum)
Riwayat Singkat R.A. Kartini
- Lahir: 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah.
- Meninggal: 17 September 1904 di Rembang, Jawa Tengah.
- Umur: 25 tahun lebih.
- Makam R.A. Kartini: Di Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab. Rembang, Jawa Tengah.
- Museum R.A. Kartini: Ada 2 tempat yaitu Museum R.A. Kartini di Rembang (diresmikan pada 21 April 1967) dan Museum R.A. Kartini di Jepara (diresmikan pada 21 April 1977).
- Sekolah: di ELS (Europesche Lagere School) di Jepara tahun 1985-1892, sebuah sekolah dasar berbahasa Belanda.
- Orang Tua: merupakan putri dari pernikahan R.M.A.A. Sosroningrat dengan Mas Adjeng Ngasirah pada tahun 1872.
- Profil Orang Tua: R.M.A.A. Sosroningrat (ayah R.A. Kartini) merupakan seorang bupati Jepara, sedangkan Mas Adjeng Ngasirah (ibu kandung R.A. Kartini) merupakan anak seorang ulama bernama Kyai Haji Madirono dan Nyai Haji Siti Aminah.
- Status Ibu Kandung: Mas Adjeng Ngasirah (ibu kandung R.A. Kartini) dijadikan sebagai garwa ampil (semacam selir alias bukan istri resmi/istri utama).
- Status Ibu Tiri: R.M.A.A. Sosroningrat melakukan poligami yakni menikah lagi (tahun 1875) dengan Adjeng Woerjan (anak dari Titrowikromo, seorang bupati Jepara). Raden Adjeng Woerjan dijadikan garwa padmi (permaisuri/istri utama/istri resmi).
- Jumlah Saudara: Dari Mas Adjeng Ngasirah (ibu kandung) dikaruniai 8 anak (R.A. Kartini merupakan anak perempuan tertua). Adapun dari Raden Adjeng Woerjan (ibu tiri), memiliki 3 anak. Total 11 anak (R.A. Kartini memiliki 10 sudara).
- Inspirator: Kartini belajar dan terinspirasi salah satunya dari seorang pejuang wanita di India bernama Pundita Ramambai.
- Membuang Gelar: Tahun 1899, RA Kartini menanggalkan gelar kebangsawanannya (R.A.) sehingga lebih memilih hanya dipanggil Kartini saja (tanpa embel-embel Raden Ajeng atau R.A.)
- Usaha Mendapatkan Pendidikan Lanjut: Pernah mencari beasiswa sekolah ke Belanda (1903) tetapi ditolak J.H. Abendanon (menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda, 1900-1905). Kemudian pernah berkeinginan melanjutkan sekolah di Batavia tetapi ditolak ayahnya, R.M.A.A. Sosroningrat.
- Dilamar: Tinggal menunggu panggilan beasiswa dari Gubernur Jendral tetapi tidak jadi diambil karena pada 23 Juli 1903, ia dilamar Adipati Djojo Adiningrat (seorang bupati Rembang).
- Menikah: R.A. Kartini menikah dengan R. Adipati Djojo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Setelah menikah, R.A. Kartini tidak lagi di Jepara melainkan tinggal di Rembang mengikuti suaminya.
- Melahirkan: R.A. Kartini melahirkan anak pertama dan satu-satunya pada tanggal 13 September 1904, yang diberi nama Soesalit Djojoadhiningrat. Empat hari setelah melahirkan (tepatnya pada 17 September 1904), R.A. Kartini menghembuskan nafas terakhirnya.
- Mendirikan Sekolah: R.A. Kartini diizinkan suaminya untuk mendirikan sekolah perempuan di sebelah timur pintu gerbang kompleks kantor Kabupaten Rembang.
- Perhatian terhadap Ukiran Jepara: Pada akhir abad 19, RA Kartini pernah membantu memperkenalkan hasil kerajinan ukiran kayu Jepara kepada orang-orang di Batavia (Jakarta).
- Pertemuannya dengan KH Sholeh Darat: Pernah diajak ayahnya pergi ke Semarang mengikuti acara pengajian yang diisi oleh KH Sholeh Darat. KH Sholeh Darat sendiri merupakan salah satu guru KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah di Yogyakarta) dan KH Hasyim Asy’ari (pendiri NU di Jombang).
- Profil KH Sholeh Darat: KH Sholeh Darat merupakan salah satu kyai pelopor yang menerjemahkan Alquran dan Kitab ke dalam bahasa Jawa dengan huruf Pegon (Arab gundul). Penyebabnya karena era itu banyak orang awam yang hanya diajarkan hafalan tanpa mengerti arti atau maksud dari apa yang dibaca sehari-hari ketika sembahyang (beribadah). R.A. Kartini sempat mengeluhkan sistem belajar agama di lingkungan tempat tinggalnya (dan mungkin kebanyakan di Jawa saat itu) dan menyampaikannya kepada KH Sholeh Darat di Semarang.
- Relasi atau Korespondensi Surat-Menyurat R.A. Kartini: Dalam kesehariannya, R.A. Kartini bernah berkirim dan berbalas surat antara lain kepada: (a) Estelle Zeehandelaar, (b) J.H. Abendanon, (c) Nyonya Abendanon, (d) Nelly Van Kol, (e) Letsy, (f) Stella, (g) Ovink Soer, dan lainnya.
- Kontroversi seputar R.A. Kartini: (1) perihal sebab-musabab meninggalnya, (2) seputar alasan sebenarnya ia tidak diperkenankan sekolah ke Belanda maupun ke Batavia, (3) alasan mengapa R.A. Kartini yang dipilih sebagai simbol utama tokoh emansipasi wanita di Indonesia, padahal ada tokoh perempuan lain yang oleh sebagian kalangan dianggap lebih hebat dan pantas.
Riwayat Beberapa Tulisan Kartini di Media Massa
- “Het Huwelijk bij de Kodja’s” di Bijdragen tot de Tall, Land-en Volkenkunde (1899).
- “Een Gouvernours Generaalsdag” di de Echo (1900).
- “Van Een Vergeten op de Ree” di de Echo (1900).
- “Van Een Vergeten Uitboekje” di Eigen Haard (1903).
- “Ontgoocheling” di Weekblad voor Indie (1904).
Catatan: Di dalam tulisan surat-surat dan artikel media massa yang ditulis R.A. Kartini, di dalamnya berisi/tercermin: kegalauan, keluh kesah, protes, dan harapan yang memperlihatkan “pergulatan pikir dan batin” (pemikiran dan perasaan). Kegalauan tidak hanya menyoroti perihal tatanan Jawa lingkungan di sekitarnya, tetapi juga apa yang menimpa di keluarganya (semisal ibunya dipoligami), kemudian apa yang dialaminya semisal tidak diperbolehkan sekolah ke Belanda/Batavia, dll. Kegalauan semakin menjadi karena R.A. Kartini kemudian membandingkannya dengan nasib dunia perempuan di luar negeri yang berbeda (yang lebih bebas). Pemahaman tersebut diketahuinya dari hasil surat-menyurat dengan rekan-rekan korespondensinya di luar negeri.
Kultur Jawa era R.A. Kartini
Untuk memahami perjuangan Kartini, maka harus paham terkait Kultur Jawa (tatanan sosial budaya Jawa) saat itu. Jangan dibayangkan kultur Jawa saat itu persis seperti saat ini. Lalu seperti apakah kultur Jawa abad 19-awal abad 20?
1. Kuatnya Sistem Patriarki
Perempuan menjadi obyek yang tersubordinasi (dibawah kuasa laki-laki). Perempuan terhegemoni oleh laki-laki dalam banyak hal.
2. Urusan wanita hanya di belakang
Perempuan mengalami domestifikasi (mengurusi hal-hal domestik/lokal alias urusan dalam rumah saja). Urusan sosial menjadi ruang dominan laki-laki.
3. Merebaknya Poligami
Laki-laki (utamanya bangsawan atau ningrat) umumnya memiliki istri lebih dari satu. Artinya perempuan saat itu menghadapi tradisi harus siap dimadu, diduakan, ditigakan, diempatkan, dst. Dalam kata lain, perempuan Jawa saat itu harus siap “cintanya dibagi”.
4. Kawin Paksa
Perempuan sering dijodohkan paksa oleh orang tuanya, entah alasan mencari status sosial atau karena jerat hutang, baik hutang uang atau hutang budi. Artinya banyak perempuan Jawa yang menikah bukan karena pilihannya sendiri. Ia menjalani rumah tangga dalam kondisi “perasaan yang dipaksa”.
5. Sistem Pingit
Setelah beranjak remaja (biasanya ukurannya bila sudah mengalami menstruasi pertama kali) maka tidak boleh sembarangan keluar rumah tanpa ada yang mendampingi. Sistem pingit ibarat sebuah “penjara” bagi kaum perempuan (terutama perempuan kaum ningrat).
6. Tuntutan menjadi “Wanita Sejati”
Ada tuntutan kepada perempuan ningrat untuk belajar menata diri supaya menjadi wanita sejati. Wanita kerap diartikan “wani ditata” (istilah bahasa Jawa yang artinya berani ditata atau berani diatur). Ditata cara bicaranya, cara jalannya, cara berpakaiannya, cara dandannya, cara melayani suaminya, dan lain-lain. Berbeda dengan makna perempuan yang diyakini berasal dari kata “empu” yang artinya tuan, ahli, terhormat, mulia. Itulah sebabnya istilah perempuan lebih banyak dipilih oleh kelompok-kelompok pejuang emansipasi atau pejuang kesetaraan, ketimbang istilah wanita yang cenderung memiliki konotasi negatif.
7. Wanita tidak diajarkan memahami Kitab Suci
Pada saat R.A. Kartini hidup (abad 19-awal abad 20), wanita atau perempuan pada umumnya tidak diperkenankan memahami kitab suci (Alquran dan kitab-kitab lainnya) secara lebih jauh. Mempelajari dan mendalami kitab suci menjadi domain kaum laki-laki, terlebih khusus para pemuka agama (agamawan). Terdapat proses penghalangan yang terstruktur agar pengetahuan wanita terhadap isi kitab suci dibatasi. Ada semacam ketakutan jika perempuan memiliki wawasan luas (khususnya soal agama) akan merusak tatanan sosial, tradisi dan budaya yag sebelumnya telah menjadi “panggung kuasa” yang mapan bagi kaum laki-laki.
8. Pendidikan bagi perempuan tidak penting
Selaras dengan poin nomor 2 di atas, pendidikan bagi perempuan saat itu tidaklah penting. Anggapan umum bagi kaum perempuan saat itu ya urusannya dapur, sumur dan kasur, atau masak, macak, dan manak. Saat itu, perempuan Jawa yang sekolah merupakan sebuah ketidaklaziman (sangat langka dan menyalahi tradisi). Mentalitas yang tertanam saat itu adalah “buat apa perempuan sekolah, tidak ada gunanya, perempuan tugasnya di rumah, mengurus anak, mengurus rumah dan melayani suami”. Bahkan sampai sekarang pun masih ada sebagian orang yang memiliki pemikiran “buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, perempuan tugasnya ngurus anak di rumah”.
Riwayat Pembukuan Surat-Surat Kartini
Berkat andil orang/pihak lain (pasca meninggalnya R.A. Kartini), surat-surat dan berbagai tulisan R.A. Kartini pada akhirnya dibukukan, dicetak dan disebarluaskan. Tidak hanya di Hindia Belanda (Indonesia saat itu), tetapi juga hingga ke mancanegara dengan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Setidaknya sampai tahun 1960, terdapat total terjemahan ke 9 bahasa yaitu bahasa Belanda, Inggris, Melayu, Arab, Sunda, Indonesia, Jawa, Jepang, dan Perancis. Tidak sembarang karya bisa tembus ke dalam jumlah terjemahan bahasa sebanyak ini.
Tentu secara “langsung”, R.A. Kartini tidak terlibat, karena ketika pembukuan demi pembukuan berlangsung, ia telah meninggal jauh sebelumnya. Tetapi “secara tidak langsung”, semua karya-karya tersebut diterbitkan karena tertarik akan mutiara pergulatan pikir dan batin yang diwariskan R.A. Kartini. Pergulatan pikir dan batin Kartini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk ukuran zamannya (jangan dibandingan di era sekarang yang sudah jauh berbeda). Untuk bisa menyelami secara lebih utuh, maka kita harus membayangkan suasana kehidupan kultur Jawa saat itu. Berikut riwayat pembukuan surat-surat R.A. Kartini:
- 1911 (7 tahun setelah meninggalnya R.A. Kartini): H. Abendanon menyusun dan menerbitkan surat-surat kartini menjadi sebuah buku dengan judul Door Duisternis tot Licht yang artinya Melalui Gelap Menuju Terang. Setahun berikutnya (1912), buku berbahasa Belanda ini sudah cetak 3x (best seller).
- 1920: Agnes Louise Symmers menerjemahkan Door Duisternis tot Licht ke dalam sebuah buku berbahasa Inggris di New York dengan judul Letters of a Javanese Princess (cetak 6 kali).
- 1922: Balai Pustaka (diterjemahkan oleh Empat Bersaudara) menerbitkan buku dalam terjemahan bahasa Melayu di Batavia dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang: Boeah Pikiran.
- 1926: Alayeh Thouk menerbitkan buku dalam terjemahan bahasa Arab di Lebanon dengan judul Alhajat Alkadimat Walruh Alhadissya: Bikalam Raden Adidjin Kartini.
- 1930: R. Sutjibrata menerbitkan buku dalam terjemahan bahasa Sunda dengan judul Ti Noe Pek Ka Noe Tjaang.
- 1938: Armijn Pane (sastrawan) menerbitkan buku dalam terjemahan bahasa Indonesia dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang (dalam perkembangannya bisa cetak 11 kali, paling laris di Indonesia).
- 1938: Ki Sastrasuganda menerbitkan buku dalam terjemahan bahasa Jawa dengan judul Mboekak Pepeteng.
- 1955: terbit buku dalam terjemahan bahasa Jepang dengan judul Hi Kariwa Ankoku wo Koete: Kartini no Tegami.
- 1960: terbit buku dalam terjemahan bahasa Perancis dengan judul Lettres de Raden Adjeng Kartini: Java en 1900.
Nama “R.A.Kartini” juga sering disebut oleh para sejarawan dalam karya-karyanya
- Peter Blumberger (1931)
- S. Furnivall (1939)
- George McTurman Kahin (1952)
- F.wetheim (1959)
- Pramoedya Ananta Toer (1961), dalam judul “Panggil Aku Kartini Saja”.
- Alexander Belenkiy (1966)
- Haryati Soebandio (1979)
- Abdurrachman Surjomihardjo (1990), dll.
Apa Sumbangsih Kartini?
Secara langsung ataupun tidak langsung, R.A. Kartini telah memiliki kontribusi:
- Turut menggoyahkan belenggu domestik menuju penguasaan ranah publik (lokal, nasional, internasional).
- Perempuan kian menemukan ‘kehormatannya’ (khususnya dalam dunia pendidikan).
- Meninggalkan “warisan batin” yang pada akhirnya menjadi world heritage (warisan dunia).
- Tahun 1921, Raden Adjeng Mirjam adalah perempuan bumiputera pertama yang menginjakkan kaki (belajar) di Belanda.
- Munculnya Sekolah Kartini di Semarang, yang kemudian meluas di beberapa kota. Pendanaan sekolah-sekolah Kartini dibiayai Kartini Fonds oleh Yayasan Kartini yang didirikan tahun 1910 di Belanda oleh JH Abendanon dan C.Th. van Deventer.
Apakah Kartini seorang pahlawan yang berjuang mengusir penjajah kolonial?
Dari kacamata Indonesiasentris (tolak ukurnya anti Belanda) maka R.A. Kartini bukanlah seorang pahlawan. R.A. Kartini tidak berjuang melawan Belanda (kolonialisme) layaknya seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Nyi Ageng Serang, atau lainnya yang berperang memikul senjata di medan laga. Teman-teman dan korespondensinya pun justru orang-orang (utamanya perempuan) Belanda. Namun begitu, R.A. Kartini merupakan pahlwan yang bersumbangsih dalam melawan kultur (kungkungan adat tradisional) dan memperjuangkan keselarasan dan kesetaraan (khususnya di bidang pendidikan). Penghargaan jasanya (kepahlawannannya) bukan melawan “penjajah dari luar” (Belanda) tetapi “penjajah dari dalam” dalam wujud belenggu dunia tatanan Jawa.
Asal-Usul Tradisi Memperingati Hari Kartini
Melihat fenomena adanya perayaan hari kelahiran R.A. Kartini yang telah ada sejak tahun 1920-an (era kolonal), maka pada tahun 1964, melalui Surat Keputusan Presiden (Keppres) No.108 tahun 1964 yang ditandatangani tanggal 2 Mei 1964, presiden Soekarno menetapkan bahwa tanggal 21 April sebagai “Hari Kartini”. Selain itu R.A. Kartini juga ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional (belakangan menjadi Pahlawan Nasional). Jauh sebelumnya, W.R. Supratman juga telah menciptakan lagu “Ibu Kita Kartini” (tahun 1928/1929?).
Penetapan Hari Kartini dan sebagai Pahlawan Nasional inilah yang kerap dianggap sebagai faktor “politik” (keputusan pemerintah). Sesuatu dikatakan politis biasanya disebabkan karena bisa jadi ada kepentingan praktis tertentu di dalamnya oleh si penguasa. Atau ada faktor like dan dislike (suka dan tidak suka) sehingga menyebabkan pemerintah bisa saja menyetujui atau menolak suatu usulan penetapan pahlawan, bukan berdasar kondisi obyektif keilmuan (ilmiah).
Faktor Eksternal yang membuat nama R.A. Kartini menjadi terkenal (populer)?
Di luar kuasa diri R.A. Kartini sendiri ketika masih hiudp, terdapat peran besar eksternal dari orang lain. Peran besar tersebut terutama berlangsung justru setelah Kartini wafat. Tokoh-tokoh atau pihak yang berperan besar “mengorbitkan” R.A. Kartini antara lain J.H. Abendanon, para penerjemah dan penerbit, para penulis buku (bahkan hingga saat ini masih ada yang menulis), penelitian-penelitian di Perguruan Tinggi, peran pemerintah pusat (terutama sejak era Soekarno), dan peran pemerintah daerah. Kebetulan R.A. Kartini meninggalkan warisan yang begitu berharga yang mana warisan tersebut ternyata masih utuh (terdokumentasikan) dan mampu ditangkap serta dieksekusi dengan baik oleh orang-orang di sekitarnya pada era setelahnya. Artinya ada “modal” yang ditinggalkan yang menarik dan dianggap begitu penting untuk diterbitkan dan disebarluaskan. Tanpa adanya “modal menarik” tersebut, sulit rasanya orang-orang melirik sosok R.A. Kartini untuk terus didokumentasikan.