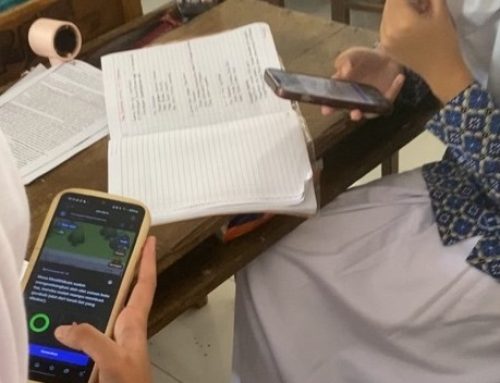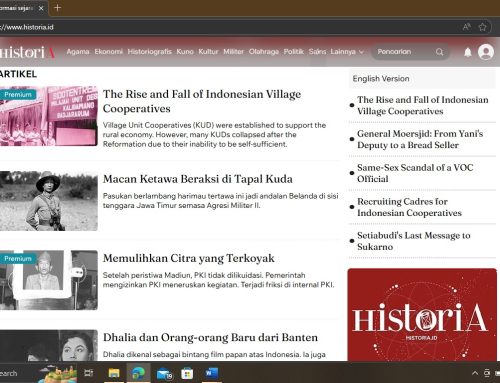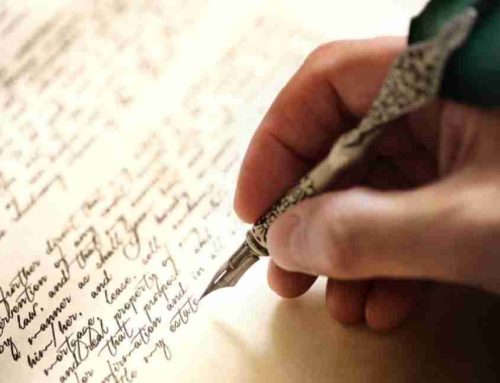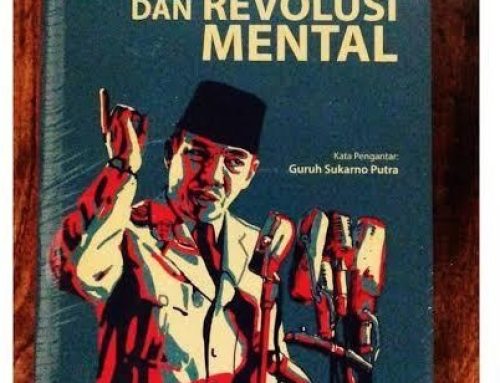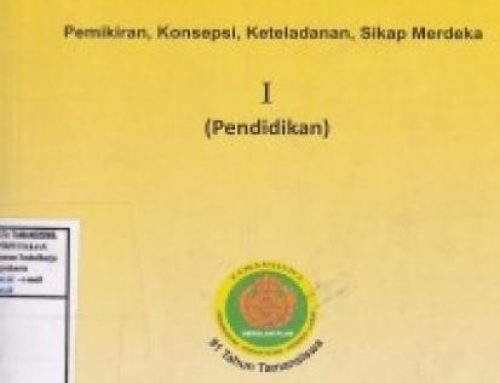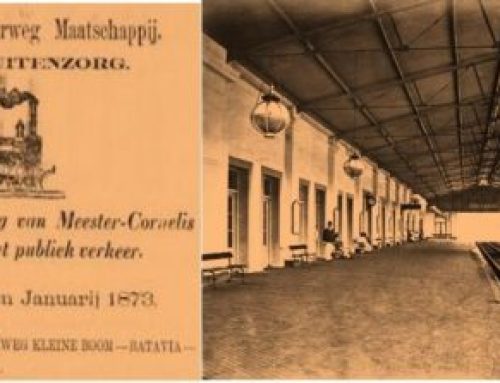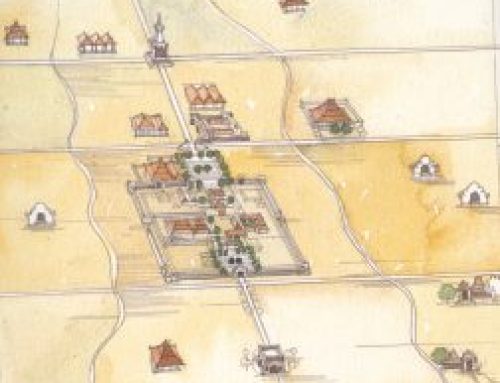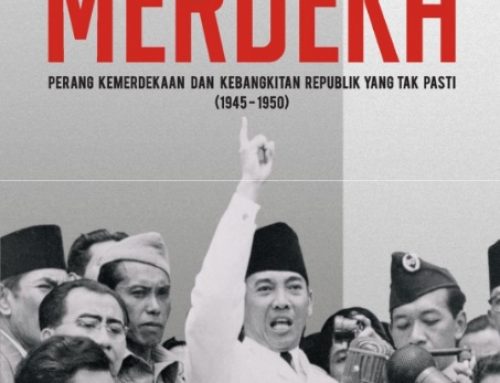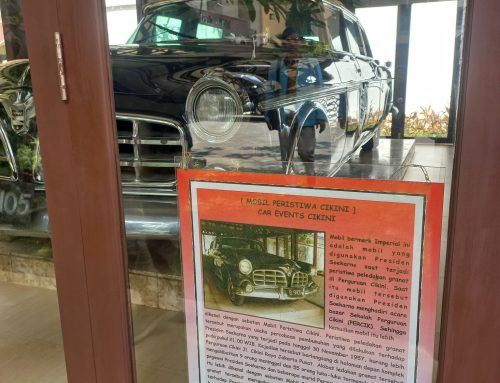Oleh: Dhimas Purnomo Adjie dan Rismayanti Khomairoh (Kedua Penulis merupakan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Jember, Jawa Timur)
*Artikel ini merupakan karya tulis peraih Juara 3 dalam “Lomba Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional” yang diselenggarakan oleh HMP Ganesha Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 21 Mei 2025.
ABSTRAK: Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 di Irian Barat merupakan peristiwa kontroversial dalam dinamika Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses integrasi wilayah yang menjadi kepentingan nasional Indonesia tidak dijalankan sesuai standar demokrasi Internasional, sehingga muncul tuduhan intimidasi yang menyebabkan legitimasi Pepera terus diperdebatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontroversial Pepera 1969 terhadap pembentukan karakter, menyoroti bagaimana proses integrasi yang dipersoalkan serta narasi demokrasi yang dianggap ilusi oleh sebagian pihak. Dengan menggunakan metode historis, penelitian ini menggunakan kekayaan sumber melalui heuristik, analisis kritis dan interpretasi ke dalam karya historiografi. Dalam penelitian ini menyajikan narasi sejarah kontroversial Pepera dari sudut pandang berbagai pihak mulai dari pemerintah nasional, aktivis Papua hingga pengamat Internasional serta menganalisis pengaruhnya untuk membangun solusi yang tepat, khususnya dalam perbaikan karakter generasi Indonesia. Keunikan dalam penelitian ini terletak pada penggabungan dua ranah kajian yang seringkali dibahas secara terpisah, yaitu sejarah integrasi politik dalam Pepera 1969 dan kajian sosial atau psikologi dalam pembentukan karakter. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya melihat Pepera sebagai peristiwa politik semata, tetapi juga menganalisis dampaknya yang mendalam dan berkelanjutan terhadap aspek psikologis dan sosial generasi Indonesia, yaitu dalam hal pembentukan karakter.
Kata Kunci: Pepera, Integrasi, Demokrasi Ilusi, Sejarah Kontroversial, Pembentukan Karakter, Papua.
ABSTRACT: The Act of Free Choice (PEPERA) in 1969 in West Irian was a controversial event in the dynamics of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The process of regional integration, which was a matter of national interest for Indonesia, was not conducted in accordance with international democratic standards, leading to allegations of intimidation and ongoing debates over the legitimacy of PEPERA. This study aims to analyze the controversial impact of the 1969 PEPERA on character development, highlighting how the disputed integration process and the notion of democracy seen by some as an illusion unfolded. Using historical methods, this research draws on a wealth of sources through heuristics, critical analysis, and interpretation to produce historiographical work. The study presents a historical narrative of the controversial PEPERA from various perspectives, including those of the national government, Papuan activists, and international observers, and analyzes its impact in order to propose appropriate solutions, particularly in improving the character development of Indonesia’s younger generation. The uniqueness of this research lies in its integration of two fields that are often discussed separately: the political history of the 1969 PEPERA and the social or psychological study of character formation. Therefore, this study not only views PEPERA as a mere political event but also analyzes its profound and lasting impacts on the psychological and social aspects of Indonesia’s generation, particularly in character building.
Keywords: PEPERA, Integration, Illusory Democracy, Controversial History, Character Development, Papua.
PENDAHULUAN
Wilayah Irian Barat atau yang lebih popular disebut Papua, dijuluki sebagai Permata di Ujung Timur karena salah satu kekayaan alamnya yang besar berupa hasil tambang. Anugerah berupa kekayaan alam yang melimpah di Papua tidak sejalan dengan tingkat konflik yang terus terjadi di wilayah tersebut. Ironi ini menjadi sorotan utama dalam memahami kompleksitas permasalahan di Papua. Sebelum menjadi wilayah yang utuh, Papua pernah mengalami sengketa status politik terkait kesatuan wilayah karena perpindahan kepemimpinan dari pemerintah kolonial Belanda kepada pemerintah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Belanda masih mempertahankan Papua sebagai wilayah koloni atau jajahannya dan menganggap wilayah Barat Pulau Papua sebagai entitas yang terpisah dari Indonesia. Sedangkan di sisi lain Republik Indonesia berupaya untuk memasukkan Papua ke dalam wilayah teritorinya karena Papua adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Proses historis integrasi wilayah Irian Barat untuk menjadi bagian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki dinamika yang kompleks, penuh tantangan dan diwarnai oleh berbagai kepentingan serta perspektif yang beragam. Permasalahan integrasi Irian Barat dibawa ke dalam meja hijau melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Bersamaan dengan perundingan untuk memperoleh kedaulatan negara Indonesia, hasil dari KMB menyatakan bahwa Belanda hanya bersepakat untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, namun status Papua masih mengambang dan akan melalui proses perundingan berikutnya. Hal tersebut memicu terjadinya ketegangan dan konflik antara Indonesia dan Belanda. Indonesia terus melakukan upaya diplomasi untuk merebut Papua, namun masih mengalami kegagalan hingga situasi memuncak ketika Presiden Soekarno menyatakan konfrontasi politik dan militer terhadap Belanda.
Pada saat itu, musuh Indonesia bukan hanya Belanda, namun juga masyarakat Papua sendiri karena munculnya nasionalisme untuk menentukan nasib sendiri. Masa pendudukan Belanda di Papua yang masih ada setelah kemerdekaan Indonesia, menyebabkan terpecahnya penduduk Papua menjadi dua kubu, yaitu kubu pro Republik dan kubu pro Papua. Kubu pro Republik merupakan kelompok yang merasa sebagai bagian dari Republik Indonesia dan memandang kedudukan Belanda sebagai kelanjutan dari kolonialisme yang harus diakhiri. Beberapa tokoh dan organisasi di Papua secara aktif memperjuangkan integrasi dengan Indonesia contohnya lahir Gerakan Tjendrawasih Revolusioner Irian Barat (GTRIB) pada tahun 1953. Anggota gerakan tersebut percaya bahwa bersatu dengan Indonesia akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Sedangkan kubu pro Papua memiliki beragam pandangan, namun umumnya tidak ingin menjadi bagian dari Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki ikatan atau harapan terhadap Belanda yang pada saat itu masih berkuasa. Beberapa penduduk juga mendambakan kemerdekaan Papua sebagai negara sendiri, terpisah dari Indonesia maupun Belanda.
Pada periode tersebut, kesadaran identitas mulai dimiliki oleh masyarakat Papua, bahkan beberapa organisasi politik lokal mulai terbentuk dan menyuarakan keinginan untuk merdeka atau mendapatkan otonomi yang lebih besar. Tentunya, aspirasi tersebut bertolak belakang dengan keinginan Indonesia untuk mengintegrasikan Papua secara penuh ditambah Belanda membentuk dewan perwakilan lokal yang bernama Nieuw Guinea Raad tahun 1961 yang memberikan dukungan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menyuarakan aspirasi politik mereka. Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakui keberadaan Nieuw Guinea Raad. Selain permasalahan internal, kepentingan kekuatan asing juga menjadi penghambat proses integrasi wilayah Papua salah satunya Amerika Serikat yang memiliki kepentingan strategi dan ekonomi di wilayah Asia Tenggara. Sikap Amerika Serikat terhadap perdamaian Papua antara Indonesia dan Belanda menjadi faktor penting dalam dinamika politik pada saat itu.
Setelah bertahun-tahun berselisih untuk mendapatkan Papua, Indonesia dan Belanda akhirnya mencapai kesepakatan melalui mediasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Perjanjian New York yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 15 Agustus 1962 (Husein, 2022). Perjanjian New York akan dijadikan sebagai landasan utama bagi pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) untuk menentukan status akhir Papua. Dalam perjanjian tersebut, Belanda setuju untuk menyerahkan pemerintahan Irian Barat kepada Badan Eksekutif sementara PBB yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) pada tanggal 1 Oktober 1962 dan selanjutnya UNTEA akan menyerahkan administrasi ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963 (Suropati, 2019). Dalam Pasal 17 dan 18 Perjanjian New York, secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia dengan bantuan dan partisipasi Utusan PBB, akan menyelenggarakan PEPERA untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Irian Barat untuk menentukan status akhir wilayah tersebut.
Sesuai dengan Perjanjian New York, tujuan utama PEPERA adalah untuk mengetahui dan mengesahkan pilihan rakyat Irian Barat mengenai status wilayah mereka, apakah ingin tetap menjadi bagian dari Indonesia atau menentukan nasib sendiri. Setelah Perjanjian New York disahkan, persiapan PEPERA mulai dilakukan. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Fernando Ortiz Sanz sebagai perwakilan untuk mengawasi pelaksanaan PEPERA. Persiapan juga dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan pembentukan Dewan Musyawarah PEPERA (DMP) yang terdiri dari 1.025 orang perwakilan yang dipilih dari berbagai wilayah di Papua dari 800.000 penduduk Papua pada saat itu (Stoffel, 2021). Proses pemilihan DMP ini menjadi salah satu poin kontroversi karena dianggap tidak sepenuhnya demokratis dan berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.
Pelaksanaan PEPERA dilakukan secara bertahap pada tahun 1969. Konsultasi dengan dewan kabupaten mengenai tata cara pelaksanaan PEPERA dimulai pada tanggal 24 Maret 1969 di Jayapura, sedangkan pemilihan DMP berlangsung hingga Bulan Juni 1969. Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura. Metode pemungutan suara yang dilakukan adalah melalui musyawarah mufakat oleh anggota DMP, bukan menggunakan sistem one man on vote seperti yang diamanatkan oleh sebagian pihak dalam interpretasi Perjanjian New York. Hasil PEPERA menunjukkan bahwa seluruh anggota DMP yang hadir secara bulat memilih untuk tetap bergabung dengan Republik Indonesia. Hasil PEPERA kemudian dibawa ke Sidang Umum PBB pada tanggal 19 November 1969 dengan ketentuan Majelis Umum PBB menerima dan mengesahkan hasil PEPERA melalui Resolusi Nomor 2504 XXIV. Meskipun hasil PEPERA telah disahkan oleh PBB, namun hingga saat ini masih menjadi sumber kontroversi dan diperdebatkan oleh berbagai pihak, terutama terkait dengan metode pemungutan suara yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi universal dan adanya tuduhan intimidasi serta kurangnya kebebasan dalam proses pemungutan suara (Anugerah, 2019).
METODE PENELITIAN
Metode penelitian adalah seperangkat prinsip, prosedur dan teknik sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data guna menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis (Sari, et.al, 2023). Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari lima tahapan utama yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi dan historiografi (Kuntowijoyo, 2013). Penelitian diawali dengan pemilihan topik terkait sejarah kontroversial tentang narasi sejarah. Dalam pemilihan topik, Kuntowijoyo menekankan pentingnya kedekatan emosional dan intelektual dengan topik yang akan diteliti. Selain itu, topik harus mengandung unsur 5W+1H. Tahapan kedua adalah proses pengumpulan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan sumber sekunder melalui penelusuran pustaka secara online seperti buku, artikel dan media massa.
Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber untuk menguji keaslian dan kredibilitas sumber-sumber yang telah dikumpulkan. Kritik sumber terbagi menjadi kritik eksternal dan kritik internal. Dilanjutkan pada tahapan keempat yaitu interpretasi atau penafsiran sumber. Tujuannya adalah untuk menemukan fakta-fakta sejarah yang ditemukan. Metode penelitian ini diakhiri dengan historiografi dengan menyajikan hasil penelitian menjadi tulisan sejarah. Historiografi berisi penyusunan fakta- fakta yang telah diinterpretasikan secara sistematis dan kronologis.
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kontroversi Narasi Sejarah PEPERA 1969 di Indonesia
Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dilatarbelakangi oleh Perjanjian New York 1962 dan pelaksanaannya harus dilakukan pada tahun 1969. PEPERA atau disebut dengan Act of Free Choice (PEPERA) merupakan sebuah penyelenggaraan pemilihan umum sebagai penentuan nasib bagi penduduk Irian Barat dalam memutuskan untuk bergabung dengan Indonesia atau berdiri sendiri sebagai sebuah negara merdeka (Marshanda, 2024). Sebelum pelaksanaan PEPERA, Pemerintah Belanda harus menyerahkan kekuasaan atas Irian Barat kepada badan pemerintah (peralihan) sementara PBB yaitu United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Jika nanti hasil dari PEPERA menyatakan bahwa masyarakat Irian memilih untuk bergabung dengan Indonesia, maka kekuasaan ini akan diberikan seutuhnya oleh UNTEA.
Sebagai bentuk realisasi dari tujuan Perjanjian New York bahwa pelaksanaan Act of Free Choice atau PEPERA selambat-lambatnya harus dilaksanakan pada tahun 1969. Berdasarkan fakta dalam lapangan, Pemerintah Indonesia berhasil menghelat PEPERA secara bertahap pada 14 Juli 1969 hingga 4 Agustus 1969. Sebagai proses integrasi antara Indonesia dengan Papua, Pemerintah Indonesia menilai berhasil dalam menjaga marwah NKRI. Mereka menganggap proses ini merupakan proses yang sangat transparansi, adil dan mengedepankan hak asasi masyarakat Papua. Masyarakat Papua telah diberikan hak secara sepenuhnya untuk menentukan status politik mereka. Dalam pelaksanaan praktik PEPERA 1969, Pemerintah Indonesia dibantu dan diawasi oleh PBB sesuai dengan isi Perjanjian New York yang diwakili oleh Dr Fernando Ortiz Sanz. Media Indonesia dalam memberitakan kinerja Ortiz Sanz memiliki makna konotasi yang negatif. Ortiz Sanz dianggap tidak melakukan apapun dalam persiapan ataupun menyusun mekanisme pelaksanaan PEPERA.
Sesuai dengan isi Perjanjian New York, Indonesia harusnya melaksanakan PEPERA dengan metode one man one vote. Ironinya, sistem pemilihan berbeda dengan fakta dalam lapangan bahwa Indonesia mengusulkan metode pemilihan baru terhadap perwakilan PBB. Pemerintah Indonesia menginginkan metode many man, one vote yang artinya banyak orang satu suara. Alasannya adalah karena sistem tersebut dinilai lebih menjunjung nilai tradisi Indonesia yang berlandaskan Pancasila dimana musyawarah mufakat menjadi tonggak penentuan kebijakan (Suryana, 2017). Perubahan sistem voting yang tidak sesuai dengan isi dari Perjanjian New York menciptakan polemik yang fatal karena hanya akan menghasilkan suara yang cacat. Pemerintah Indonesia menganggap sistem voting yang tercantum dalam perjanjian tidak sesuai dengan kondisi Indonesia dan cenderung bertentangan dengan budaya tradisional Indonesia.
Ortiz Sanz menganggap sistem musyawarah mufakat yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia telah mencederai Perjanjian New York yang berasaskan one man one vote. Implementasi sistem one man one vote yang dilakukan di Papua memiliki tantangan yang signifikan. Pemerintah Indonesia pada waktu itu mengemukakan kekhawatiran bahwa mekanisme ini sulit diterapkan secara efektif di wilayah Papua, khususnya di daerah – daerah pedalaman yang ditandai oleh kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau, infrastruktur yang terbatas serta tingkat pemahaman politik yang masih rendah di kalangan masyarakat adat. Sebagai utusan PBB yang menginginkan tidak adanya cedera dalam implementasi Perjanjian New York, Ortiz Sanz mengusulkan untuk penyesuaian dalam metode pemilihan agar nilai demokrasi tetap hadir di dalam pemilihan status wilayah Papua. Ortiz Sanz mengusulkan untuk melakukan sistem pendaftaran pemilih karena dinilai dapat menjangkau seluruh unsur masyarakat hingga ke wilayah pedalaman (Algemeen Handelsblad, Ondanks Toezeggingen Djakarta en van Oneens over West-Irian March 03, 1969).
Selain itu, sistem ini sebagai media legitimasi hasil pemungutan suara yang kemudian dapat menjadi data pembanding antara pendaftar yang hadir dan yang memilih. Sistem ini dinilai lebih valid di mata nasional yang tetap menjunjung tinggi nilai transparansi dan demokrasi (Algemeen Handelsblad, Ondanks Toezeggingen Djakarta en van Oneens over West- Irian March 03, 1969). Sayangnya, Usulan tersebut tidak diindahkan oleh Pemerintah Indonesia karena mereka tetap menolak dan bersikeras dengan metode pemilihan melalui musyawarah mufakat. Kritik perwakilan PBB yang dilayangkan kepada Pemerintah Indonesia terhadap pelaksanaan PEPERA menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan kultural lokal dengan tuntutan prosedural Internasional. Pemerintah Indonesia masih menganggap Ortiz Sanz terlalu kaku dalam merumuskan kebijakan. Keputusan tersebut tentu memicu amarah masyarakat Papua karena mereka menilai sistem musyawarah mufakat tidak memberikan hak kebebasan individu dalam memberikan suara.
Untuk menyuarakan pertentangan tersebut, masyarakat Papua menggelar aksi protes di depan kediaman Ortiz Sanz di Papua. Suara ini kemudian disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, yaitu U Thant, namun mendapatkan penolakan karena menurutnya sistem pemilihan dapat ditentukan oleh negara yang sedang melaksanakan pemungutan suara berdasarkan tradisi yang dimiliki negara tersebut (Suryana, 2017). Dengan berubahnya sistem pemilihan, maka pemerintah Indonesia segera membentuk Dewan Musyawarah PEPERA (DMP). Untuk memastikan anggota yang tergabung dalam DMP adalah anggota yang dapat mewakili suara masyarakat Papua, Ortiz Sanz mengharuskan pemerintah Indonesia agar memilih anggota yang ditunjuk langsung oleh masyarakat (Nederlands dagblad: gereformeerd gezinsblad, Vrije keuze op West-Irian Indonesië gebruikt traditionele methode March 22, 1969). Hal tersebut berbeda dengan fakta di lapangan jika anggota DMP merupakan orang pilihan ABRI dan pemerintah yang diawasi secara ketat dengan intimidasi dan ancaman pembunuhan. Segala upaya tersebut dilakukan hanya untuk menggabungkan Papua ke dalam NKRI meskipun mengaburkan prinsip demokrasi Republik Indonesia (Suryana, 2017).
Pelaksanaan PEPERA dengan sistem musyawarah mufakat untuk pertama kalinya dilakukan di Merauke pada tanggal 14 Juni 1969. Sidang DMP di Merauke berlangsung tertib dengan dihadiri oleh ketua DMP, Gubernur Irian Barat, Sudjarwo Tjondronegoro (wakil khusus pemerintah Indonesia untuk Irian Barat, Perwakilan PBB dan Mendagri (Suryana, 2017). Pada tahun 1969, Kabupaten Merauke tercatat memiliki jumlah penduduk sebesar 144.171 jiwa berdasarkan data sensus yang digunakan dalam pelaksanaan PEPERA. Untuk Kabupaten Merauke, sebanyak 175 anggota ditunjuk pemerintah Indonesia untuk menjadi anggota DMP (Suryana, 2017). Dalam keputusan sidang, Merauke menyatakan tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia, sehingga keputusan ini menjadi kemenangan pertama oleh Pemerintah Indonesia. Pelaksanaan PEPERA kembali dilakukan di kabupaten Jayawijaya pada tanggal 16 Juli 1969. Pada tahun yang sama, kabupaten Jayawijaya memiliki 165.000 jiwa berdasarkan sensus penduduk yang digunakan dalam pelaksanaan PEPERA. Dari 165.000 jiwa diwakili oleh 175 anggota DMP untuk menggunakan hak suaranya (Suryana, 2017). Mengenai detail anggota DMP di setiap wilayahnya dapat dilihat dalam tabel:
Tabel 1. Jumlah Dewan Musyawarah PEPERA di Papua Tahun 1969
| Kabupaten | Jumlah Jiwa | Jumlah | Ketua DMP Pemilih |
| Jayapura | 81.246 | 110 | Drs. Anwar Ilmar |
| Cendrawasih | 93.230 | 130 | Drs. S. Harahap |
| Manokwari | 52.290 | 75 | S. Deminaus Kawab |
| Sorong | 86.840 | 110 | D. Soebardja |
| Fakfak | 38.917 | 75 | Alex Silas Onim |
| Meroke | 141.373 | 175 | Gr. Darmowidigdo, S.E. |
| Paniai | 156.000 | 175 | S. Soerodjotanojo, S.H. |
| Jayawijaya | 165.000 | 175 | Clemens Kiriwaib |
| Jumlah | 1.025 |
Sumber: Leirissa, R. Z. (1992). Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Metode pemilihan musyawarah mufakat yang diusung oleh Pemerintah Indonesia berhasil diterapkan dalam pelaksanaan PEPERA tahun 1969. Dengan rasio representasi sekitar 1 anggota DMP untuk setiap 823 penduduk, timbul pertanyaan kontekstual mengenai sejauh mana mekanisme ini mampu merefleksikan prinsip-prinsip dasar hukum demokrasi, khususnya terkait realisasi hak kebebasan individu dalam proses penentuan nasib sendiri. Padahal secara prinsip demokrasi sebagaimana tercermin dalam instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) dan Resolusi Majelis Umum PBB yang menekankan pentingnya partisipasi langsung, bebas dan tanpa paksaan dari setiap individu dalam proses penentuan status politik suatu wilayah (Jehanu, 2021). Konsep tersebut harus bertentangan dengan sistem pemilihan dalam pelaksanaan PEPERA di Papua. Pemerintah Indonesia justru menganggap prinsip one man one vote sebagai bentuk formalitas yang tercantum dalam Perjanjian New York.
Pelaksanaan PEPERA secara resmi telah selesai dilakukan pada tanggal 4 Agustus 1969. Sesegera mungkin Pemerintah Indonesia segera merumuskan Rancangan Undang-Undang mengenai status otonom Papua untuk mempercepat proses pembangunan. Pada tanggal 16 Agustus 1969 dengan amanat Presiden Soeharto untuk segera dibicarakan dan disahkan sebagai Undang-Undang. Pada tanggal 10 September 1969, rancangan tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 1969 (BPK, 1969). Integrasi Papua ke dalam NKRI yang berhasil dilakukan bukan berarti tidak memiliki kecacatan hukum. Banyak suara yang masih bersifat gugatan hasil dari PEPERA baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam sidang umum PBB yang diselenggarakan pada tanggal 19 November 1969, setidaknya ada dua perwakilan duta luar negeri, yaitu Duta Besar Ghana dengan Duta Besar Gabon, yang merasa bingung dan meragukan dengan laporan Ortiz Sanz mengenai suara yang diperoleh dalam perhelatan PEPERA (Yambeyapdi, 2018).
Sidang umum tersebut juga telah mengesahkan hasil dari PEPERA untuk anggota PBB dengan jumlah suara 84 anggota PBB setuju dan 30 negara abstain. Duta Besar Zambia merupakan salah satu dari 30 suara abstain yang menyatakan kegagalan paham dalam persetujuan Sekretaris Jenderal PBB, mengenai sistem pemilihan musyawarah mufakat yang diusulkan Pemerintah Indonesia yang jelas-jelas tidak disepakati dalam Perjanjian New York. Suara abstain lainnya juga datang dari Duta Besar Afrika yang menganggap proses pemungutan suara sebagai cacat hukum dan kejanggalan ini semakin memperlemah posisi PBB di Afrika dalam menghadapi minoritas kulit putih di Afrika Selatan. (bandingkan kondisi orang kulit putih yang superior akan papua yang dihuni oleh orang berkulit hitam).
Menurut Amir Mahmud sebagai perwakilan Indonesia dalam melaksanakan tugas PEPERA, wilayah Papua akan menjadi bagian dari Indonesia dan akan tetap demikian (Amirmahmud, 1987). Hal tersebut menjadi bukti eksplisit bahwa pemerintah Indonesia menganggap Papua harus menjadi wilayah kekuasaan Indonesia bukan milik asing, sehingga dalam praktik PEPERA semua cara yang digunakan sudah sesuai dengan takaran hukum Internasional (Amirmahmud, 1987). Sebelum dilaksanakan PEPERA 1969, segenap perwakilan indonesia termasuk Amirmahmud melakukan peninjauan daerah-daerah Papua. Hasil yang didapatkan cukup mengejutkan karena penduduk dari wilayah pelosok masih buta dengan atmosfer perpolitikan Indonesia. Mereka tidak tahu menahu kondisi daerahnya yang saat itu masih mengalami krisis identitas kepemilikan antara Indonesia dengan Belanda. Ironinya, perwakilan Indonesia tersebut tidak memberikan edukasi terhadap mereka yang belum sadar akan perpolitikan saat itu justru menggunakannya sebagai salah satu kesempatan untuk memperoleh suara. Mereka mendikte kepala daerah ketika menjadi perwakilan PEPERA nanti cukup mengatakan “Soeharto”, “Merah Putih”, atau “Republik Indonesia”.
Selain pelaksanaan PEPERA dan legitimasi yang ada di dalam prosesnya, kontroversi terkait penyebutan nama “Irian” pada saat pelaksanaan PEPERA berlangsung dikaitkan dengan konteks sosial dan politik pada saat itu. Menurut pemberitaan media massa, asal usul penyebutan nama Irian pertama kali dicetuskan oleh Frans Kaisiepo, yaitu seorang tokoh Papua yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Terdapat beberapa interpretasi mengenai asal-usul dan makna penggunaan nama Irian, namun yang paling populer diberitakan adalah Irian berarti “Ikut Republik Indonesia Anti Belanda”. Makna dari akronim tersebut adalah menggaungkan semangat anti Belanda dan dukungan untuk bergabung dengan Indonesia. Meskipun asal usul nama Irian diajukan oleh tokoh Papua yang pro-integrasi, namun pada kenyataannya nama Irian tidak diterima oleh semua orang Papua. Bagi sebagian kelompok yang memiliki aspirasi kemerdekaan, nama Irian dianggap sebagai nama pemberian dari luar yang melambangkan integrasi pemaksaan.
B. Pengaruh Kontroversi Narasi Sejarah PEPERA Terhadap Pembentukan Karakter
Definisi dari karakter adalah gabungan dari pemahaman, perhatian dan tindakan mengenai nilai-nilai etika yang mendasar dan membimbing perilaku individu (Lickona, 2012). Proses pembentukan karakter melalui tiga tahapan yaitu tahap pengetahuan, pelaksanaan dan pembiasaan (Aprianto, 2023). Karakter berbeda dengan kepribadian dan moralitas, meskipun ketiganya saling terkait (Atfal, et.al, 2023). Nilai-nilai, keyakinan, sikap dan kebiasaan memainkan peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Pembentukan karakter bangsa adalah proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya sejarah bangsa itu sendiri. Di Indonesia, kontroversi mengenai narasi sejarah PEPERA, terutama terkait keadilan dan legitimasi prosesnya, dapat memberikan pengaruh yang kompleks terhadap pembentukan karakter baik secara individu maupun kolektif.
Dalam narasi sejarah PEPERA yang masih menjadi kontroversi, dapat memicu suatu individu untuk mencari dan menyebarkan berbagai sumber informasi dan interpretasi sejarah yang anakronis. Meskipun mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis dan memunculkan perspektif bahwa sejarah dapat ditafsirkan dari berbagai sudut pandang. Jika tidak terkontrol dan terkendali, kontroversi tersebut dapat memicu terjadinya polarisasi dan konflik. Selain itu, kontroversi mengenai narasi sejarah PEPERA juga dapat memengaruhi nilai-nilai, keyakinan dan sikap individu serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan terhadap sejarah, kebangsaan dan identitas. Dalam hal ini, nilai-nilai karakter yang mendapatkan pengaruh dari adanya pembelokan narasi sejarah PEPERA di Indonesia adalah nasionalisme, kesadaran kritis dan sikap demokratis.
1. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan suatu pemahaman yang menjunjung tinggi rasa kebangsaan atau nasionalitas sebagai hal yang paling utama (Kusumawardani, 2015). Pembelokan terkait narasi sejarah PEPERA 1969 di Papua dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap karakter nasionalisme di Indonesia, terutama dalam konteks hubungan Pemerintah Pusat dan masyarakat. Jika narasi sejarah PEPERA yang diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia berbeda secara fundamental dengan narasi resmi pemerintah, maka dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat dan institusi negara. Selain itu, nasionalisme yang dipaksakan melalui narasi sejarah yang tidak sesuai dengan pengalaman yang diketahui atau didengar akan memunculkan perspektif bahwa nasionalisme Indonesia dipandang sebagai sesuatu yang tidak inklusif serta tidak menghargai sejarah dan identitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Papua.
Dampak lain yang ditimbulkan adalah potensi perpecahan nasional yang semakin tinggi akibat ketidakpercayaan dan rasa ketidakadilan di Papua yang menyebar dan mempengaruhi solidaritas nasional secara keseluruhan. Selain itu, lemahnya persatuan dan kesatuan menyebabkan salah satu pilar nasionalisme dapat terkikis. Hal tersebut menjadi ancaman yang serius bagi keberlangsungan nasionalisme. Tanpa adanya rasa solidaritas yang kuat sebagai landasan persatuan, pilar-pilar nasionalisme lainnya seperti rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keinginan untuk mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa juga akan ikut melemah.
2. Kesadaran Kritis
Kesadaran kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif dan mendalam serta mampu mengidentifikasi sesuatu yang mendasari informasi tersebut (Sulaiman, et.al, 2022). Perbedaan narasi sejarah PEPERA antara pemerintah dengan pihak lain memberikan dampak terhadap kesadaran kritis. Adanya dua narasi yang saling bertentangan menciptakan perpecahan dalam pemahaman sejarah bangsa. Contoh kejanggalan konkret peristiwa PEPERA di lapangan yang berdampak pada kesadaran kritis generasi Indonesia adalah, yang pertama, terbatasnya opsi-opsi yang tersedia dalam PEPERA seperti pilihan tetap menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Sosialisasi diberikan secara terbatas khususnya kepada penduduk Papua dan umumnya masyarakat Indonesia. Banyak yang tidak dipahami sepenuhnya dari pilihan yang akan ‘diwakilkan’ oleh para tokoh adat terpilih. Bahkan, salah satu wartawan menyampaikan bahwa pada dasarnya, orang Papua menilai orang-orang non-Papua di tanah Papua pro-republik, namun ketika PEPERA datang semuanya takut untuk bersuara (Pamungkas, 2015).
Kedua, pemilihan para tokoh adat untuk menjadi DMP seringkali tidak transparan dan diduga adanya intervensi atau penunjukan oleh pihak tertentu. Fenomena tersebut akan menciptakan adanya kepatuhan pasif terhadap keputusan yang dibuat oleh pihak yang berkuasa. Ketiga, minimnya ruang diskusi atau debat publik yang bebas dan terbuka mengenai masa depan Papua. Masyarakat tidak memiliki kesempatan yang setara untuk bertukar pikiran dan membentuk opini secara mandiri. Terakhir, narasi yang didorong oleh pemerintah pusat sangat dominan, sementara perspektif dan aspirasi sebagian masyarakat yang berbeda tidak mendapatkan ruang yang sama untuk berpendapat. Hal tersebut berdampak pada kesadaran kritis karena ketika informasi terbatas dan narasi tunggal mendominasi, maka kemampuan masyarakat untuk menganalisis situasi secara kritis menjadi terhambat. Dengan demikian, kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa PEPERA di lapangan tidak hanya berdampak pada legitimasi proses itu sendiri, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi pembentukan karakter kesadaran kritis.
3. Demokratis
Demokratis merupakan suatu kondisi dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh rakyat secara langsung atau melalui sistem perwakilan yang dipilih secara bebas dan adil (Hidayati, 2014). Demokrasi memiliki beberapa ciri utama yaitu kedaulatan rakyat, pemilihan umum yang bebas dan adil, transparansi dan partisipasi publik. Aspek tersebut bertentangan dengan peristiwa PEPERA di lapangan karena menggunakan sistem musyawarah terbatas bukan one man one vote. Sistem musyawarah mufakat yang digunakan melibatkan beberapa tokoh masyarakat yang dipilih. Fenomena dalam sejarah tersebut memberikan pengaruh pada perkembangan karakter khususnya nilai-nilai demokrasi.
Masyarakat Papua yang merasa tidak memiliki kesempatan untuk menyuarakan pilihan mereka secara langsung akan merasa terasingkan dari proses integrasi dan tidak memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil PEPERA maupun negara Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, proses PEPERA juga dinilai memiliki keterbatasan akses dan pengawasan Internasional karena dalam pelaksanaannya dilakukan oleh perwakilan PBB, namun di lapangan diketahui jika akses perwakilan PBB terbatas dan pengawasan yang independen dinilai kurang memadai oleh sebagian pihak terkait. Hal tersebut menginterpretasikan bahwa kurangnya transparansi dalam pelaksanaan PEPERA. Dampak fenomena tersebut terhadap karakter demokratis adalah rakyat tidak memiliki kesempatan yang setara untuk menentukan nasibnya melalui mekanisme yang adil dan bebas.
Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah pilar utama demokrasi, sehingga ketika tidak dijalankan maka akan merusak kepercayaan terhadap proses pemilihan umum. Tidak hanya itu, kejanggalan dalam proses PEPERA yang sudah tertulis dalam narasi sejarah Indonesia akan menghambat terbentuknya budaya demokrasi yang sehat serta akan mewariskan pemahaman yang cacat tentang demokrasi. Dalam hal ini, generasi bangsa menjadi korban narasi sejarah dan akan melakukan hal turun temurun pada generasi selanjutnya.
C. Solusi untuk Memperbaiki Pembentukan Karakter
Pendidikan merupakan landasan utama dalam membangun karakter seseorang. Secara sederhana, pendidikan adalah suatu proses yang secara sadar dan terencana dirancang untuk mengembangkan potensi anak didik secara utuh baik dari aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Pembentukan karakter merupakan bagian integral dari pengembangan afektif yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur dan membentuk kepribadian yang baik. Proses penyaluran pendidikan tidak terlepas dari institusi atau lembaga pendidikan. Menurut jenisnya, pendidikan pada umumnya terdiri dari pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal (Hanifah, et.al, 2023). Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, umumnya terdiri dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi dan biasanya diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal sebagai pelengkap atau pengganti pendidikan formal. Tidak hanya pendidikan formal dan nonformal, pendidikan informal juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter yang prosesnya terjadi di lingkungan keluarga, masyarakat dan pengalaman sehari-hari.
Di Indonesia, penyelenggaraan pendidikan formal memiliki struktur vertikal dan diatur oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan yang telah dibagi masing-masing jenjangnya. Sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter dan kualitas generasi suatu bangsa, pendidikan formal dituntut untuk mampu menciptakan ekosistem pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik semata, namun juga membangun kapasitas siswa dalam berpikir reflektif, analitis dan rasional. Dalam institusi pendidikan formal, pembentukan karakter dipengaruhi oleh berbagai komponen utama yang saling berinteraksi. Center point yang paling berpengaruh adalah pendidik (guru dan tenaga kependidikan). Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai teladan dan pembimbing karakter bagi siswa. Seorang guru harus mempunyai keterampilan yang baik dalam menyampaikan materi kepada anak didiknya. Di samping itu, kualitas kurikulum dan bahan ajar juga harus diperhatikan. Sebaiknya, kurikulum harus mengedepankan dua komponen, yaitu pengetahuan akademik dan nilai-nilai karakter.
Tidak hanya pendidikan formal, pendidikan nonformal juga berpengaruh dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Di era modern saat ini, pendidikan nonformal hampir sama dengan pendidikan formal, baik prosedur maupun penyelenggaraannya. Hanya saja, pendidikan nonformal lebih sedikit memberikan kebebasan karena tidak terikat oleh regulasi pemerintah yang diatur secara vertikal, misalnya lembaga kursus, balai pengembangan, komunitas hingga pesantren (Rosyad, 2017). Pendidikan nonformal memberikan ruang fleksibel bagi seseorang yang mengasah keterampilan atau pengetahuan spesifik diluar kurikulum formal, sekaligus memperkuat nilai-nilai karakter yang berkaitan dengan pencarian jati dirinya seperti kesadaran kritis dan kebebasan untuk memilih hal-hal yang menjadi tujuan atau kesukaannya. Dalam hal ini, pengaruh lingkungan fisik dan sosial sangat berpengaruh dalam membentuk karakter (Ritonga, 2022).
Selanjutnya ada pendidikan informal yang umumnya berlangsung secara alami di lingkungan keluarga atau masyarakat. Pendidikan informal terjadi melalui interaksi sosial, pengalaman hidup dan observasi di lingkungan sekitar. Pendidikan ini tidak memiliki struktur maupun jenjang yang formal, namun justru menjadi pondasi pertama dalam pembentukan nilai, norma dan karakter individu sejak usia dini (Rosyad, 2017). Pendidikan informal berlangsung melalui interaksi sehari-hari. Anak-anak dapat belajar tentang budaya, etika, kebiasaan dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan terdekatnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, karena sejak timbulnya peradaban manusia sampai sekarang keluarga selalu mempengaruhi pertumbuhan budi pekerti tiap-tiap manusia (Firmansyah, 2019). Dalam hal tanggung jawab untuk membentuk karakter seorang anak, sepatutnya tidak hanya ditanggung oleh institusi pendidikan formal saja. Melainkan juga berakar kuat dalam lingkungan keluarga. Memang tidak dapat dipungkiri jika sebagian besar waktu anak dihabiskan dalam lingkungan sekolah, namun pemantauan orang tua juga tidak dapat dilepaskan begitu saja. Ketiga jenis institusi pendidikan di atas meskipun berbeda dalam struktur dan pelaksanaannya, namun memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses pembentukan karakter generasi banga. Dalam hal ini, generasi bangsa Indonesia adalah para pelajar dan anak-anak. Tujuan yang dimiliki juga sama, yaitu membentuk karakter generasi bangsa yang kritis, cerdas dan analitis.
Dari ketiga jenis tersebut, pendidikan formal menjadi pemegang kunci utama dalam pembentukan karakter generasi bangsa. Dengan sistem yang terstruktur, jangkauan yang luas dan keberadaan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional, menjadikan pendidikan formal sebagai kunci utama dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Guru menjadi aktor utama dalam mengarahkan dan membimbing siswa melalui media pembelajaran yang aktif dan kreatif. Namun definisi tersebut bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya. Kenyataan dalam lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara idealisme tersebut dengan implementasi pembelajaran yang diterapkan. Salah satu persoalan di dunia pendidikan adalah sistem yang satu arah mengharuskan guru menjadi center para siswa tanpa adanya ruang diskusi. Sistem ini menjadikan guru sebagai sumber pengetahuan satu-satunya dan siswa sebagai penerima pasif. Guru harus memiliki sistem pembelajaran yang mampu mengasah jiwa kritis dan analitis siswa terlebih dalam memaknai sebuah narasi sejarah. Sayangnya, banyak guru yang tidak memberikan bahan bakar untuk siswa berlatih kritis dan analitis melalui pembelajaran sejarah dengan sumber yang bervariatif, justru guru hanya berpaku pada satu sumber yaitu narasi sejarah terbitan pemerintah. Padahal sesuai prinsipnya, sejarah bukan hanya menceritakan benar atau salahnya saja, namun lebih kompleks dari pada itu dalam memaknai peristiwa.
Fenomena tersebut dapat diamati dalam konteks narasi sejarah tentang Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA). Proses peristiwa yang terlibat dalam kemelut kepentingan berbagai pihak menimbulkan proses yang kontroversial kemudian membuahkan narasi sejarah yang beragam di tengah masyarakat. Setidaknya ada dua versi yang berkembang di tengah masyarakat. Pertama, Narasi versi pemerintah, cerita yang menggambarkan superioritas peran pemerintah yang menjadi pahlawan di tengah kemelut krisis identitas Papua. Narasi ini cenderung tersebar di kalangan publik dan lingkungan pendidikan formal. Narasi versi Intelektual, cerita yang merefleksikan pada kejadian di tempat yang dikumpulkan hingga menjadi runtutan cerita yang logis dan fakta. Narasi ini hanya berada di lingkup kecil yang peduli akan nasib narasi sejarah. Ironinya, pemahaman guru di sekolah masih terpaku pada narasi resmi milik pemerintah dan narasi inilah yang diajarkan pada siswa di sekolah tanpa memberikan ruang analisis terhadap berbagai sudut pandang sejarah, sehingga menimbulkan kekhawatiran di masa depan. Seharusnya, guru memberikan ruang pembelajaran yang interaktif dan mendorong siswa untuk aktif bertanya, berdiskusi dan menganalisis informasi dari berbagai sumber, sehingga dapat membangun pemahaman mereka sendiri tentang sejarah.
Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh framing media yang tidak mendetail dan kontekstual dalam memberitakan aksi yang merupakan bagian dari dampak PEPERA. Hal tersebut beresiko menghasilkan pola pikir yang sempit dan dapat mengikis cara berfikir rasional dan analitis untuk kalangan generasi muda. Dalam jangka panjang, hal tersebut berpotensi memicu sikap rasisme dan intoleransi terhadap sesama anak bangsa. Pendidikan yang hanya menekankan penerimaan informasi tanpa pemahaman kritis dan reflektif bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional yang mengedepankan pengembangan individu yang berpikir terbuka, berkepribadian dan menghargai keberagaman. Pengaruh sistem pembelajaran sekolah yang masih menganut sistem satu pandang tanpa mengajak siswa untuk melihat dari sudut pandang lain akan berpengaruh pada kualitas siswa yang dapat mengaburkan cita-cita mulia Indonesia, yaitu “Indonesia emas 2045”.
Untuk menyelesaikan permasalahan terkait potensi dampak negatif pembelokan narasi sejarah PEPERA terhadap pembentukan narasi bangsa, maka perlu mengintegrasikan solusi-solusi yang telah dirancang. Sudah saatnya guru mulai merambah ke buku bacaan yang disusun oleh kaum intelektual, seperti dosen, sejarawan, peneliti dan budayawan, untuk menjadikan bahan ajar bagi siswa. Dalam misi menciptakan siswa yang mampu berpikir kritis dan analitis, seorang guru harus mampu menyediakan bahan bakar yang menjadi pijakan mereka dalam menganalisis narasi sejarah dari dua sudut pandang yang berbeda. Tidak dapat dipungkiri, pembelajaran sejarah pada buku paket atau modul pembelajaran milik pemerintah masih bersifat subjektif yang mengabaikan beberapa poin penting pada peristiwa yang terjadi sebenarnya. Padahal, pengayaan materi pembelajaran dapat menggunakan sumber kredibel termasuk dokumen primer, catatan saksi sejarah dan hasil penelitian yang terpercaya tentang PEPERA.
Penggunaan modul tunggal sebagai bahan ajar hanya untuk mendoktrin siswa agar terus berada dibawah koridor pemerintah dan penyingkatan narasi untuk keperluan pembatas buku ajar di sekolah. Dalam konteks peristiwa PEPERA, buku ajar sekolah versi pemerintah tentunya akan didominasi oleh peran pemerintah dalam merebut kembali Papua. Narasi dibuat seakan-akan nilai-nilai demokrasi berhasil diterapkan tanpa sedikit perlawanan. Dalam versi pemerintah, pemberontakan yang terjadi dan masih terjadi hingga saat ini, seperti pemberontakan Biak dan OPM, bukan dari permasalahan kegagalan demokrasi dalam perhelatan PEPERA. Faktanya, masyarakat Papua merasa kecewa akan sistem pemilihan yang berubah, pemaksaan oleh pemerintah dan intimidasi yang berkepanjangan. Ketidaklengkapan narasi sejarah ini sangat berpotensi terjadi pembelokan sejarah. Framing sejarah yang hanya menggunakan satu sudut pandang tanpa adanya penambahan sudut pandang lain hanya menutup kemampuan kritis dan analisis siswa yang pada dasarnya sudah menjadi kemampuan alami. Maka dari itu, sudah waktunya guru untuk tidak lagi hanya berpaku pada pembelajaran sejarah milik pemerintah, dan mulai menggunakan modul lain sebagai parameter untuk mendukung terciptanya pembentukan karakter yang kritis dan analitis sesuai dengan cita cita Indonesia Emas 2045.
Kemelut guru dalam pendidikan formal menjadi sorotan massif bagi masyarakat karena keberadaannya menjadi kunci utama dalam mencetak karakter generasi penerus bangsa. Temuan sekaligus fenomena yang sering dijumpai pada sekolah-sekolah adalah ketidaksesuaian antara latar belakang keilmuan guru dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sebagai contohnya guru yang berlatar belakang pendidikan seni budaya harus diposisikan untuk mengajar mata pelajaran sejarah. Ketidaksesuaian ini menjadi bentuk krusial yang dapat melukai sistem pendidikan sejarah. Sejarah sebagai sebuah disiplin ilmu memerlukan kemampuan analisis sumber, penalaran kronologis serta keterampilan dalam membangun argumentasi berbasis fakta sejarah yang valid, sehingga sulit rasanya jika guru seni budaya harus mengajar sejarah. Kondisi ini memperparah tantangan dalam pendidikan sejarah, terutama dalam mengajarkan materi- materi kompleks dan sensitif seperti PEPERA di Papua tahun 1969. Sebagai peristiwa historis yang erat kaitannya dengan hukum internasional dan hak asasi manusia, membutuhkan pemahaman mendalam dan analisis kritis agar narasi yang disampaikan kepada peserta didik tetap objektif, berimbang dan kontekstual. Guru yang tidak memiliki dasar keilmuan sejarah beresiko untuk menyederhanakan dan bahkan memanipulasi yang berdampak pada pembelokan narasi peristiwa tersebut. Ketidakmampuan dalam mengelola keragaman sumber dan perspektif sejarah akan mencederai tujuan pendidikan sejarah yang sesungguhnya, yaitu membentuk generasi yang memahami perjalanan bangsa secara komprehensif dan mampu berpikir kritis.
Jika kondisi ketidaksesuaian rumpun ilmu ini terus dibiarkan, implikasinya tidak hanya pada penurunan kualitas pembelajaran, tetapi juga akan menciptakan cacat pada sistem pendidikan yang valid dan otentik. Potensi terjadinya pembelokan narasi sejarah dalam ruang kelas akan semakin besar, yang pada akhirnya memberikan jarak yang semakin jauh pada generasi bangsa yang memahami perjalanan sejarah sebagai identitas nasional. Kebijakan strategis untuk pendidikan yang komprehensif dan modern dituangkan dalam salah satu program, yaitu Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). Program ini dirancang untuk meningkatkan profesionalitas dalam penguasaan kegiatan belajar mengajar mulai dari melaksanakan, merancang dan menghasilkan pembelajaran yang berkualitas (Hanun, 2021). Peluncuran program PPG merupakan cara pemerintah dalam upaya mempersiapkan guru profesional yang unggul. Tujuannya agar guru dapat menguasai seluruh kompetensi pendidikan yang selaras dengan standar nasional pendidikan. Tanda seorang guru atau mahasiswa sudah sesuai dengan standar guru nasional adalah dengan memiliki sertifikat pendidik nasional.
Secara ideal, PPG dirancang untuk membekali calon guru dengan kompetensi profesional, sosial dan kepribadian yang utuh melalui elaborasi teori dan praktik yang seimbang. Namun, dalam implementasi di lapangan, terdapat sejumlah ketidaksesuaian yang menghambat tercapainya tujuan ideal tersebut. Salah satu tantangan yang paling menonjol adalah variasi sistem pelajaran yang diterapkan di berbagai kampus penyelenggara PPG. Ketidak serentakan dalam pendekatan pembelajaran dan penilaian antar institusi perguruan tinggi menyebabkan output peserta PPG yang tidak seragam dalam orientasi dan kesiapan mengajar. Variasi ini berdampak pada ketidakpastian arah dan gaya mengajar para lulusan PPG ketika mereka kembali ke lingkungan sekolah, sehingga tidak seluruhnya sesuai dengan kebutuhan kontekstual peserta didik di masing-masing wilayah. Selain itu, dalam pelaksanaan PPG, terdapat kecenderungan penekanan yang lebih besar pada pembelajaran teoritis di ruang kelas dibandingkan dengan praktik langsung di sekolah. Para peserta, baik mahasiswa maupun guru dalam jabatan lebih banyak terlibat dalam diskusi, studi literatur dan penyelesaian akademik dibanding memperoleh pengalaman dalam mengelola pembelajaran di kelas nyata. Hal tersebut menyebabkan keterbatasan pemahaman terhadap dinamika interaksi peserta didik, manajemen kelas dan adaptasi terhadap karakteristik lingkungan belajar yang beragam. Beban tugas yang berlebihan juga menjadi faktor yang membatasi efektivitas program. Fenomena ini dapat mengurangi waktu dan energi peserta PPG untuk mengamati, memahami dan merespons situasi nyata di sekolah, sehingga sulit untuk menentukan gaya mengajar ketika berada di lapangan secara langsung.
KESIMPULAN
Pengaruh kontroversial PEPERA 1969 terhadap pembentukan karakter generasi muda bangsa menyiratkan kesimpulan bahwa pelaksanaan PEPERA seharusnya menjadi wujud integrasi demokratis dengan Indonesia. Berkaca dari sejarah di masa lampau, dapat menjadi pembelajaran penting di masa depan. Kontroversi PEPERA yang beredar pada kalangan akademisi masih menganut pemberitaan pemerintah bahwa PEPERA sebagai tindakan sah dan final yang menunjukkan keinginan rakyat Papua untuk berintegrasi dengan Indonesia. Pada kenyataannya, pelaksanaan PEPERA menuai banyak kontroversi dan kritik. Banyak pihak, terutama aktivis Papua dan pengamat internasional, menilai bahwa prosesnya tidak demokratis dan intimidasi. Mereka berpendapat bahwa seharusnya digunakan prinsip “satu orang satu suara” (one man one vote) sesuai dengan Perjanjian New York. Kontroversi tersebut akan berdampak pada pembentukan karakter generasi bangsa Indonesia khususnya penyusutan pada semangat nasionalis, kesadaran kritis dan kebebasan demokrasi. Solusi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan mengembalikan karakter kepada yang baik adalah melalui institusi pendidikan khususnya pendidikan formal. Peran guru menjadi titik utama karena tidak hanya sebagai penyalur ilmu, namun juga sebagai pembimbing dan mengajarkan nilai-nilai karakter kepada siswanya. Pendidikan karakter memegang peranan krusial sebagai strategi utama dalam memulihkan jati diri bangsa dan mendukung terbentuknya masyarakat Indonesia yang lebih baik di masa depan. Berbagai jenis lembaga pendidikan seperti pendidikan formal, nonformal dan informal memiliki posisi saling melengkapi dan berkontribusi dalam proses pembelajaran serta pembentukan karakter seseorang. Pendidikan formal memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang terstruktur, pendidikan nonformal menawarkan pengembangan diri, sedangkan pendidikan informal membentuk karakter dan pemahaman melalui pengalaman sehari-hari.
Sumber Referensi
Buku
Amirmachmud. (1987). H. Amirmachmud Prajurit Pejuang: Otobiografi.
Jakarta: Panitia Penerbitan Otobiografi Bapak H. Amirmachmud.
Kuntowijoyo. (2013). Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Leirissa, R. Z. (1992). Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
Lickona, T. (2012). Mendidik untuk Membentuk Karakter: Bagaimana Sekolah Dapat Memberikan Pendidikan Tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab. Jakarta: Bumi Aksara.
Sari, A., Dahlan, D., Tuhumury, R. A., Prayitno, Y., Willem H, S., Supiyanto, S., & Werdhani, A. S. (2023). Dasar-dasar Metodologi Penelitian. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.
Artikel
Anugerah, Boy. (2019). Papua: Mengurai Konflik dan Merumuskan Solusi. Jurnal Lemhannas RI, 7(4), 56. https://doi.org/10.55960/jlri.v7i4.111
Aprianto, R., & Kumalasari, D. (2023). Pengaruh Tokoh Pahlawan Nasional Dalam Pembelajaran Sejarah Terhadap Pembentukan Pendidikan Karakter Anak. Journal of Social Science Education, 4(2), 131-144. https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v4i2.7716
Atfal, M., Yuniar, A. C, Rantina, M., & Santoso, G. (2023). Proses Pembentukan Karakter Seseorang Berdasarkan Lingkungan Kehidupan. Jurnal Pendidikan Transformatif, 2(2), 40-46. https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i2.193
Firmansyah, Wira. (2019). Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak di Era Globalisasi. Jurnal Primary Education Silampari, 1(1), 1-6. https://doi.org/10.31540/pejs.v1i1.305
Hanifah, N., & Khairunnisa, A. (2023). Membangun Karakter Generasi Muda Melalui Pendidikan Informal, Formal, dan Nonformal. Jurnal Nusantara Hasana, 3(3), 19-25.
Hanun, Farida. (2021). Implementasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam di LPTK UIN Serang Banten. Jurnal Edukasi, 19(3), 268-285. https://doi.org/10.32729/edukasi.v19i3.1158
Harahap, D. U, Henry, Susanto & Marzius, Insani. (2022). Pentingnya Irian Barat Bagi Indonesia. Jurnal of Social Science Education, 3(2). 150-160. http://dx.doi.org/10.23960/JIPS/v3i2.152-160
Hidayati, N. (2014). Dinasti politik dan Demokrasi Indonesia. Jurnal Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial, 10(1), 18-21. https://doi.org/10.32497/orbith.v10i1.357
Husein, H & Siti H, C. (2022). Konflik Indonesia-Belanda: Upaya Mengembalikan Irian Jaya ke dalam Pangkuan Ibu Pertiwi. Prosiding WIKSA (Pendidikan Sejarah Universitas Indraprasta PGRI), 1(1), 207. https://proceeding.unindra.ac.id/index.php/wiksa
Jehanu, Velrianus B & Adrianus A.V Ramon. (2021). Penetapan Status Teroris Kelompok Bersenjata di Papua: Upaya Mencari Penyelesaian Komprehensif Demi Menjaga Persatuan Indonesia. Jurnal Pembumian Pancasila, 1(1). 65-81. https://doi.org/10.63758/jpp.v1i1.19
Korwa, Rycho. (2013). Proses Integrasi Irian Barat ke dalam NKRI. Jurnal Politico, 2(1), 1-9.
Kusumawardhani & Faturochman. (2015). Nasionalisme. Jurnal Buletin Psikologi, 12(2), 61-72. https://doi.org/10.22146/bpsi.7469
Marshanda, W. (2024). Diplomasi, Konflik, Dan Kemerdekaan: Pembebasan Irian Barat (1949-1962). Pubmedia Ilmu Sosial dan Humaniora, 1(4), 1-11. https://doi.org/10.47134/pssh.vli4.134
Pamungkas, Cahyo. (2015). Sejarah Lisan Integrasi Papua ke Indonesia: Pengalaman Orang Kaimana Pada Masa Trikora dan Pepera. Jurnal Studi Sejarah, 25(1), 104. https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3423
Ritonga, Tamin. (2022). Pentingnya Pendidikan Karakter Bagi Generasi Muda. Jurnal Pengabdian Masyarakat Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, 1(1), 1-6. http://dx.doi.org/10.37081/adam.v1i1.303
Rosyad, RA (2017). Kualifikasi Pemimpin Lembaga Pendidikan Formal, Lembaga Pendidikan Islam non Formal dan Informal. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr, 6(1), 107-123. http://dx.doi.org/10.24090/jimrf.v6i1.2748
Stoffel, Mukti. (2021). Penegakan Hak Asasi Manusia Terkait New York Agreement 1962 Dalam Hal Penentuan Pendapat Rakyat Papua. Jurnal Negara dan Keadilan, 10(1), 47. https://doi.org/10.33474/hukum.v10i1.4625
Sulaiman, A., Mashuri, MF, Sungkono, SLL, Zahrah, A., & Royhana, SF (2022). Mengukur kesadaran kritis: Konstruksi Skala kesadaran sosial-politik bagi masyarakat Indonesia. Jurnal Pengetahuan, 10(2), 93-98. https://doi.org/10.22219/cognicia.v10i2.20159
Suropati, U. (2019). Solusi Komprehensif Menuju Papua Baru: Penyelesaian Konflik Papua Secara Damai, Adil dan Bermartabat. Jurnal Lemhannas RI, 7(1), 77. https://doi.org/10.55960/jlri.v7i1.52
Suryana, Andri Yunas, Suwirta & Moch. Eryk Kamsori. (2017). Peran Amir Machmud dalam Pelaksanaan PEPERA 1969. Jurnal Factum, 26(2), 167-179. https://doi.org/10.17509/factum.v6i2.9976
Yambeyapdi, Ester. (2018). Papua: Sejarah Integrasi yang Diingat dan Ingatan Kolektif. Jurnal Indonesian Historical Studies, 2(2), 89-95. https://doi.org/10.14710/ihis.v2i2.3749
Koran
“Ondanks Toezeggingen Djakarta en van Oneens over West-Irian” dalam Algemeen Handelsblad, 22 Maret 1969. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=KBNRC01:000035217:mpeg21: p007
“Vrije keuze op West-Irian Indonesië gebruikt traditionele methode” dalam Nederlands dagblad: gereformeerd gezinsblad, 22 Maret 1969. https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010554599:mpeg21:p001
Website & Publikasi Resmi
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. https://peraturan.bpk.go.id/Details/49114/uu-no-12- tahun-1969