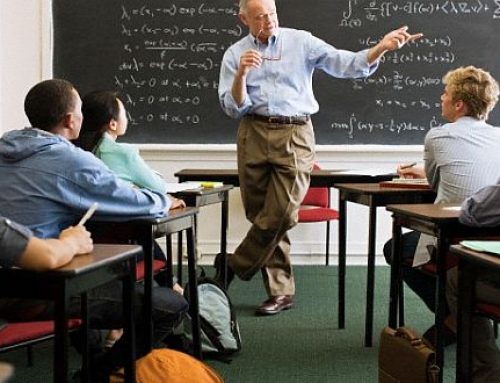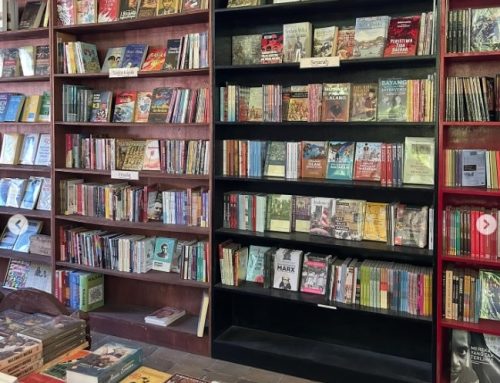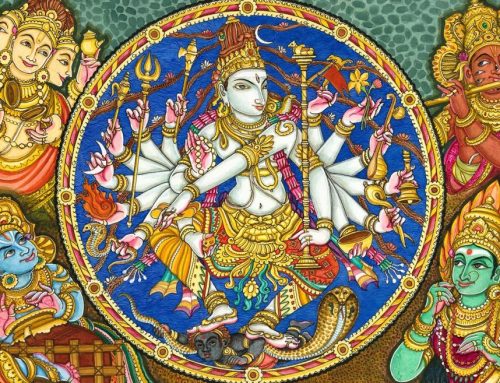Oleh: Dadan Adi Kurniawan
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sebelas Maret
Email: dadan.adikurniawan@staff.uns.ac.id
“Mumet iku bagian soko proses, tondo yen otak’e bener-bener pernah nggo mikir tenanan”
(Pusing itu bagian dari proses, tanda kalau otak kita benar-benar pernah digunakan untuk berfikir serius)
Apa yang Membedakan PTK dengan Penelitian Lainnya?
Dalam konteks budaya penelitian skripsi di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) memiliki karakter yang berbeda dengan penelitian Historis, Kualitatif maupun Kuantitatif. Baik Historis, Kualitatif maupun Kuantitatif, ketiganya merupakan jenis penelitian yang bertujuan memotret fenomena “alamiah” di lapangan. Jika Kualitatif dan Kuantitatif identik dengan penelitian yang memotret secara alamiah kondisi kekinian (saat ini), maka Historis adalah jenis penelitian yang memotret secara alamiah kondisi kelampauan (masa lalu). Ketiganya sama-sama memotret “keadaan alamiah” atau “keadaan murni” di lapangan tanpa ada campur tangan, rekayasa atau intervensi peneliti. Bedanya, Kualitatif dan Historis bersifat non-positivistik (tafsir sosial yang ruang lingkupnya luas karena tidak bersandar pada data angka, tidak bersandar pada hukum pasti yang empiris), sedangkan Kuantitatif bersifat positivistik (melihat sesuatu secara empiris dan menggunakan hukum pasti berdasarkan hitungan data angka). “Di dalam penelitian kualitatif, peneliti dilarang mengarahkan target penelitian dan mengkondisikan situasi di lapangan. Peneliti sebisa mungkin benar-benar memotret kondisi alamiah yang tidak dibuat-buat. Kalau perlu target yang sedang diteliti tidak mengetahui bahwa ia sedang diteliti, sehingga tidak terjadi adanya perubahan sikap dan kebiasaan. Penelitian Kualitatif berusaha memotret kondisi riil apa adanya di lapangan yang mencerminkan kondisi sehari-hari”.
Hal ini berkebalikan dengan prinsip kerja PTK yang justru merupakan jenis penelitian sarat akan intervensi atau campur tangan berupa “tindakan” (action) dari peneliti. Peneliti memberikan “tindakan” (semacam “terapi” dan “ramuan”) yang sudah diformulasikan dengan matang. Peneliti melakukan uji coba yang kemudian dipraktikan kepada pasien sesungguhnya. Sesuai namanya, PTK adalah jenis penelitian tindakan “di suatu kelas (di sekolah)”. Adapun kualitatif dan kuantitatif bisa saja di dalam kelas (sekolah) maupun di luar kelas (di masyarakat). Siapa yang ditindak? Siswa (peserta didik) di kelas tersebut. Berapa kelas? Satu kelas saja. Kenapa mesti ditindak? Karena dianggap memiliki “penyakit” alias “masalah” (problem). Contoh penyakit atau masalah-masalah di kelas yang perlu ditindak seperti apa? Contohnya seperti: rendahnya motivasi belajar, minat belajar, prestasi belajar, hasil belajar, kreativitas belajar, disiplin belajar, konsentrasi belajar, keterampilan menulis, kemampuan analisis, kesadaran sejarah, berfikir sejarah, kejujuran, toleransi, dll.
Jika dalam penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Historis bertujuan memotret dan melaporkan 100% kondisi apa adanya (apapun kondisinya, entah baik entah buruk), maka PTK bertujuan untuk memperbaiki kondisi/keadaan yang sebelumnya dianggap kurang/tidak baik supaya mencapai keadaan yang baik atau sangat baik (seperti yang diharapkan). Jika kondisinya belum baik, maka perlu diberi tindakan lagi hingga mencapai kondisi baik sesuai standar yang sudah ditetapkan peneliti. Sampai di sini sudah kelihatan kan perbedaan mendasar antara PTK dengan penelitian lainnya? Yak benar sekali, PTK adalah penelitian dengan memberikan intervensi “untuk memperbaiki keadaan”. Biasanya menggunakan judul “……untuk meningkatkan…..”, “……untuk mengembangkan…..”, “…… untuk mengoptimalkan…..”, “peningkatan ….. melalui”, dan sejenisnya. Yang berusaha diperbaiki/ditingkatkan tidak selalu soal “hasil belajar siswa”, tetapi juga “proses belajar siswa”, yang penting masih menjadi ranah otoritas atau kewenangan guru. PTK tidak bertujuan memperbaiki keadaan di luar pembelajaran/kelas yang bukan menjadi wewenang guru kelas misalnya seperti memperbaiki sistem manajemen sekolah, sistem kurikulum, pengelolaan keuangan sekolah, sistem penerimaan siswa, dll. PTK fokus memperbaiki proses dan hasil pembelajaran di dalam kelas, utamanya pada diri siswa. Adapun Kualitatif, Kuantitatif, dan Historis adalah penelitian tanpa intervensi/tindakan (campur tangan peneliti). Ketiga penelitian ini bertujuan “sekedar menyelidiki dan memotret keadaan alamiah apa yang ada di lapangan”. Ketiganya tidak bertujuan mencipta kondisi/keadaan sesuai yang diharapkan layaknya PTK.
Seperti Apa Judul PTK yang Ideal?
Judul ideal PTK memuat aspek What, How, Who (WHW). Secara garis besar judul PTK memuat: (1) tindakan apa yang akan diberikan; (2) kepada siapa dan di mana; (3) untuk meningkatkan apa.
What berkaitan dengan apa yang akan ditingkatkan/diperbaiki. Ini menjadi “variabel terikat” yang diperngaruhi (sebagai akibat). Jumlahnya untuk strata-1 (S1) adalah 1 sampai 2 variabel. Budaya di Prodi Pendidikan Sejarah UNS adalah 2 Variabel, meskipun sebagian kecil juga ada yang memilih 1 variabel saja. Variabel terikat sejatinya adalah “masalah” atau “penyakit” yang mau disembuhkan itu sendiri. Contoh variabel terikat yang menjadi target untuk dipengaruhi/ditingkatkan (disembuhkan) misalnya prestasi belajar, hasil belajar, nilai belajar, motivasi belajar, kreativitas belajar, minat belajar, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dll.
How berkaitan dengan tindakan/intervensi yang bagaimana yang akan diberikan. Ini menjadi “variabel bebas” yang mempengaruhi. Variabel bebas sejatinya adalah tindakan atau terapi yang dipilih sebagai senjata untuk mengobati penyakit (masalah). Variabel bebas ini contohnya seperti pemilihan model pembelajaran tertentu, metode pembelajaran tertentu, media pembelajaran tertentu, sumber belajar tertentu, dan sejenisnya.
Who berkaitan dengan target yakni siapa yang akan ditingkatkan (siswa kelas berapa, mata pelajaran apa, sekolah mana). PTK harus memilih satu kelas spesifik di sekolah tertentu. Misalnya kelas XI IPS-1 SMAN A, X IPA-5 SMA B, XII IPS-7 MA C, dll.
Berikut beberapa contoh judul PTK tentang Pembelajaran Sejarah:
- Penerapan Model Discovery Learning Untuk Meningkatkan Historical Comprehension dan Hasil Belajar Peserta Didik pada Mata Pelajaran Sejarah Kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Surakarta.
- Peningkatan Keterampilan Menulis Sejarah Siswa Melalui Penerapan Pendekatan Kontekstual Teaching Learning Berbasis Sumber Belajar Arsip Primer Sejarah di Kelas XI IPS 5 SMA Negeri 1 Surakarta.
- Penerapan Model Contextual Teaching Learning dengan Media Virtual Reality Candi Peninggalan Hindu-Budha di Jawa Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X-E7 SMA Negeri 1 Karanganyar.
- Penggunaan Media Path dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Hasil Beajar Peserta Didik Kelas X Teknik Bodi Otomotif SMKN 3 Boyolangu Kabupaten Tulungagung.
- Peningkatan Fokus Belajar dan Pemahaman Materi Peristiwa Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia melalui Penerapan Model Teams Games Tournament (TGT) Inovasi Ular-Ularan Pembelajaran Sejarah di Kelas XI IPA 5 MAN 1 Surakarta.
- Penerapan Media Sosial Line Dalam Pembelajaran Sejarah Indonesia Untuk Meningkatkan Keterampilan dan Hasil Belajar Siswa Kelas X Tata Boga 4 SMK Negeri 3 Malang.
- Penerapan Model Course Revie Horay (CRH) untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar Sejarah Peserta Didik Kelas X IPS 2 MA Negeri 1 Surakarta.
Seperti Apa Logika Latar Belakang Penelitian Tindakan Kelas?
Untuk bisa memberikan “tindakan yang tepat” (efektif alias manjur/mujarap), maka terlebih dahulu harus diketahui persis “apa penyakitnya” (masalahnya). Penetapan sebuah penyakit (masalah) bisa dilakukan karena melihat adanya “gejala-gelaja” (tanda-tanda) yang bisa dikenali. Setelah berhasil menemukan penyakit (masalahnya), maka langkah selanjutnya adalah mencari “akar penyebabnya” (akar penyebab masalah). Jika sudah diketahui akar penyebab masalahnya (penyakitnya), langkah selanjutnya yaitu “memberikan tindakan” (resep atau obat) yang dianggap paling pas alias paling manjur agar penyakitnya lekas sembuh. Untuk memudahkan pemahaman alur logika PTK, berikut adalah contoh PTK dalam dunia kesehatan. Penyakitnya: darah tinggi. Gejala: mudah marah-marah, mudah pusing, detak jantung tidak teratur dan mudah kelelahan. Akar penyebab: sering dipenuhi pikiran berat (sedikit-sedikit kepikiran). Solusi tindakan: bersikap cuek dan mengagendakan piknik/refreshing secara teratur. Contoh dalam konteks pembelajaran di kelas misalnya: Penyakit: Motivasi belajar rendah. Gejala: sering terlambat masuk kelas, pasif, sering tidak memperhatikan guru saat menjelaskan, ogah-ogahan mengerjakan tugas, dan hasil nilai PTS/PAS rendah. Akar penyebab: metode dan media belajar guru yang monoton dan membosankan. Solusi tindakan: menerapkan metode talkshow berbasis partisipsi aktif siswa di mana siswa ada yang berlatih menjadi host, menjadi narasumber, penanya, penyanggah, dan notulensi.
Bersandar pada logika di atas, sebuah latar belakang masalah PTK setidaknya memuat:
- Pembicaraan isu permasalahan utama (variabel terikat) di level nasional.
- Pembicaraan isu permasalahan utama yang ternyata juga ditemui di sekolah yang Anda teliti.
- Penjelasan gejala masalah (tanda-tanda) dari isu permasalahan utama di sekolah yang diteliti.
- Pemaparan perbandingan kondisi pembelajaran dari beberapa kelas.
- Penetapan satu kelas final yang paling problematik.
- Penetapan akar penyebab masalah dari kelas yang paling problematik tersebut.
- Alternatif tindakan/terapi/obat yang akan diterapkan;
- Alasan mengapa peneliti memilih tindakan/terapi/obat tersebut didasarkan pada rasionalisasi tindakan (secara teoritis menurut pakar dan secara rasional menurut peneliti) dan juga berdasar pada keberhasilan dari studi-studi yang sudah ada.
- Urgensi tindakan (penjelasan mengenai resiko jika tidak segera ditangani alias dibiarkan secara terus-menerus akan berdampak seperti apa).
Perlukah Peneliti Terjun (Studi Awal) ke Lapangan?
Cara menetapkan/memilih kelas, mengetahui gejala masalah, menetapkan masalah, dan mengetahui akar-akar penyebab masalah, semuanya diperoleh melalui data di lapangan. “Akan aneh atau dipertanyakan jika seorang peneliti bisa menemukan masalah bahkan menetapkan masalah di sebuah kelas, padahal ia belum turun ke lapangan, belum membandingkan antara kelas satu dengan kelas lainnya”. Untuk itu PTK bisa dilakukan kalau peneliti sudah terjun langsung ke lapangan yakni menyaksikan langsung (melakukan observasi), mengorek keterangan secara lisan (melakukan wawancara), dan didukung dengan adanya dokumen terkait (mencari dokumen penguat). Segala hasil observasi, wawancara dan dokumen ini perlu dilaporkan di latar belakang masalah. Perlu dilaporkan pula rincian bukti-bukti perbandingan kondisi dan hasil belajar antarkelas untuk memperkuat mengapa peneliti menjatuhkan pilihan pada satu kelas tertentu. Harus jelas jumlah pasti atau kisaran jumlah (bisa dalam bentuk prosentase) siswa yang pasif berapa, yang nilainya jelek berapa, yang tidur saat proses pembelajaran berapa, yang mainan HP sendiri berapa, yang terlihat malas-malasan berapa, dll. Jangan sekedar ditulis “ada sebagian siswa yang….”, “banyak siswa yang….” atau “sebagian besar siswa …”. Penulisan seperti ini kurang jelas dan detail. Penulisan yang rinci dan penarikan keputusan yang memiliki argumentasi jelas sangat penting sekali sebagai pondasi awal bahwa kelas yang akan diberi tindakan adalah kelas yang paling problematik saat itu.
Penjelasan terkait observasi, wawancara dan dokumen sebagai berikut:
- Observasi: Observasi awal peneliti hendaknya tidak dilakukan hanya sekali, melainkan harus beberapa kali. Mengapa demikian? Karena kalau hanya sekali hasilnya bisa saja bersifat “kebetulan”. Misalkan kebetulan kelas itu yang paling ramai, banyak siswa yang ndelalah sedang pada sakit, kelas itu yang paling pasif, guru sedang dalam kondisi agak sakit, tema materinya ngepasi kurang menarik, metodenya ngepasi kurang tepat, dll. Untuk itu diperlukan observasi awal setidaknya 2-3 kali. Observasi berapa kelas? Mestinya tidak hanya satu kelas. Observasi awal dilakukan di beberapa kelas untuk melihat kelas mana yang sekiranya paling masuk kriteria (paling buruk) untuk segera diberi tindakan. Waktu atau tanggal-tanggal observasi ini dicantumkan di dalam latar belakang.
- Wawancara: Selain melakukan observasi, dalam menyusun latar belakang PTK, peneliti juga harus melakukan wawancara awal dengan guru pengampu. Gunanya untuk apa? Untuk mencari informasi terkait kelas mana yang paling membutuhkan tindakan, masalah serius mana yang perlu segera ditangani, akar penyebab masalahnya kira-kira apa dari perspektif guru. Selain wawancara dengan guru, peneliti juga mestinya melakukan wawancara awal dengan beberapa siswa untuk menyelidiki apa yang dirasakan dari perspektif pasien. Bisa jadi akar masalah versi guru dengan versi yang dirasakan siswa berbeda. Menyelidiki pula kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang disukai oleh siswa guna mempertimbangkan pilihan tindakan/obat yang tepat. Tanggal, sumber dan hasil wawancara ini perlu dicantumkan di dalam latar belakang.
- Dokumen Pendukung: Selain observasi dan wawancara, dasar vonis peneliti akan lebih kuat jika mendapatkan dokumen awal misalnya seperti hasil rata-rata PTS/PAS dari beberapa kelas untuk mengetahui kelas mana yang paling rendah nilainya. Laporan dokumen ini perlu dicantumkan di dalam latar belakang.
Catatan Penting BAB II
1. Kajian Teori: Kajian teori dalam Penelitian Tindakan Kelas cenderung mudah. Cara menetapkannya tinggal melihat variabel-variabel penting pada judul. Misalnya PTK dengan judul: Penerapan Model Contextual Teaching Learning dengan Media Virtual Reality Candi Peninggalan Hindu-Budha di Jawa Untuk Meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X-E7 SMA Negeri 1 Karanganyar, maka teori-teori/konsep-konsep yang dipakai antara lain: (1) Model Contextual Teaching Learning, (2) Virtual Reality, (3) Motivasi Belajar, (4) Hasil Belajar, (5) Pembelajaran Sejarah. Model Contextual Teaching Learning menekankan aspek karakter model dan sintak yang mengikutinya. Virtual Reality menekankan pada rincian kegiatan teknis (penggunaan media belajar) yang akan dilakukan. Motivasi Belajar menurunkan kriteria-kriteria yang akan menjadi pedoman dalam pembuatan instrumen pengumpul data seperti angket, lembar observasi, dan lembar daftar pertanyaan wawancara. Instrumen pengumpul data tersebut harus dibuat detail dan cermat yang memuat indikator-indikator Motivasi Belajar. Dari mana indikator motivasi belajar diperoleh/ditetapkan? Dari hasil mencermati teori Motivasi Belajar yang dicetuskan para pakar. Hasil Belajar menurunkan kriteria apakah mencakup hasil belajar di ranah kognitif saja atau juga mencakup ranah afektif dan psikomotorik.
2. Sintak: Bagi pengambil PTK harus paham benar apa itu Sintak. Sintak adalah urutan atau langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Sintak sangat berkaitan dengan Model Pembelajaran. Untuk itu, di dalam Bab 2 Sintaknya harus jelas dan tuntas (clear). Apakah benar model pembelajaran tersebut memiliki sintak yang demikian. Terkadang Sintak yang dicantumkan tidak sesuai dengan model yang dipilih. Setiap model pembelajaran memiliki Sintaknya masing-masing, bahkan sintak dari setiap pakar pendidikan pun tidak sama persis. Untuk itu sumber referensi terkait model pembelajaran dan sintak pembelajaran yang dipakai harus kuat. Sintak ini harus benar-benar dipakai dan kelihatan saat membuat perencanaan dan kegiatan pelaksanaan.
3. Jumlah Siklus: Jumlah Siklus dalam PTK ada berapa? 1 Siklus? 2 Siklus? 3 Siklus? Atau berapa? Selama sudah mencapai standar/kondisi yang diharapkan, maka sebenarnya sudah cukup. Artinya 1 siklus pun kalau sudah mencapai standar yang diharapkan sudah cukup. Tetapi idealnya minimal 2 Siklus untuk melihat kemantaban (hasilnya lebih meyakinkan). Jika 2 siklus belum mencapai, maka lanjut 3 siklus. Jika 3 siklus belum mencapai, maka 4 siklus. Jika belum mencapai juga, kemungkinan jenis tindakan/terapi/obat yang diberikan kurang manjur (tidak efektif).
Catatan Penting BAB III
A. Sumber Data:
- Sumber Informan (siswa dan guru). Soal guru sudah jelas. Untuk siswa, kira-kira siswa yang mana yang akan diwawancarai? Apakah yang duduknya hanya yang depan saja? Apakah yang duduknya di depan, tengah, belakang? Atau mewawancarai siswa yang nilainya tinggi, sedang dan rendah? Atau mewawancarai siswa yang keaktifan tinggi, sedang dan rendah? Atau dasar pertimbangan lainnya?
- Sumber Aktivitas (kegiatan proses pembelajaran mulai dari pembukaan, kegiatan inti, hingga penutup).
- Sumber Dokumen (dokumen hasil angket, dokumen nilai hasil tes, dokumen daftar nilai, dokumen daftar presensi, dokumen lembar keaktifan siswa, dll).
B. Teknik Pengumpulan Data:
- Observasi yang dilakukan seperti apa, menyiapkan lembar observasi atau tidak, observasi dilakukan sendirian oleh peneliti atau mengajak teman (observer), siapa observernya.
- Wawancara dilakukan dengan cara bagaimana, terstruktur atau tidak terstruktur, wawancara langsung atau wawancara tidak langsung, wawancara dilakukan kepada siapa saja, pewawancara menyiapkan lembar daftar pertanyaan atau tidak.
- Studi dokumen dilakukan seperti apa dan dokumennya apa saja.
- Angket yang digunakan model apa, disusun sendirian atau juga dikonsultasikan ke siapa, berisi berapa butir poin pertanyaan/pernyataan, dasar penyusunannya berdasarkan apa.
- Tes yang digunakan jenisnya apa, apakah tes pilihan ganda, tes uraian, atau lainnya. Mengapa memilih tes jenis tersebut. Jumlah soal tes ada berapa, mengapa jumlahnya segitu, rentang kesulitan soal tesnya dari C berapa sampai C berapa (misal C1-C4), mengapa maksimal C-nya segitu. Tesnya secara langsung di kelas secara konvensional atau tes secara online (menggunakan aplikasi).
Buku Apa yang Harus Dibaca terkait Penelitian Tindakan Kelas (PTK)?
- Suharsimi Arikunto, Suhardjono, dan Supardi. (2019). Penelitian Tindakan Kelas. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- David Hopkins. (2011). Panduan Guru: Penelitian Tindakan Kelas. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wina Wijaya. (2009). Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta: Kencana.
- Masih banyak buku-buku Metodologi PTK lainnya. Silahkan cari dan lengkapi sendiri.
Siapa yang Idealnya Mengajar dan Menerapkan Tindakan di kelas?
Karena ide besar dan perancang utama PTK adalah mahasiswa (yang akan melakukan penelitian), maka idealnya yang mengajar adalah si mahasiswa itu sendiri. Sebenarnya bisa saja meminta bantuan guru asli di sekolah tersebut untuk menjalankan segala skema yang sudah direncanakan mahasiswa (yang sudah dikonsulkan juga ke guru dan dosen pengampu). Hanya saja tindakan tersebut kurang etis. Apakah iya si guru nantinya akan mau diatur-atur, diarahkan dan diberi masukan oleh mahasiswa selaku arsitek tindakan (pembuat perencana)? Oleh sebab itu, idealnya mahasiswa itu sendiri yang terjun langsung mengajar dan mempraktikan ide, gagasan dan tawaran tindakan (terapi/obat) yang diyakini manjur tersebut.
Berapa Idealnya Jumlah Pertemuan dalam 1 Siklus?
Satu siklus bisa terdiri dari satu pertemuan saja (1 pertemuan misalnya 2 x 45 menit). Tetapi idealnya, satu siklus minimal 2 pertemuan (1 pertemuan misalnya 2 x 45 menit, sehingga total 4 x 45 menit). Pertemuan Pertama untuk tahap pengenalan dan pemahaman terkait aturan main serta persiapan. Pertemuan kedua adalah pelaksanan inti tindakan. Jika semuanya dilakukan dalam satu pertemuan saja, dimungkinkan hasilnya kurang optimal. Banyak siswa yang mungkin masih gagal memahami aturan main model yang diterapkan guru (peneliti).
Apakah Soal Tes Perlu Diujicobakan?
Demi memastikan bahwa soal yang akan digunakan untuk tes tidak cacat, sebaiknya perlu diuji coba dahulu. Di kelas mana soal tersebut diuji coba? Jangan di kelas yang sedang diteliti. Namun diujicobakan di kelas lain yang memiliki karakteristik kemampuan tidak jauh berbeda. Apakah harus diujicobakan ke semua siswa? Tidak perlu, katakanlah diujicobakan ke 15-20 siswa saja sudah cukup. Dari hasil uji coba tersebut akan kelihatan apakah soal tes terlalu mudah, terlalu sulit, atau ada soal-soal tertentu yang cacat dikarenakan pemilihan kata/redaksi yang menimbulkan multi tafsir, sehingga jawaban yang diplih menjadi tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh si pembuat soal.
Kapan Idealnya Dilakukan Tes?
Idealnya tidak dilaksanakan bersamaan pada akhir pertemuan kedua dari Siklus I atau bersamaan pada akhir pertemuan kedua pada Siklus II. Lebih bagus kalau dicarikan waktu tersendiri khusus untuk tes. Supaya apa? Supaya materi yang disampaikan sebelumnya bisa mengendap dulu, bisa merasuk dahulu. Namun terpaksanya bisa dilakukan pada akhir pertemuan kedua pada tiap Siklus (jika seandainya tiap siklus terdiri dari 2 pertemuan).
Apakah Soal Tes Harus Berbeda Antara Siklus 1 dan Siklus 2?
Memang sebaiknya berbeda (meskipun tidak sepenuhnya). Sebagian kecil masih bisa dipakai dengan cara ditukar-tukar nomornya. Jika pada Siklus berikutnya sudah berganti materi, maka soal-soal yang baru otomatis juga menyesuaikan dengan materi baru. Perlu digaribawahi bahwa meskipun soal-soalnya berubah, tetapi level kesulitan dan tipikal soalnya tetap harus sama (konsisten), tidak boleh berubah. Jumlah soal level C2 pada Siklus 1 harus sama dengan jumlah soal level C2 di Siklus 2, dan jumlahnya harus sama lagi di Siklus 3 (jika seandainya sampai 3 Siklus). Jumlah soal level C4 pada Siklus 1 harus sama dengan jumlah soal level C4 di Siklus 2, dan jumlahnya harus sama lagi di Siklus 3 (jika seandainya sampai 3 Siklus). Tagihan level C tidak boleh terlalu tinggi melebihi tagihan Kompetensi Dasar di Modul Ajar. Jika tagihan di Modul Ajar maksimal hanya di level C4, maka menjadi kurang etis jika soal yang disusun mencapai level C5.
Kalau Ditotal-Total, Minimal Berapa Kali Peneliti Harus Masuk Kelas?
Jika ditotal semuanya, tentu peneliti akan masuk kelas berulang kali. Katakanlah untuk observasi awal (Pra Siklus) sebanyak 2 kali. Untuk tes awal (Pra Siklus) sebanyak 1 kali. Total masuk kelas untuk 2 Siklus sebanyak 4 kali. Untuk tes sendiri total sebanyak 2 kali (jika dilaksanakan di luar Siklus). Jika ditotal maka idealnya peneliti (mahasiswa) masuk kelas minimal sebanyak 9 kali. Namun di tengah padatnya kegiatan sekolah, idealitas tersebut terkadang sulit dilaksanakan. Sehingga waktunya bisa lebih dipersingkat, misalnya menjadi total 7 kali (dengan skema tiap tes diselipkan di akhir pertemuan ke-2 dari tiap Siklus).
Apakah Tindakan yang Sudah Terbukti Efektif di Kelas X Otomatis Bisa Diterapkan Juga di Kelas Lain atau di Sekolah Lain?
Tidak. PTK adalah penelitian yang ruang lingkup pengujiannya hanya di satu kelas tertentu. Hasilnya tidak bisa digeneralisasi. Sebuah Tindakan bisa jadi efektif diterapkan di kelas X tetapi belum tentu manjur diterapkan di kelas Y atau kelas-kelas lainnya, apa lagi di sekolah lain. Efektivitas jenis Tindakan/Terapi yang dipilih tidak bisa digeneralisasi (efektif di semua tempat dan keadaan). Bisa jadi manjur, bisa jadi tidak manjur. Hal ini dikarenakan tiap kelas memiliki karakter siswa yang berbeda-beda, memiliki tingkat kapasitas yang berbeda-beda, memiliki problematika yang berbeda-beda.
Catatan Penting BAB IV
1. Perlu Deskripsi Lengkap Jalannya Kegiatan
Ada cukup banyak Penelitian Tindakan Kelas yang pada bagian Bab 4, khususnya bagian “Pelaksanaan Kegiatan” baik Pendahuluan (Pembukaan), Tindakan Inti dan Penutup, tidak disampaikan secara rinci. Bagian “Pelaksanaan Kegiatan” ini harusnya disajikan/dilaporkan secara rinci. Disajikan bagaimana guru menyiapkan fokus siswa, dengan cara apa. Jika guru melakukan absensi, maka hasilnya seperti apa, berapa orang yang tidak masuk. Ketika guru memberikan pertanyaan stimulus, maka pertanyaannya seperti apa. Ketika guru menyuguhkan gambar stimulus, perlu diuraikan gambarnya gambar apa. Dijelaskan pula ada berapa pembagian kelompok, masing-masing beranggotakan berapa orang. Jumlah yang bertanya berapa orang dan siapa saja. Jumlah yang menanggapi ada berapa orang dan siapa saja. Jumlah yang menyanggah berapa orang dan siapa saja. Hasil karya dari pekerjaan tiap kelompok dideskripsikan. Cara menyimpulkan bersama seperti apa. Siswa yang berani maju menyimpulkan siapa dan kesimpulannya seperti apa. Seluruh proses pelaksanaan dari awal pembukaan hingga akhir penutupan, dideskripsikan selengkap mungkin. Bukan hanya deskripsi secara umum.
2. Jangan Pelit Catatan pada Refleksi Tindakan
Banyak kasus bagian Refleksi Tindakan di Bab 4 hanya diinventarisasi secara singkat-singkat. Mestinya bagian “Refleksi Tindakan” ini disampaikan secara detail terkait berbagai kekurangan pada pelaksanaan Siklus I. Misal jika masih ada yang bermain HP, maka kira-kira ada berapa orang. Kalau misal ada yang tidur, kira-kira siapa saja atau ada berapa orang. Kalau saat saat sesi tanya jawab, banyak yang nyontek, penyebabnya apa. Kalau peneliti selaku guru yang mengajar ada sesuatu yang terlewat (tidak dilakukan/disampaikan ke siswa), maka sesuatu yang terlewat tersebut apa. Kalau ada kesalahan guru (peneliti), perlu disebutkan dan penyebabnya apa. Kalau ada keteledoran-keteldoran, maka semua harus dicatat dan disajikan secara lengkap di bagian Refleksi Tindakan.
Perencanaan dan tindakan di Siklus II harus didesain (disempurnakan) berdasarkan hasil refleksi pada Siklus I. Begitu pun seterusnya, hasil refleksi Siklus 2 harus dijadikan dasar perbaikan dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan tindakan pada Siklus 3 (jika seandainya sampai Siklus 3). Setiap refleksi, peneliti mengkonsultasikan kepada observer (teman sejawat penelitian) maupun observer (guru). Peneliti juga sebaiknya menanyakan ke pihak siswa (beberapa orang). Ditanyakan kira-kira kekurangan atau kelemahan di pelaksanaan sebelumnya apa. Seluruh keterangan dan masukan sangat bermanfaat untuk bahan refleksi perbaikan ke tahap berikutnya.
3. Perihal Pembahasan
Dianalisis dengan: (1) Teori-Teori/Konsep-Konsep dan (2) Penelitian-Penelitian sebelumnya. Pada bagian ini menyerap banyak referensi (buku, jurnal, skripsi/tesis).



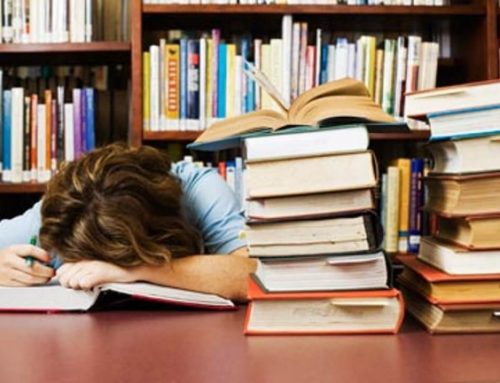


![Sejarah Kehidupan Sehari-hari [Hal-Hal Kecil] Sebagai Historiografi Alternatif dan Cara Pandang Baru](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/12/pasar-500x383.jpg)
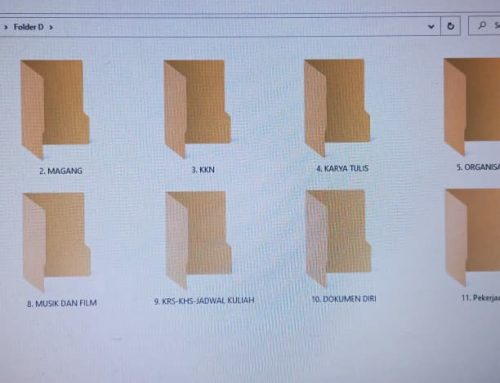








![Benarkah Kuliah di Jurusan Pendidikan Sejarah dan Ilmu Sejarah itu Tidak Penting [Tidak Berguna]?](https://sejarah.fkip.uns.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/lulusan-bertoga-500x383.jpg)