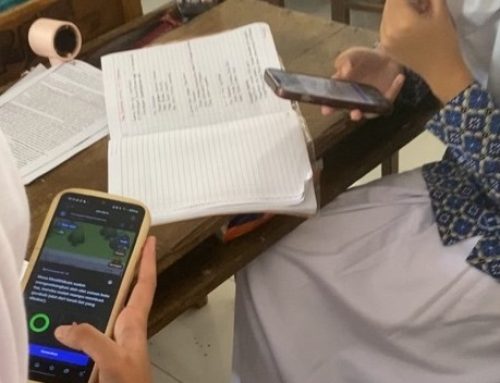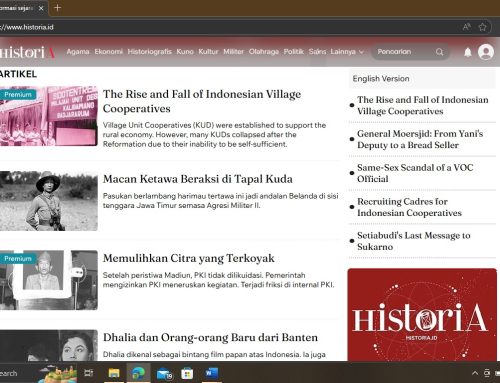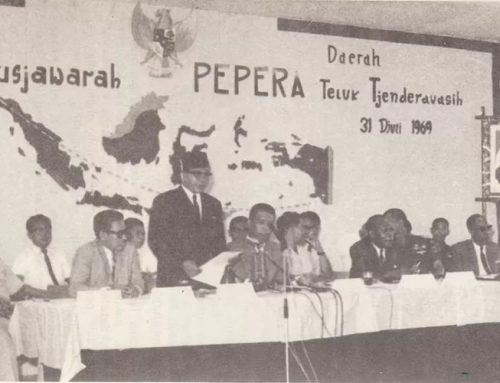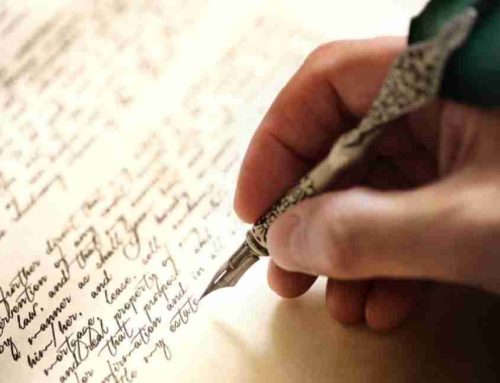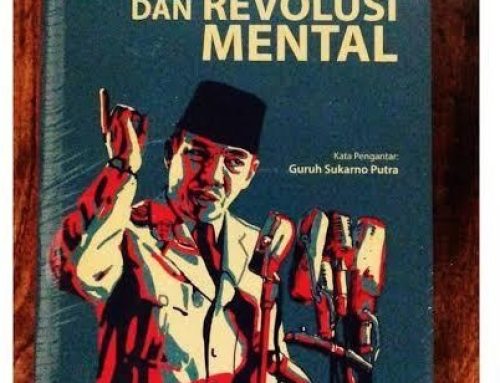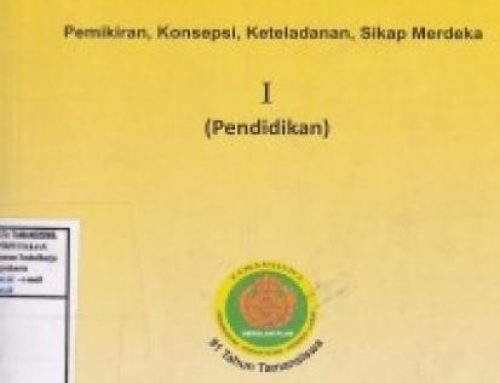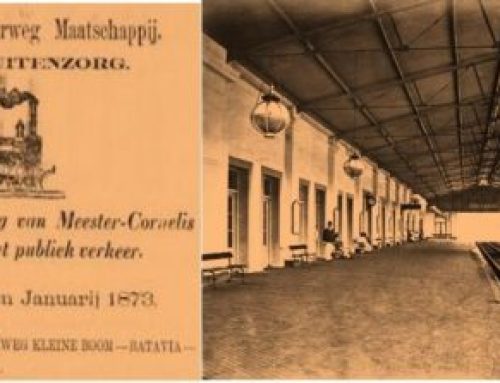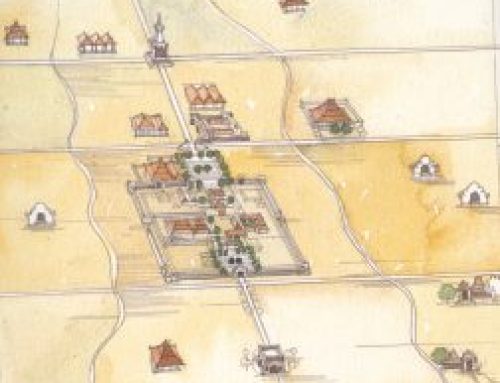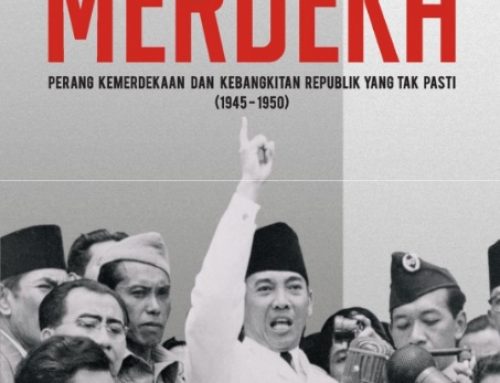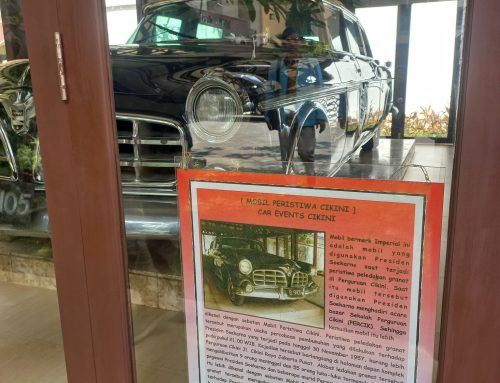Oleh: Ilham Putra Pratama* & Galih Putri Erlindawati* (*Mahasiswa Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2023)
Dalam berbagai lini kehidupan, perempuan kerap dihadapkan pada sistem yang menempatkan mereka dalam posisi subordinasi. Dalam perjalanannya, perempuan sering kali dianggap sekadar sebagai objek yang dapat dikendalikan oleh struktur kekuasaan yang lebih besar, baik dalam ranah politik, ekonomi, maupun sosial. Di Indonesia saat ini, kekhawatiran mengenai semakin kuatnya dominasi militer dalam ranah sipil melalui Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) memunculkan kembali pertanyaan tentang bagaimana kekuasaan dapat memperkuat sistem patriarki. Perluasan kewenangan militer tidak hanya beresiko mengancam prinsip demokrasi, tetapi juga dapat memperkokoh budaya patriarki yang telah lama mengakar. Ketika negara memberikan otoritas lebih besar kepada institusi yang didominasi oleh laki-laki, maka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam masyarakat semakin terpinggirkan. Dalam konteks ini, perempuan menjadi semakin rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan berbasis gender.

Gambar 1. Sebuah lukisan cat air karya Ernest Hurdoin, yang menggambarkan seorang “Njai” (sebutan untuk seorang wanita yang diperistri secara tidak resmi) (sumber: KITLV 36B185)
Kondisi ini semakin nyata ketika melihat bagaimana perempuan sering kali hanya dipandang sebagai komoditas, bukan sebagai individu yang memiliki hak penuh atas tubuh dan kehidupannya. sebagaimana yang terlihat dalam kasus viral seorang guru SD di Jember. Ia menjadi korban manipulasi ketika sang mantan menjanjikan hadiah berupa mobil sebagai imbalan untuk mengirimkan video asusila. Namun, janji tersebut hanya tipu daya belaka, dan pada akhirnya video tersebut disebarluaskan tanpa persetujuannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana perempuan masih sering diposisikan sebagai objek yang bisa dimanipulasi, dikendalikan, dan dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan. Masyarakat masih cenderung menyalahkan perempuan dalam kasus-kasus pelecehan dan eksploitasi seksual seperti ini, seolah-olah perempuanlah pihak yang paling bertanggung jawab atas ketidakadilan yang menimpa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan masih sering dianggap hanya sebagai pemuas nafsu, bukan sebagai manusia yang berdaulat atas dirinya sendiri.
Namun, apakah dalam setiap zaman dan dalam berbagai struktur kekuasaan, perempuan selalu ditempatkan dalam posisi subordinasi? Apakah mereka selalu dipandang sekedar sebagai komoditas yang dapat didomestikasi, baik secara politik maupun seksual, tanpa ruang untuk berperan sebagai subjek yang aktif dalam dinamika kekuasaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menilik kembali sejarah, khususnya dalam konteks kerajaan-kerajaan islam di Jawa bagian tengah. Sejak masa lampau, konsep kekuasaan di Jawa sangat erat kaitannya dengan figur raja yang dianggap memiliki legitimasi ilahiah.; “segala sesuatu di Jawa, tanah tempat kita berpijak, air yang kita minum, rumput, dedaunan, semuanya milik raja.” Menjadi tugas raja untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan setiap orang diharapkan mematuhinya tanpa syarat. Seperti diketahui para raja-raja Jawa dahulu, utamanya eks kerajaan Mataram Islam, dapat memiliki hingga empat istri resmi atau garwa padmi dan sejumlah istri tidak resmi, yaitu selir atau garwa ampeyan (Carey & Houben, 2016, hlm. 45). Luasnya kekuasaan raja tercermin dari banyaknya selir, semakin banyak selir, semakin berwibawalah raja tersebut. Kata selir sendiri sebenarnya berasal dari kata sineliran yang berarti mereka “yang terpilih” — namun di masa kolonial kata Selir disalah artikan oleh orang-orang belanda sebagai bijwiff atau concubine (gundik), dengan kata lain, pada pandangan kolonial selir tidak lebih dari sekadar objek (Kumar, 1980, hal. 18; Hull, 2017, hal. 66).
Mengambil selir bagi para raja Jawa merupakan salah satu strategi kekuasaan, dimana hal ini dapat kita pahami secara sederhana sebagai perkawinan politik, dimana beberapa selir tersebut merupakan putri priyayi (bangsawan) kelas bawah yang diberikan kepada raja sebagai tanda loyalitas mereka. Selain itu ada pula yang menyerahkan putrinya sebagai “upeti” tanda takluk, suatu perpaduan antara motif seksual dan politik (Hull, 2017, hlm. 66). Dengan demikian, mereka dapat memelihara hubungan kekerabatan antara raja dengan keluarga terkemuka kerajaan dalam suatu ikatan intim dengan dunia pedesaan Jawa melalui ikatan kekeluargaan yang luas (Carey & Houben, 2016, hml. 45). Ada pula rakyat biasa yang menjual atau memberikan putri mereka dengan motif sebagai jalan untuk mengubah status mereka, kebanyakan dari mereka berharap jika putri mereka dinikahi raja maka akan meningkat lah derajat putri mereka serta keluarga. Apalagi jika kelak dapat melahirkan anak bagi sang raja, biasanya mereka tidak hanya dijadikan selir, ada beberapa yang dijadikan permaisuri.
Sementara itu perbedaan cara pandang orang Belanda terhadap budaya ini, yang kemudian membuat orang-orang Belanda hanya memanfaatkan selir sebagai pemuas syahwat belaka, sebagai contoh pada 1789 terdengar berita tentang Johan Frederik baron van Reede tot de Parkelaar (1757–1802), seorang saudagar di surakarta (kelak menjadi residen Surakarta, menjabat 1891) Ia dianggap membaurkan agama dan syahwat, anggapan demikian muncul lantaran ia memiliki banyak selir. “bisa saja dia terlihat membaca alkitab dan berdoa, sementara itu ia dikelilingi selusin pelacur makasar dan Jawa yang terus menerus merangsangnya secara menggairahkan.”(Boxer, 1983, hlm. 135)Kembali lagi, masing-masing kerajaan di Jawa “memasok” selir dari beberapa daerah tertentu, utamanya daerah daerah yang dianggap sebagai penghasil perempuan cantik dan memikat, setidaknya ada 11 kabupaten di Jawa yang menurut catatan sejarah merupakan daerah penghasil “komoditas” perempuan-perempuan untuk kerajaan, menariknya daerah daerah tersebut hingga saat ini tetap bertahan sebagai penghasil perempuan cantik namun untuk kepentingan lain (kabupaten-kabupaten itu saat ini justru dikenal sebagai daerah “pemasok” perempuan untuk prostitusi di kota-kota besar). Adapun 11 kabupaten tersebut adalah; Indramayu, Karawang, dan Kuningan di Jawa Barat; Pati, Japara, Grobongan, dan Wonogiri di Jawa Tengah; serta Blitar, Malang, Banyuwangi, dan Lamongan di Jawa Timur (Koentjoro, 1989, hlm. 3; Hull, 2017, hlm. 66). Kecamatan Gabus Wetan di Indramayu terkenal sebagai daerah asal praktik prostitusi modern, tetapi akar dari praktik tersebut tampaknya telah ada sejak masa ketika perempuan muda dari daerah tersebut dikirim ke istana Sultan Cirebon.

Gambar 2. Potret Wanita Jawa yang sedang mengenakan batik (Sumber: Tropen Museum)
Hal ini kemudian berkorelasi dengan kebiasaan mementingkan kecantikan & daya tarik seksual oleh para selir di masa lalu, seperti yang diungkapkan J.W. Winter seorang penerjemah resmi keraton Kasunanan Surakarta:
“[…] Pelajaran tentang menulis, membordir, dan menjahit tidak memiliki tempat [dalam pendidikan mereka] […] yang dianggap perlu untuk anak perempuan adalah melatih mereka bagaimana mengatur kecantikan. Dari kecil, mereka diajar menepis semua rasa malu, […] dan yang dididikkan kepada wanita muda itu hanya satu hal: bagaimana berparas cantik, berlagak sopan, dan bertingkah laku pantas. Untuk pergi dengan payudara mereka hampir telanjang bulat, menghindari bicara ketika bergaul dan berlatih berpura-pura dengan wajah merona malu-malu dan bersikap sembunyi-sembunyi hingga mereka pada akhirnya dipilih sebagai perempuan piaraan [Sunan] di Keputren, di mana mereka bisa memakai daya tarik seksualnya untuk memikat raja supaya disukai diatas semua [selir yang lain […].” (Winter, 1902, hlm. 40) tentu kecantikan dan daya pikat seksual merupakan semacam keharusan untuk memperhalus karir seorang selir.
Perlakuan sebagai “komoditas” yang demikian terhadap perempuan tidak hanya terjadi di Jawa, namun hampir di seluruh Nusantara. Di Bali misalnya, jika seorang janda yang berasal dari kasta rendah tidak mendapat dukungan kuat dari keluarganya secara otomatis ia akan menjadi “hak milik” raja, kemudian jika sang raja memilih untuk tidak memasukkan-nya kedalam rumah tangga sang raja, maka ia akan dikirim ke daerah pedalaman untuk menjalankan prostitusi, dan sebagian pemasukannya secara teratur harus diberikan kepada sang raja (Sunjayadi, 2018).
Kembali lagi ke Jawa, meski bila dilihat secara kasat mata hubungan selir dan raja tidak lebih dari sebuah hubungan yang menggairahkan, namun akan menjadi kesalahan besar bila ada anggapan bahwa kunci hubungan antara raja-raja Jawa dengan istrinya selalu dititik beratkan pada hubungan seksualitas saja. Seperti yang telah dijelaskan di awal jika pernikahan itu juga diatur dengan tujuan dan maksud tertentu, seperti memperkuat dukungan politiknya dengan membentuk aliansi politik dengan keluarga-keluarga bangsawan lokal yang kuat serta memiliki potensi untuk menjadi lawan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa perempuan dari keluarga atau areal tertentu dipilih menjadi permaisuri. Dalam kasus ini, kecantikan kalah abu dibandingkan manfaat politik yang bisa diperoleh dari perkawinan tersebut (Carey & Houben, 2016, hlm. 49). Kecantikan sejumlah permaisuri dari Pulau Madura yang dinikahi Sunan Surakarta pada abad ke-18 tidak sebanding dengan para istri raja Jawa. Pernikahan tersebut bukan semata urusan pribadi, melainkan bagian dari strategi politik untuk mempererat hubungan dengan penguasa lokal Madura, khususnya keluarga Cakraningratan yang merupakan keturunan Panembahan Cakraningrat II (séda Kamal, 1647–1707, bertakhta 1705–1707) dari Madura Barat (Bangkalan), yang muncul sebagai kekuatan utama dalam politik Jawa Timur pada tahun- tahun penuh perang dan gejolak politik antara 1704 dan 1745 (Padmamusastra, 1902, hlm. 153–168; Ricklefs, 2001, hlm. 110–125)
Di Yogyakarta, kondisi yang serupa juga berlaku. Namun pada kasus ini pilihan jatuh kepada putri bupati mancanagara timur yang jauh dari keraton dan dianggap berpotensi menjadi pusat pembangkangan politik. Pemberontakan singkat Bupati Wedana Madiun, Raden Ronggo Prawirodirjo III (menjabat 1796–1810), pada November-Desember 1810 adalah satu contoh. Menariknya, dua dari tiga permaisuri Sultan Hamengkubuwono II dan Sultan Hamengkubuwono III, yang memerintah pada periode 1812–1814, berasal dari kawasan timur tersebut. Selain itu, banyak keturunan sultan, termasuk Pangeran Diponegoro, menikah dengan anggota keluarga bangsawan mancanegara timur, memperkuat hubungan politik dan kekerabatan antara keraton Yogyakarta dan wilayah tersebut (Carey & Houben, 2016, hlm. 49).
Selain itu, pernikahan politis tidak hanya terjadi antara penguasa dengan putri bangsawan lainnya, tidak jarang istri raja berasal dari keluarga Kyai dan ulama, sebagaimana misal Garwa Padmi sultan Mangkubumi, Ratu Kadipaten (Ratu Ageng Tegalrejo) yang merupakan keturunan dari Ki Ageng Derpoyudo, kemudian ibu dari pangeran Diponegoro, Raden Ayu Mangkorowati (sekitar 1770–1825) masih memikiki trah Ki Ageng Prampelan (Seorang generasi kesepuluh Sunan Ngampel Dentho) (Serat Salasilah Para leloehoer ing Kadanoerejan, t.t. hlm. 27). Politik pernikahan tersebut tidak berlangsung satu arah saja, biasanya Putri dari Garwa Ampeyan atau keponakan raja diperistrikan dengan para ulama dari desa-desa perdikan pesantren terkemuka seperti Tegalsari (Ponorogo) dan Banjarsari (Madiun), juga dengan para Sayyid dari dinasti wali terkenal di Tembayat, hal ini menunjukkan bagaimana keraton menjalankan politiknya untuk membangun koneksi dengan dunia pedesaan, jaringan ini amat penting sebagai jalan meredam ancaman pembangkangan dari masyarakat agamis, lewat hubungan pernikahan dan pemberian daerah atau desa perdikan (Fokkens, 1877, hlm. 321–323; Carey & Houben, 2016, hlm. 60–61).Memang sistem feodal tidak serta merta mengandung unsur komersialisasi seksual secara keseluruhan bila kita mengasosiasikannya dengan dominasi unsur politik yang begitu kental. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri, jika pada praktiknya, feodalisme juga dapat menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengidentifikasi nilai perempuan sebagai komoditas.