Oleh: Jingga Asri Naila Hasna (Mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS Angkatan 2023)
Pendahuluan
Perang Teluk II (2003- 2011) merupakan periode panjang setelah terjadinya Perang Teluk I (1990-1991). Perang Teluk II dipimpin oleh negara negara Barat terutama Amerika serikat untuk menjatuhkan rezim Saddam Hussein di Irak, dimulai dengan Operation Iraqi Freedom pada tahun 2003. Ketika Perang Teluk I (1990-1991) Irak menginvasi Kuwait, sehingga memicu reaksi pasukan pentagon AS dan pasukan multinasional, karena invasi ini dianggap melanggar hukum PBB. Selain itu, Irak juga dicuragi memiliki senjata pemusnah masa (WMD). Sehingga Irak di serang pasukan multinasional dari gabungan berbagai negara termasuk sekutu AS yaitu Inggris, serangan ini dipimpin oleh AS. Hingga awal 1991 invasi Irak ke Kuwait atau biasa di sebut Perang Teluk II berhasil ditumpas. Irak juga mendapat sanksi embargo dari Dewan PBB yang melemahkan stabilitas ekonomi Irak dan memikili dampak berkepanjangan bahkan sampai sekarang. Meskipun rezim Saddam Hussein mampu bertahan, banyak pihak menganggap Irak sebagai faktor ketidakstabilan di kawasan Asia Barat Daya.

Gambar 1. Spesialis Infanteri 3-7 Divisi 3 Angkatan Darat AS, bertugas di garis depan bersama peletonnya pada tanggal 29 Maret 2003, di dekat kota Karbala di Irak (Nelson, 2003). Diakses dari https://edition.cnn.com/2013/10/30/middleeast/operation-iraqi-freedom-and-operation-new-dawn-fast-facts
Pada 2001 menara kembar WTC diserang oleh kelompok Al-Qaeda, akibat serangan ini presiden AS yang menjabat kala itu George W. Brush mulai merubah pandanganya pada Irak, ia menganggap bahwa Saddam Hussein adalah rezim yang membahayakan dan melatar belakangi perlindungan pada serangan teroris tersebut. Walau tidak ada bukti yang menyatakan bahwa serangan 9/11 ada keterlibatan Irak di dalamnya. Selain itu ada intelejen AS yang melaporkan bahwa Irak berusaha menghidupkan program senjata pemusnah massal, meski begitu adanya senjata pemusnah masal di Irak tidak terbukti benar hingga kini. Dengan alasan-alasan menjaga perdamaian dan menghilangkan ketakutan akan adanya senjata pemusnah masal kala itu membuat AS mulai menginvasi Irak dengan melancarkan Operation Iraqi Freedom (2003) yang menciptakan konflik Panjang dari tahun 2003-2011.

Jalanya Operation Iraq Freedom
Perang Teluk Kedua (2003-2011) dimulai dengan invasi AS pada 20 Maret 2003 untuk menggulingkan rezim Saddam Hussein melalui kampanye udara “shock and awe” yang menghancurkan infrastruktur militer Irak dan memungkinkan serangan darat cepat ke Baghdad, yang jatuh pada 9 April 2003. Setelah kemenangan awal, AS membubarkan pemerintahan Saddam dan militer Irak, menciptakan kekosongan kekuasaan yang memicu munculnya kelompok pemberontak, termasuk mantan loyalis Saddam dan milisi Sunni-Syiah. Pada 2004, Al-Qaeda di Irak (AQI) di bawah Abu Musab al-Zarqawi melancarkan serangan besar terhadap pasukan koalisi dan warga sipil, dengan pertempuran sengit terjadi di Fallujah. Konflik meningkat menjadi perang saudara pada 2006 setelah pengeboman Masjid Kubah Emas di Samarra, memicu kekerasan sektarian. Sebagai respons, AS meningkatkan jumlah pasukan melalui “operasi surge” pada 2007, mengirim 30.000 tentara tambahan untuk menstabilkan wilayah-wilayah utama. Strategi ini, bersama gerakan Sunni Awakening, mengurangi kekerasan hingga 2008, memungkinkan AS menarik pasukannya secara bertahap setelah perjanjian SOFA pada 2008. Pada 2011, AS resmi mengakhiri operasi militernya di Irak, tetapi negara itu tetap dilanda ketidak stabilan politik, korupsi, serta ketegangan sektarian, yang pada 2014 memungkinkan ISIS muncul dan merebut wilayah luas, memperpanjang krisis yang masih berlanjut hingga kini (Al-Fattah, 2024) Lebih dari 100.000 warga sipil tewas sejak invasi Amerika di Irak, menurut database Irak Body Count, sedangkan AS kehilangan hampir 4.500 tentara (Iswara, 2022).
Dampak Perang Teluk II
1. Bidang Kesehatan
Ketika Rezim Saddam Hussein masih berkuasa (1990-2003), paramedis banyak yang mengutuk pemerintahan Saddam yang kejam, dimana seorang tenaga medis hanya digaji sekitar 1$ setiap bulannya. Hal ini tentunya membuat fasilitas kesehatan bagi masyarakat tidak memadai. Setelah AS menggulingkan Rezim Saddam Hussein pada 2003, warisan kekacauan Invasi, nyatanya masih dirasakan rakyat Irak. Invasi yang tergesa gesa dengan kurangnya perencanaan lanjutan, menyebabkan dominasi hukum suku di Irak. Di mana tidak ada penegakan hukum yang komprehensif yang disetujui negara. Akibatnya, perselisihan antara dokter dan pasien sebagian besar ditangani oleh suku yang sering menyalahkan dokter atas gagal perawatan medis yang buruk, yang mengakibatkan serangan berulang terhadap tenaga medis. Irak tidak mampu memberikan perlindungan apa pun pada para tenaga medis. Kepergian massal para tenaga medis dari Irak diakibatkan kekerasan yang merajalela.
Pada tahap awal konflik tahun 2003, diperkirakan 12% rumah sakit hancur menurut laporan yang diterbitkan oleh Kongres AS. Perang saudara yang dimulai pada tahun 2006 memaksa banyak petugas medis untuk pergi karena mereka terus-menerus takut menjadi sasaran karena mereka beragama Sunni atau Syiah. Pemberontakan berikutnya yang menyebabkan munculnya ISIS. Karena tidak adanya perlindungan yang memadai bagi para petugas medis, membuat mereka tidak ingin mempertaruhkan hidupnya di negara yang tidak stabil seperti Irak. Jumlah klinik yang menyusut akibat konflik semakin memperburuk kondisi rakyat Irak. Seorang pejabat yang bekerja di Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa hanya ada satu klinik umum yang melayani sekitar 100.000-150.000 orang di Baghdad. Rasio tersebut bahkan lebih besar lebih rendah di daerah pedesaan.
According to data compiled by the World Bank, health expenditure per capita in Iraq is substantially less than the world average and was consistently less than US$200 until 2017. Spending rose in the years after the defeat of ISIS, only to fall to $202 in 2020. By comparison, the world average had exceeded $1000 by 2013 (Yuan, 2023).
Sistem keuangan yang buruk menghambat perkembangan layanan kesehatan Irak, korupsi juga merajalela, obat obatan terlarang serta obat tanpa izin, palsu dan kadaluarsa bebas keluar masuk negara Irak bahkan digunakan sebgai bisnis sejak jatuhnya rezim Saddam Hussein. Selain itu tindak korupsi yang semakin marak karena Partai politik di Irak hanyalah mafia, dan mereka tidak bertanggung jawab kepada rakyat. Sehingga fasilitas serta program kesehatan benar benar tidak berjalan dan tidak memadai.
One agent who distributes medicines from smugglers to pharmacy owners across the country said that the investment in prescription drug smuggling began soon after the war. “It was a lucrative business because people needed medicines when there was conflict all the time and the government was not doing anything to help with that”, said the agent, who asked for anonymity. “99% of the drugs I sell came from smuggling”, one pharmacist who owns a pharmacy in Baghdad’s Zayouna district said, “because the government has little capacity to examine all needed drugs for official import, and the smuggled drugs are much faster and oftentimes cheaper (Yuan, 2023)
Korupsi telah menjadi rahasia umum di Irak, seorang mantan Perdana Menteri Harusafa al-Kadhimi mengatakan bahwa antara tahun 2003 dan pertengahan tahun 2020, korupsi telah menghabiskan lebih dari $600 miliar dana Irak. Hasilnya merugikan bidang kesehatan yang sudah sangatlah rapuh, turut serta menyebabkan fasilitas kesehatan Irak menjadi ketinggalan zaman dan kekurangan obat-obatan penting. Pada tahun 2021, ada dua kebakaran besar di dua rumah sakit terpisah di Baghdad dan Nasiriyah, sebuah kota di Irak selatan, kebakaran ini menewaskan lebih dari 150 orang secara kolektif.
Nyatanya praktek penyelundupan obat terlarang dari negri tetangga seperti Yordania, Iran, dan Turki, banyak diketahui pejabat Irak, namum mereka juga tidak bisa berbuat banyak, sebab para apoteker terkadang dilindungi oleh milisi. Sehingga praktek semacam ini telah menjadi rahasia umum. Sementara itu pertentangan kelompok Sunni dan Syiah mengancam keselamatan tenaga kesehatan mengakibatkan semakin terbatasnya fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat Irak selama perang teluk II.
2. Bidang Kemanusiaan
Kekerasan senjata adalah masalah kemanusiaan yang besar di Irak selama Perang Teluk II. Dari database Iraq Body Count yang berisi data statis 120.108 kematian warga sipil Irak akibat kekerasan bersenjata yang terjadi sejak 20 Maret 2003 sampai Desember 2011. Iraq Body Count (IBC) adalah proyek independent yang berusaha mendokumentasikan jumlah korban sipil akibat kekerasan di Irak sejak Invasi AS pada tahun 2003. Mereka menggunakan berbagai sumber, termasuk laporan media, catatan medis, dan wawancara dengan keluarga korban, untuk memperkirakaran jumlah korban invasi. Meskipun sulit mendapat angka yang pasti. Data ini dapat digunakan untuk mendesak pemerintah dan organisasi Internasional untuk segera mengambil tindakan agar mengakhiri konflik dan memberikan bantuan kemanusiaan pada warga sipil Irak yang menjadi korban.

Gambar 3. Diagram Batang Korban Perang Teluk II. Dikases dari http://www.iraqbodycount.org

Gambar 4. Jumlah Korban Perang Teluk II. Diakses dari http://www.iraqbodycount.org
Sebagian besar kematian warga sipil Irak akibat kekerasan selama perang Irak tahun 2003–2008 dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal, terutama melalui eksekusi di luar hukum yang meningkat secara tidak proporsional di wilayah tersebut dengan jumlah kematian akibat kekerasan yang lebih besar. Pelaku yang tidak dikenal yang menggunakan bom bunuh diri, bom kendaraan, dan mortir memiliki dampak yang sangat mematikan dan tidak pandang bulu terhadap warga sipil Irak yang menjadi sasarannya. Kematian yang disebabkan oleh pasukan Koalisi terhadap warga sipil Irak, wanita, dan anak-anak mencapai puncaknya selama periode invasi, dengan dampak yang tidak pandang bulu dari serangan udara.
A global assessment of the burden of armed violence in 2004–2007 found that persons living in Iraq had the highest risk of dying violently in conflict, peaking at 91 violent deaths per 100,000 population in 2006 (Geneva Declaration Secretariat, 2008). In 2009, we described patterns of civilian death caused by different weapons used in the Iraq war, and highlighted weapon-effects on children and female civilians (Hicks, 2009)
IBC secara akurat mencerminkan sifat konflik bersenjata Irak dan sejauh mana pelaku kekerasan dapat, dan tidak dapat, diidentifikasi, melalui tiga kategori pelaku utamanya: pasukan koalisi, pasukan anti-koalisi, dan pelaku yang tidak dikenal. Kematian dikaitkan dengan pasukan koalisi (yang sebagian besar terdiri dari pasukan AS). Pasukan anti-Koalisi, meskipun secara visual tidak dapat dibedakan dari warga sipil, diidentifikasi sebagai Anti-Koalisi melalui serangan mereka terhadap target Koalisi (yang mencakup target yang terkait dengan Koalisi, seperti pos pemeriksaan polisi Irak, pasukan keamanan Irak, dan target pemerintah). Pelaku yang tidak dikenal adalah mereka yang menargetkan warga sipil (yaitu, tidak ada target militer yang dapat diidentifikasi), sementara tampak tidak dapat dibedakan dari warga sipil misalnya, seorang pelaku bom bunuh diri yang menyamar sebagai warga sipil di sebuah pasar (Hicks, 2011)
Kematian perempuan dan anak akibat pasukan Koalisi mencapai puncaknya selama invasi pada tahun 2003, sedangkan kematian akibat pasukan Anti-Koalisi mencapai puncaknya pada tahun 2004–2005. Meskipun status sipil anak anak dan wanita dilindungi oleh hukum perang. Namun nyatanya pelaku perang teluk II tidak kenal bulu, dan menargetkan siapapun termasuk wanita dan anak anak sebagai warga sipil.
3. Bidang Pers
Selama lebih dari tiga dekade sebelum jatuhnya rezim Saddam Hussein pada bulan April 2003, media Irak dikontrol ketat oleh negara. Media cetak, radio, dan TV disensor ketat oleh Kementerian Informasi Irak (Najjar, 2004; Sinjari, 2006). Di bawah sistem pers semacam ini, jurnalis menjadi pendukung pemerintah yang berkuasa, tidak ada ruang bagi jurnalis untuk berfungsi dalam peran pengawas pers. Judul berita surat kabar Irak serta laporan berita radio dan televisi memuji Presiden Hussein dan keluarganya, praktik umum yang ditemukan tidak hanya dalam berita tetapi juga dalam bentuk media massa lainnya termasuk musik dan film. Akses internet juga sangat dibatasi. Sebelum jatuhnya Baghdad ke tangan AS dan pasukan koalisi, Kementerian Pertahanan Irak Informasi dan Persatuan Jurnalis Irak, yang dipimpin oleh putra sulung Hussein, Uday, mengendalikan enam surat kabar harian dan selusin surat kabar mingguan (Najjar, 2004). Tugas utama Kementerian Informasi adalah mengendalikan jurnalis dan mengubah mereka menjadi boneka propaganda melalui korupsi dan terror (Schaper, 2003)
Setelah runtuhnya rezim Saddam Hussein gelombang baru kebebasan pers dan banyak media muncul dengan cepat. Tak lama setelah jatuhnya Baghdad, lebih dari 25 stasiun radio dan televisi muncul dan jumlah surat kabar pada satu titik mencapai puncaknya di angka 150, yang memicu harapan akan kebebasan pers yang lebih besar dan pembentukan masyarakat demokratis baru. Teknologi media yang pernah dilarang seperti antena parabola dan Internet kini tersedia, yang memungkinkan warga Irak untuk menonton saluran TV pan-Arab, berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan email, dan mengunjungi situs web untuk pertama kalinya. Namun hambatan baru segera muncul, kurangnya tenaga yang kompeten pada bidang junalistik mengakibatkan banyak media jurnalistik yang harus tutup karena kesulitan keuangan dan pendapatan iklan yang rendah.
Runtuhnya rezim Saddam melepaskan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para jurnalis yang diwawancarai mengungkapkan keinginan mereka untuk demokrasi dan kebebasan pers dengan menyingkirkan belenggu jurnalisme dari era lampau. Hampir semua jurnalis yang diwawancarai setuju bahwa ada lebih banyak kebebasan pers saat ini dibandingkan dengan era Saddam. Meskipun kebebasan pers baru ditemukan di Irak, masih banyak kendala yang menghalangi jurnalis untuk melaporkan berita buruk tentang pemerintah atau politisi. Jurnalis Irak terus-menerus menjadi sasaran kelompok ekstremis dan milisi sektarian dan bahkan oleh beberapa pejabat di pemerintah pusat dan provinsi. Meskipun beberapa jurnalis yang diwawancarai mengakui bahwa mereka dapat menulis cerita tentang dugaan korupsi dalam pemerintahan pusat dari waktu ke waktu, milisi dan kelompok militan lain yang terkait dengan beberapa politisi, tindakan ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan jurnalis. Akibatnya, jurnalis menyensor diri sendiri dengan menahan atau menghapus cerita tentang pejabat pemerintah yang mendukung kelompok milisi yang kejam dan melanggar hukum karena takut akan penyergapan.
The freedom that the Iraqi press enjoyed immediately after the fall of Saddam Hussein’s regime was sweet but short-lived (Kim & Hama-Saeed, 2008) adalah ungkapan yang cocok menggambarkan kondisi jurnalisme di Irak era itu.
Irak telah menjadi tempat yang semakin berbahaya dan sulit bagi jurnalis untuk melaporkan tanpa rasa takut. Bahaya fisik yang dihadapi jurnalis termasuk ancaman pembunuhan dan penculikan oleh teroris, pemberontak Irak, dan milisi serta pembatasan hukum dan ancaman fisik yang diberlakukan oleh pemerintah Irak dan provinsi. Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ), mendaftarkan Irak sebagai tempat paling berbahaya dan paling mematikan di dunia bagi jurnalis pada tahun 2005. Jumlah jurnalis yang terbunuh di Irak sejak Maret 2003 berjumlah 125 hingga Januari 2008. Dari jurnalis yang terbunuh, 103 adalah jurnalis Irak. Selama periode yang sama, 48 rekan kerja media Irak lainnya yang bertugas sebagai penerjemah, pengemudi, dan fixer terbunuh. Partai politik, kelompok militan, pemberontak, dan gangster kriminal berada di balik sebagian besar pembunuhan dan penculikan jurnalis. Selain itu, angkatan bersenjata Irak dan militer AS diyakini bertanggung jawab atas beberapa kematian jurnalis Irak. Menurut CPJ/komite perlindungan Jurnalis (2008), 96 jurnalis Irak terbunuh oleh aksi pemberontak, termasuk baku tembak, bom bunuh diri, dan pembunuhan, sementara 16 jurnalis Irak terbunuh oleh militer AS. CPJ mengatakan tidak jelas apakah pasukan AS menargetkan jurnalis dengan sengaja.
Pada tahun 2007 saja ada sekitar 32 jurnalis tewas di Irak, bukti memburuknya situasi keamanan di negara tersebut. Karena masalah keamanan, media Barat dengan akses terbatas ke jalan-jalan Irak telah mempekerjakan banyak pekerja media Irak termasuk penulis, penerjemah, dan fotografer yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu jurnalis asing meliput tugas-tugas berbahaya (Blake, 2005; Palmer & Fontan, 2007). Seorang jurnalis mengatakan bahwa mesin propaganda politik dan sensor yang pernah dipegang oleh Rezim Saddam Hussein kini dikendalikan oleh berbagai partai politik dan sekte agama yang memaksa jurnalis untuk menerbitkan atau menyiarkan berita sebagai sarana untuk menyerang pesaing dan penantang mereka. Jurnalis lain mengatakan pengaruh media terhadap publik dan khususnya pejabat pemerintah terbatas. Sebagian besar pejabat pemerintah dan politisi Irak tidak terbuka terhadap kritik yang membangun.
Kesimpulan
Perang Teluk II (2003-2011) yang diawali dengan invasi Amerika Serikat ke Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein membawa dampak yang luas terhadap stabilitas politik, sosial, kesehatan, dan kebebasan pers di Irak. Meskipun AS mengklaim misinya bertujuan untuk membangun demokrasi, kenyataannya invasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan yang menyebabkan munculnya berbagai kelompok pemberontak, konflik sektarian antara Sunni dan Syiah, serta meningkatnya kekerasan bersenjata yang merenggut lebih dari 100.000 nyawa warga sipil. Dari segi kesehatan, sistem pelayanan medis di Irak semakin memburuk akibat konflik berkepanjangan, korupsi, serta maraknya perdagangan obat-obatan ilegal.
Selain itu, perang ini juga mengubah lanskap media Irak. Meskipun kejatuhan Saddam Hussein membawa harapan bagi kebebasan pers, jurnalis di Irak tetap menghadapi ancaman dari kelompok militan, pemerintah, dan aktor-aktor politik lainnya, yang mengakibatkan banyak kasus sensor dan kekerasan terhadap wartawan. Secara keseluruhan, dampak Perang Teluk II terus dirasakan hingga hari ini. Perang ini menunjukkan bahwa perubahan rezim melalui kekuatan militer tanpa strategi rekonstruksi yang jelas dapat membawa konsekuensi yang lebih buruk daripada kondisi sebelum perang.
Daftar Pustaka
Blake, M. (2005). In the Deadly Cauldron of Iraq, Even the Arab Media Are Being Pushed Off the Story. Columbia Journalism Review, 43(6), 8-16.
Geneva Declaration Secretariat. (2008). Global burden of armed violence. Geneva: Geneva Declaration Secretariat, 174.
Habib, A.-F. (2024). E-modul Sejarah Asia Barat Daya, 51-53.
Hicks, M.H. et al. (2009) .The weapons that kill civilians-deaths of children and noncombatants in Iraq, 2003. New England Journal of Medicine, 360(16), 1585-1588.
Hicks, M.H.-R. et al. (2011). Violent deaths of Iraqi civilians, 2003–2008: Analysis by perpetrator, weapon, time, and location. PLoS Medicine, 8(2), 1-15.
Iraq Body Count. Iraq Body Count database. Diakses dari http://www.iraqbodycount.org pada tanggal 1 Januari 2025.
Iswara, A.J. (2022). Sejarah Perang Irak vs Amerika: Awal Invasi, Tewasnya Saddam Husein. Diakses dari https://indeks.kompas.com/profile/2014/Aditya.Jaya.Iswara pada tanggal 31 Desember 2024.
Kim, H.S. & Hama-Saeed, M. (2008). Emerging Media in Peril: Iraqi journalism in the post-Saddam Hussein era. Journalism Studies, 9(4), 578-594.
Najjar, O.A. (2004). The Middle East and North Africa, in de Beer, A.S. & Merrill, J.C. (eds.) Global journalism: topical issues and media systems. Boston: Allyn & Bacon.
Palmer, J. & Fontan, V. (2007). Our ears and our eyes: Journalists and fixers in Iraq. Journalism. 8(1), 5-24.
Sinjari, H. (2006). The Iraqi press after liberation: Problems and prospects for developing a free press. In Arab Media in the Information Age, Abu Dhabi, UAE Emirates Center for Strategic Studies and Research.
Yuan, S. (2023). Health and the invasion of Iraq: 20 years later: The legacy of the US-led invasion is still being felt across Iraqi society. The Lancet, 401, 891-892.

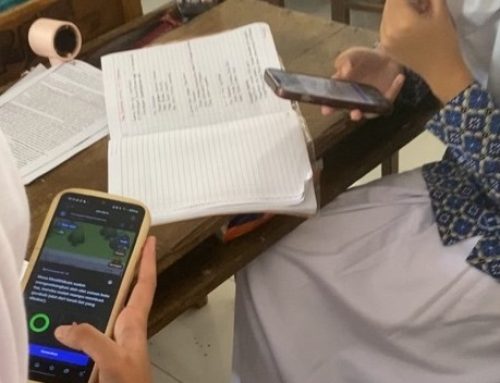
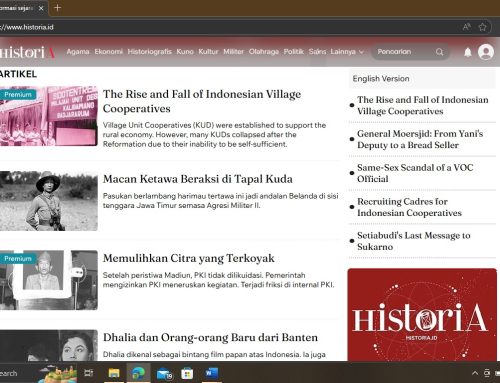


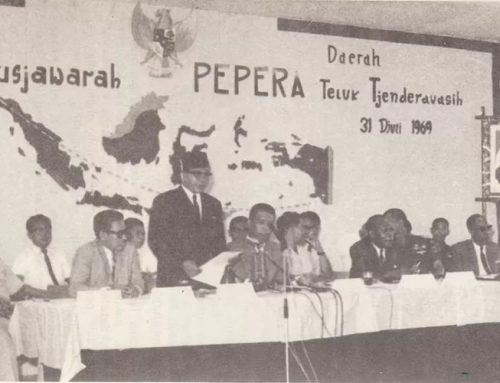
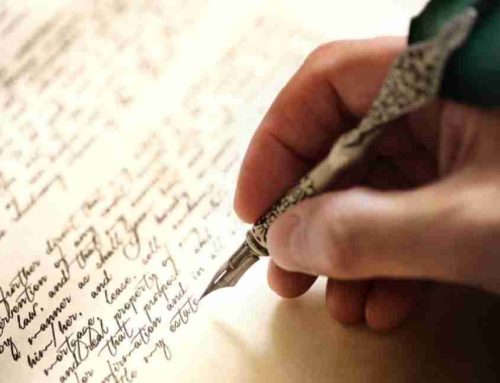



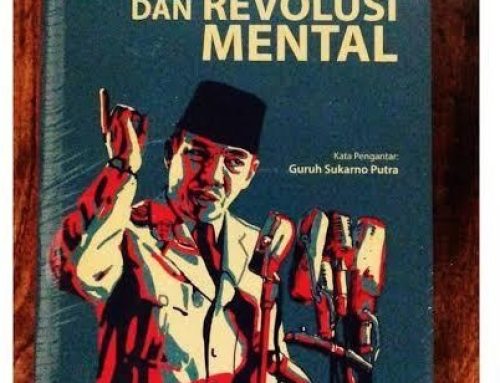



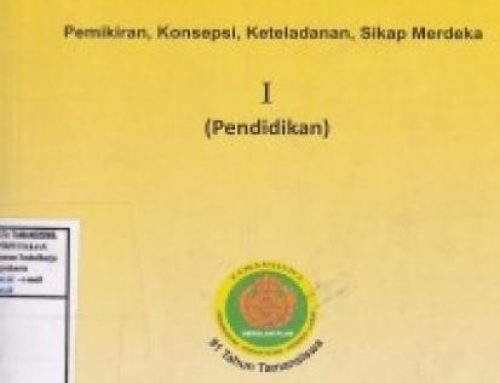


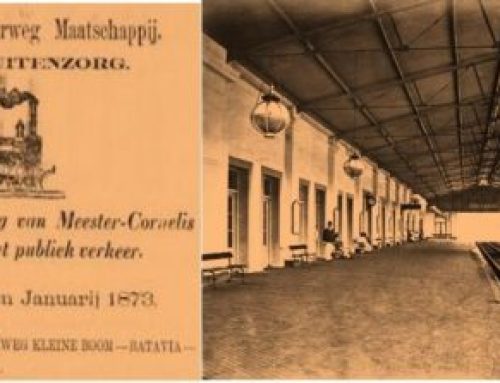

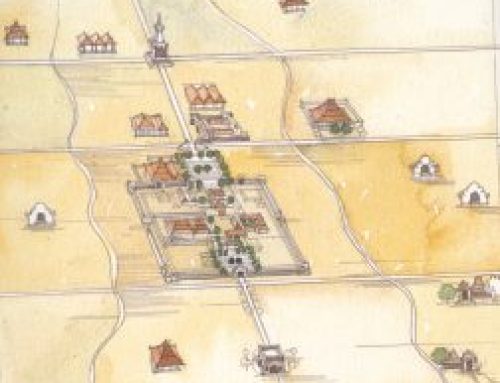
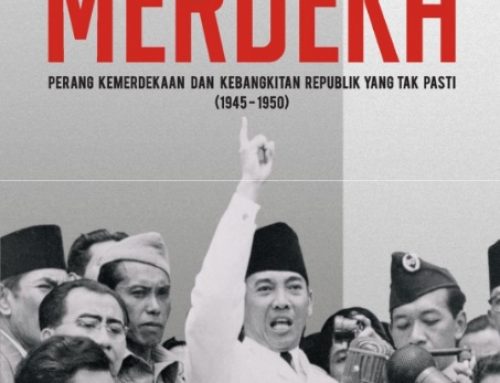


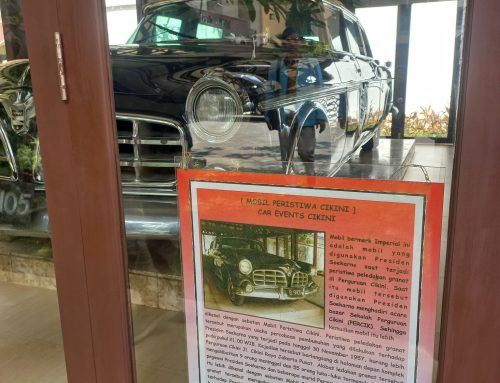





sangat bermanfaat