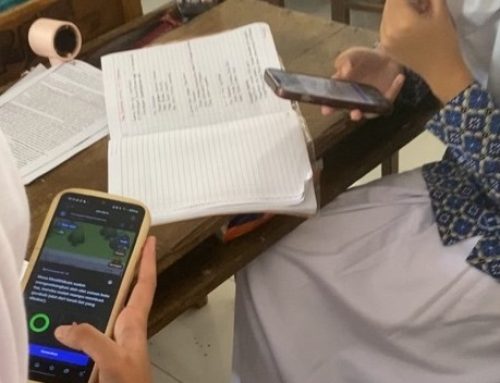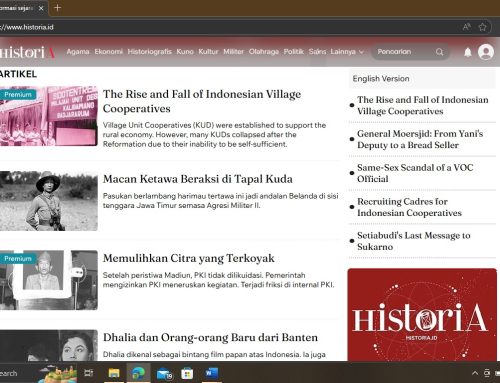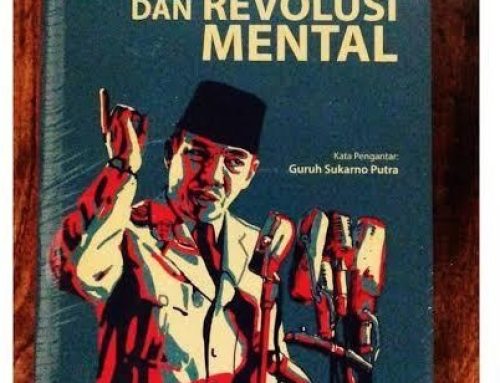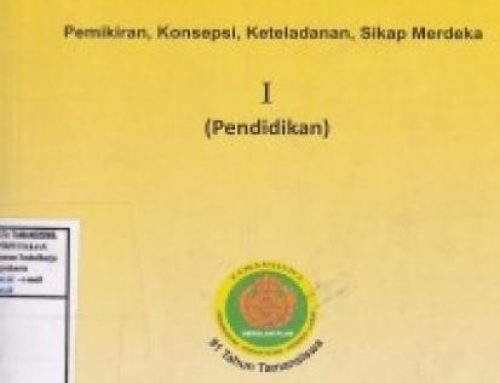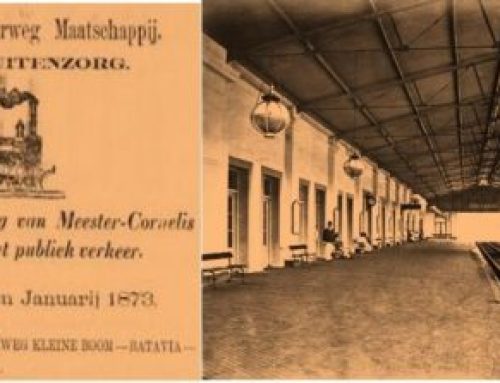Oleh: Muhimatul Choiriyah (Siswi Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus, Jawa Tengah)
*Artikel ini merupakan karya tulis yang sudah pernah diikutkan Lomba Penulisan Essay yang diselenggarakan oleh HMP Ganesha Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Juni 2024 dan berhasil meraih Juara 3.
Pendahuluan
Toleransi merupakan sebuah kunci yang harus selalu diterapkan dalam setiap keberagaman yang ada. Dunia mengakui bahwa Indonesia adalah negara multikultural yang memiliki beragam bentuk perbedaan, seperti adat istiadat, kesenian, etnis, sampai dengan kebudayaan. Keberagaman sosial dan budaya yang ada bisa saja memicu sebuah konflik diferensiasi antar kelompok hingga dapat mengancam runtuhnya persatuan dan kesatuan. Namun sebaliknya, keberagaman tersebut dapat membentuk sebuah bagian yang dapat terjalin indah apabila masyarakatnya menerapkan sikap saling menghormati dan menghargai (Atabik, 2016). Sikap toleransi di Indonesia sudah diterapkan bahkan sejak zaman nenek moyang dahulu, mereka cenderung toleransi dengan menjalin kerja sama dalam bidang perdagangan.
Disebutkan, Indonesia merupakan Negara yang menjadi titik kumpul bertemunya para pedagang luar (melting pot) dengan pluralisme etnis, mulai orang Arab, etnis Tionghoa, maupun Eropa dengan ragam agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakatnya, baik Islam, Kristen, Katholik, Konghucu dan Budha (Hartono dan Handinoto, 2009). Pendatang luar tersebut datang ke Indonesia untuk membeli sejumlah rempah-rempah Nusantara. Mereka sangat disambut dengan baik oleh para pribumi setempat
Salah satu daerah titik kumpul mendaratnya para pendatang luar yang ingin berniaga ke Nusantara adalah kota Lasem. Lasem dalam lintas sejarah masa lampau sangatlah inversi dengan Lasem yang sekarang. Pada masa kolonial, Lasem merupakan sebuah kota yang tersohor sebagai pusat perdagangan oleh warga non-local, sebelum akhirnya dipindah statusnya menjadi kecamatan pada Tahun 1750. Dahulu Lasem dikenal sebagai kota kecil yang cukup ramai sebagai silang maritime di pantai utara Jawa, familiar sebagai kota pusaka yang memiliki keanekaragaman berupa warisan budaya yang diwariskan dari garis keturunan para pendatang luar. Sebagai kota kecil, Lasem telah teruji punya pengalaman panjang dalam merajut harmoni dalam bingkat toleransi keberagaman antara etnis asli dengan bangsa pendatang. Di mana para entitas pendatang tersebut sangat menghormati adat-istiadat yang dilakukan oleh warga setempat begitupun sebaliknya, masyarakat lokal Lasem juga menghormati adat-istiadat pendatang luar. Toleransi inilah yang memunculkan harmonisasi antar etnis sehingga tidak adanya diferensiasi antar golongan (Ahmad Atabik, 2016.)
Bukti toleransi yang telah menjalar di kota Lasem dibuktikan dengan adanya hasil kebudayaan yang terdapat coretan akulturasi bangsa pendatang luar seperti etnis Arab dan Tionghoa yaitu adanya Poskamling yang terdapat ornamen berupa tulisan Arab dan Tionghoa. Poskamling ini berada di dekat pesantren yang ada di Lasem. Disebutkan, hasil akulturasi budaya ini merupakan perwujudan adanya ajaran Islam yang masuk melalui pesantren. Selain poskamling, terdapat bangunan Masjid Mbah Sambu yang merupakan hasil akulturasi arsitektur Tionghoa, Timur Tengah, dan Jawa. Hasil kebudayaan lain yaitu bangunan Klenteng Gie Yong Bio dan Klenteng Cu An Kiong yang juga termasuk ke dalam bukti sejarah bahwa masyarakat lokal dapat berbaur dan bersosialisasi dengan masyarakat Tionghoa (Nurhajarini et. al., 2015).
Karya sejenis pernah digarap oleh Ahmad Atabik (2016) dalam jurnal berjudul “Harmonisasi Kerukunan Antar Etnis Dan Penganut Agama Di Lasem”. Jurnal dari Ahmad Atabik membahas mengenai kerukunan antar agama dan etnis yang ada. Namun, lebih spesifik mengenai kerukunan antar umat beragama sehingga melahirkan suatu kebudayaan dan pluralitas dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antar etnis di Indonesia sudah terjalin lama jauh sebelum Indonesia merdeka bahwa sejak era kerajaan- kerajaan Hindu-Budhha. Faktor utama terbentuknya masyarakat kosmopolit yaitu amalgamasi (perkawinan silang), penerimaan terhadap kebudayaan asing, hingga terbukanya ruang-ruang social yang dengan hasil kebudayaan baru tanpa melupakan akar budaya asal. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Atabik belum membahas secara spesifik mengenai hasil kebudayaan yang dihasilkan seperti akulturasi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah bacaan yang menjelaskan lebih spesifik mengenai ekspresi toleransi yang ada di kota pusaka Lasem beserta hasil yang lebih spesifik dan ringkas dengan tajuk “Merajut Nusantara : Ekspresi Toleransi di Tengah Keberagaman Masyarakat Kota Pusaka Lasem dalam Lintas Sejarah” yang diterapkan sebagai suatu dasar pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan.
Berkaca pada uraian diatas mengenai bukti sejarah masyarakat lokal dalam berbaur dengan para pendatang luar, maka diperlukan suatu landasan fakta yang dapat mengeksplorasikan adanya toleransi dan pencampuran budaya (akulturasi) antara masyarakat lokal di kota pusaka Lasem dengan masyarakat pendatang luar seperti etnis Tionghoa dan Arab. Mula-mula penulis menjelaskan mengenai pluralitas yang ada, kemudian sebuah toleransi yang terjalin di kota Lasem dalam lintas sejarah masa lampau beserta hasil kebudayan yang ada, kemudian dieksplorasikan dengan urgensi membangun toleransi di tengah masyarakat sosio-kultural Indonesia.
Pembahasan
Sebagai wilayah mendaratnya kapal-kapal milik pendatang luar, wilayah Lasem tentu sangatlah tersohor dengan keberagaman dan toleransi yang ada. Dalam lintas sejarah masa lampau, Lasem merupakan saksi bisu dalam masa keemasan perdagangan yang ada di Nusantara. Pendatang luar yang datang ke daerah Lasem bertujuan untuk melakukan kegiatan berniaga sekaligus membeli sejumlah rempah-rempah Nusantara. Disebutkan bahwa etnis Tionghoa datang ke Nusantara sejak abad pertama masehi dan telah mengenal jawa, hal tersebut telah dirangkumkan dalam catatan Tionghoa tentang terdamparnya seorang pendeta Budha yakni Fa-Hsein yang bernama lain Fa-Hian/Fa Xian dan Hwui Ning disebuah pulau bernama „Ya-Wa-Di’ yang merupakan transliterasi Tionghoa dalam teks Sansekerta untuk menyebut Jawa(Komunitas Rumah Buku Lasem, 2014). Etnis Tionghoa yang tiba dan mendarat di daerah Lasem memulai tinggal di sebuah wilayah tepi sungai Babagan, tepatnya di desa Galangan (Ayuningrum, 2017).
Motif utama kedatangan etnis Tionghoa ke Pantai Utara Jawa, termasuk Lasem adalah motif ekonomi untuk melangsungkan perniagaan. Para pedagang ini diketahui telah melakukan perjalanan dengan berlayar di berbagai wilayah di pulau Jawa, dan kemudian mendarat di sekitar wilayah Tuban dan Gresik, ada juga yang memilih mendirikan kawasan tempat tinggal permanen dan menikahi pribumi setempat lalu menetap selamanya. Adanya masyarakat Tionghoa yang tinggal menetap inilah yang kemudian menciptakan suatu kebudayaan baru dan diadopsi sebagai tanpa meninggalkan unsur-unsur budaya lama dari Tiongkok. Selain itu, para imigran Tionghoa yang bermukim dan menetap di Lasem selama kurang lebih dua hingga tiga generasi dan menjalin hubungan sosial bersama masyarakat lokal yang ada di Lasem, sehingga telah menyatu dan terbiasa dengan adat dan istiadat di mana mereka berada. Akulturasi itu dapat dijumpai pada aspek kesenian Jawa yang ada di Lasem, seperti seni batik yang menggunakan motif khas batik tulis Lasem. Sebagian dari etnis Tionghoa yang telah tinggal permanen di Lasem sudah melakukan amalgamasi dengan penduduk local (Komunitas Rumah Buku Lasem, 2014).
Sebagaimana dijelaskan oleh Unjiya pada tahun 2014, populasi masyarakat Tionghoa pada awal abad ke 19 sangatlah melaju pesat. Hal itu menyebabkan seiring berkembangnya zaman yang ada, maka muncul penstrataan sosial yang berdasarkan karakter ras, sehingga menjadikan masyarakat Tionghoa berpikir untuk mendirikan satu komunitas sosial masyarakat yang bermukim di sebuah wilayah yang disebut “Kampoeng Pecinan”. Masyarakat Tionghoa yang tinggal di daerah Pecinan Lasem dianggap memiliki keunikan karena memiliki perbedaan kultural maupun religi dengan penduduk asli Jawa di Lasem, lalu mereka membuat ruang hidup (kawasan) yang terpisah dengan setempat.
Kota Lasem pada lintas sejarah masa lampau memiliki berbagai cerita mengenai harmonisasi toleransi yang telah terjalin. Disebutkan, Lasem telah menjadi kadipaten beberapa kerajaan Nusantara terdahulu, seperti Kerajaan Majapahit yang termasuk dalam salah satu kerajaan Hindu-Budha di Nusantara yang terbesar dan terkuat dalam sejarah, dan juga kerajaan Demak yang setelahnya bisa menggeser otoritas Kerajaan Majapahit yang telah berkuasa sejak lama. Di awal abad XIV, kota pusaka Lasem berada merupakan vassal Majapahit yang berdiri sejak abad XIII dan runtuh di abad XV karena adanya konflik internal kerajaan dan bergesernya episentrum kekuasaan ke Kerajaan Islam Demak. Salah satu sumber berita mengenai nama Lasem menyebutkan bahwa Lasem telah menjadi semacam tanah bawahan Kerajaan Majapahit sejak tahun 1273 Saka atau 1351 Masehi. Daerah kekuasaan ini dulunya dipimpin oleh Dewi Indu, yaitu kemenakan Prabu Hayam Wuruk, penguasa Majapahit (Kamzah, 1858). Tome Pires, seorang pengelana portugis yang pernah singgah ke Indonesia menyebutkan bahwa wilayah Rembang menuju kea rah Timur sampai Tuban, banyak dijumpai masyarakat pengrajin kayu (Handinoto, 2015: 6-7).
Setelah era dibawah kekuasaan Majapahit berakhir, Lasem tetap eksis menjadi kadipaten binangun pada abad ke 15. Kemudian disusul dengan menjadi bagian dari Kerajaan Mataram Islam pada awal abad ke 16, pada saat itu terciptalah era baru yaitu masa Islam- pengaruh Eropa (kolonial). Kerajaan Lasem diubah menjadi Kadipaten Lasem di bawah pimpinan Adipati Tedjokusuma tahun 1628 semasa kekuasaan VOC di kepulauan Nusantara ini. Tahun 1750, pusat kota yaitu kadipaten Lasem dipindah ke Rembang sebelum akhirnya pada tahun 1751 wilayah Lasem ditetapkan menjadi kecamatan. Setelah dipindahnya kabupaten ke Rembang, aktivitas harian dan perkembangan di Lasem makin tidak terurus.
Banyak pelabuhan-pelabuhan yang terbengkalai, begitupun kawasan Pecinan yang makin lama makin ditinggalkan oleh penghuninya. Kebanyakan dari mereka memili keluar dari Lasem dan memulai hidup baru di kawasan Pecinan di bandar-bandar besar, seperti Surabaya, Jakarta dan Semarang. Lambatnya perkembangan kota Lasem tentu memiliki sisi positif. Positifnya, kecamatan Lasem tidak mengalami modernisasi dan tetap kental dengan peninggalan-peninggalan budayanya. Namun dalam kegiatannya, kecamatan Lasem yang posisinya yang berada di perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur mau tidak mau, kecamatan ini juga terkena imbasnya (Handinoto, 2006)
Di antara seluruh corak keberagaman yang telah hadir di Lasem, corak kebudayaan masyarakat Tionghoa yang paling kental dan menyatu dengan tradisi masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya klenteng-klenteng peninggalan pada masa kolonial maupun jauh sebelum Indonesia merdeka, seperti Klenteng Cu An Kiong yang dikenal sebagai salah satu klenteng tertua yang ada di Jawa. Hingga saat ini, tak jarang kita menemukan bangunan- bangunan kuno yang memiliki ornamen-ornamen khas kebudayaan Tionghoa. Sentuhan perpaduan atau akulturasi ini tentu merupakan penghargaan dari masyarakat Lasem untuk menghargai kebudayaan-kebudayaan yang pernah singgah di Lasem (Hartono dan Handinoto, 2006).
Harmoni Toleransi Masyarakat Lasem dengan Etnis Tionghoa
Sejarah mencatat bahwa pada awal abad ke 14 hingga abad 16 telah terjadi interaksi sosial atau peristiwa yang melahirkan sebuah toleransi antara penduduk asli Lasem dengan imigran Tionghoa. Meskipun interaksi tersebut tentu mengalami pasang surut dalam keberjalanannya, namun harmoni dan toleransi antar penduduk senantiasa terjalin dengan apik. Salah satu harmoni toleransi dapat dilihat dari adanya penjajahan di seluruh wilayah Indonesia. Penjajahan di tanah Jawa yang dilakukan oleh Belanda (VOC) merupakan hal yang tidak disangka oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kedatangan awal Belanda ke Jawa pada tahun 1596 disebutkan hanya untuk berniaga dan mencari komitas rempah-rempah yang dihasilkan di bumi Nusantara. Namun tujuan awal yang mereka laksanakan berbelok menjadi keinginan untuk menjajah nusantara dan menguasai secara penuh wilayah yang kaya akan rempah-rempah tersebut. Perlawanan pribumi terhadap para penjajah terjadi di berbagai daerah, termasuk Lasem (Ahmad Atabik, 2016).
Tahun 1979, VOC melangsungkan serangan ke Kota Lasem yang masih berada di luar hagemoni mereka, hal itu dilakukan untuk memonopoli aktivitas niaga di wilayah pantai utara Jawa. Serangan hebat yang dilakukan VOC tersebut terjadi secara berlarut-larut hingga menyebabkan terbunuhnya penguasa Lasem saat itu, Raden Mas Wingit. Upaya perlawanan rakyat Lasem terhadap VOC dimulai sejak masa Amangkurat IV (1717-1726) di era Mataram Islam. Waktu itu kaum santri bersama etnis Tionghoa bersatu teguh dalam melawan penjajah. Tahun 1740 terjadi VOC melancarkan seragan besar-besaran pada orang-orang Tionghoa di Batavia. Peristiwa ini, kini dikenal sebagai peristiwa Angke yang memakan ribuan korban jiwa. Akibat pembantaian tersebut, kurang lebih 1000 orang Tionghoa di Batavia bermigrasi dan mencari suaka ke Lasem. Pelarian orang-orang Tionghoa dari Batavia di Lasem ini umumnya menggeluti profesi di bidang kepelabuhan, pedagang, maupun buruh kasar yang dikenal memili etos kerja tinggi. Kedatangan mereka tentunya diterima baik oleh masyarakat setempat, khususnya sesama orang Tionghoa.
Namun, semarak perdamaian dan perubahan di Lasem itu tidak berlangsung lama, peperangan dan pergolakan dengan para penjajah kembali terjadi. VOC lebih gencar membidik politik di daerah Rembang, daerah ini dianggap strategis, pusat perdagangan, dan daerah penghasil kayu jati yang berkualitas (Unjiya, 2014). Hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Lasem dalam melawan VOC, seperti api berkobar yang kemudian ditiup, semangat perjuangan mereka menggema dimana-mana. Diawali dengan berjuang di Pantai Bonang sampai dengan Pelabuhan Dasun, pertempuran pecah antara Laskar Lasem yang diwakili oleh kaum santri dan masyarakat etnis Tionghoa dengan legion di Rembang. Perang ini disebutkan hampir terlaksana selama tiga bulan lamanya. Peperangan yang terjadi selama tiga bulan itu menelan banyak korban dari kedua belah pihak yang bertikai.
Meskipun peperangan-peperangan yang terjadi telah dimenangkan oleh Belanda, namun semangat toleransi dan kepedulian antar sesama sangatlah terjalin indah di Lasem. Bersatunya etnis Tionghoa dan masyarakat setempat untuk melawan penjajah merupakan sebuah symbol harmonisasi dan pluralitas yang patutnya harus selalu dikenang dan diabadikan. Peristiwa- peristiwa yang terjadi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu sejarah yang dapat diterangkan kembali di sekolah, sehingga kejadian tersebut tidak dilupakan begitu saja.
Penutup
Sejarah mencatat bahwa pada awal abad ke 14 hingga abad 16 telah terjadi interaksi sosial atau peristiwa yang melahirkan sebuah toleransi antara penduduk asli Lasem dengan imigran Tionghoa. Meskipun interaksi tersebut tentu mengalami pasang surut dalam keberjalanannya, namun harmoni dan toleransi antar penduduk senantiasa terjalin dengan apik. Salah satu harmoni toleransi dapat dilihat dari adanya penjajahan di seluruh wilayah Indonesia. Penjajahan di tanah Jawa yang dilakukan oleh Belanda (VOC) merupakan hal yang tidak disangka oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kedatangan awal Belanda ke Jawa pada tahun 1596 disebutkan hanya untuk berniaga dan mencari komitas rempah-rempah yang dihasilkan di bumi Nusantara. Namun tujuan awal yang mereka laksanakan berbelok menjadi keinginan untuk menjajah nusantara dan menguasai secara penuh wilayah yang kaya akan rempah-rempah tersebut. Perlawanan pribumi terhadap para penjajah terjadi di berbagai daerah, termasuk Lasem (Ahmad Atabik, 2016).
Tahun 1979, VOC melangsungkan serangan ke Kota Lasem yang masih berada di luar hagemoni mereka, hal itu dilakukan untuk memonopoli aktivitas niaga di wilayah pantai utara Jawa. Serangan hebat yang dilakukan VOC tersebut terjadi secara berlarut-larut hingga menyebabkan terbunuhnya penguasa Lasem saat itu, Raden Mas Wingit. Upaya perlawanan rakyat Lasem terhadap VOC dimulai sejak masa Amangkurat IV (1717-1726) di era Mataram Islam. Waktu itu kaum santri bersama etnis Tionghoa bersatu teguh dalam melawan penjajah. Tahun 1740 terjadi VOC melancarkan seragan besar-besaran pada orang-orang Tionghoa di Batavia. Peristiwa ini, kini dikenal sebagai peristiwa Angke yang memakan ribuan korban jiwa. Akibat pembantaian tersebut, kurang lebih 1000 orang Tionghoa di Batavia bermigrasi dan mencari suaka ke Lasem. Pelarian orang-orang Tionghoa dari Batavia di Lasem ini umumnya menggeluti profesi di bidang kepelabuhan, pedagang, maupun buruh kasar yang dikenal memili etos kerja tinggi. Kedatangan mereka tentunya diterima baik oleh masyarakat setempat, khususnya sesama orang Tionghoa.
Namun, semarak perdamaian dan perubahan di Lasem itu tidak berlangsung lama, peperangan dan pergolakan dengan para penjajah kembali terjadi. VOC lebih gencar membidik politik di daerah Rembang, daerah ini dianggap strategis, pusat perdagangan, dan daerah penghasil kayu jati yang berkualitas (Unjiya, 2014). Hal itu tidak menyurutkan semangat masyarakat Lasem dalam melawan VOC, seperti api berkobar yang kemudian ditiup, semangat perjuangan mereka menggema dimana-mana. Diawali dengan berjuang di Pantai Bonang sampai dengan Pelabuhan Dasun, pertempuran pecah antara Laskar Lasem yang diwakili oleh kaum santri dan masyarakat etnis Tionghoa dengan legion di Rembang. Perang ini disebutkan hampir terlaksana selama tiga bulan lamanya. Peperangan yang terjadi selama tiga bulan itu menelan banyak korban dari kedua belah pihak yang bertikai.
Meskipun peperangan-peperangan yang terjadi telah dimenangkan oleh Belanda, namun semangat toleransi dan kepedulian antar sesama sangatlah terjalin indah di Lasem. Bersatunya etnis Tionghoa dan masyarakat setempat untuk melawan penjajah merupakan sebuah symbol harmonisasi dan pluralitas yang patutnya harus selalu dikenang dan diabadikan. Peristiwa- peristiwa yang terjadi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu sejarah yang dapat diterangkan kembali di sekolah, sehingga kejadian tersebut tidak dilupakan begitu saja.
Daftar Pustaka
Ayuningrum, D. (2017). Akulturasi Budaya Cina Dan Islam Dalam Arsitektur Tempat Ibadah Di Kota Lasem, Jawa Tengah. Sabda:
Jurnal Kajian Kebudayaan, 12(2), 122-135.
Handinoto & Hartono, S. (2006). Lasem; Kota Kuna yang Bernuansa China, Seminar Nasional Pemahaman Sejarah Arsitektur
Indonesia X, Arsitektur Pecinan Di Indonesia. Jurusan Arsitektur Unika Sugijapranata Semarang.
Handinoto. (2015). Lasem: Kota Tua Bernuansa Cina di Jawa Tengah, Yogyakarta: Ombak.
Komunitas Rumah Buku Lasem. (2014). Lasem: Sejarah Panjang Toleransi. Lasem: Elzam Berkah Utama
Nurhajarini, D. R., & Purwaningsih, E. (2015). Akulturasi lintas zaman di lasem: perspektif sejarah dan budaya (kurun niaga-sekarang).
Fibiona.
Riyanto, S., Mochtar, A. S., Alifah, A., Taniardi, P. N., & Priswanto, H. (2020). Lasem dalam rona sejarah Nusantara: sebuah kajian
arkeologis (pp. xiv-100). Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Shofiyah, E. H. F. (2021). Komunikasi Antar Budaya (Studi Kasus: Toleransi Antara Etnis Tionghoa dengan Etnis Pribumi Muslim di
desa Karangturi, Lasem, Rembang) (Doctoral dissertation, IAIN Kudus).
Unjiya, M. A. (2014). Lasem: Negeri Dampo Awang, Yogyakarta: Salmaidea.